Fimela.com, Jakarta Kita semua pernah punya pengalaman atau kisah tentang cinta. Kita pun bisa memaknai arti cinta berdasarkan semua cerita yang pernah kita miliki sendiri. Ada tawa, air mata, kebahagiaan, kesedihan, dan berbagai suka duka yang mewarnai cinta. Kisah Sahabat Fimela yang diikutsertakan dalam Lomba Share Your Stories Februari 2021: Seribu Kali Cinta ini menghadirkan sesuatu yang baru tentang cinta. Semoga ada inspirasi atau pelajaran berharga yang bisa dipetik dari tulisan ini.
BACA JUGA
Advertisement
***
Oleh: Yosi Prastiwi
Dulu saya pikir menerima kelebihan dan kekurangan pasangan adalah tips awet dalam hubungan pernikahan. Menerimanya satu paket lengkap sebagai manusia yang setara. Sebab saya juga punya kekurangan.
Tentu saja kekurangan yang saya maksud berkaitan dengan remeh temeh. Semacam kebiasaan hidup sebelumnya. Bukan hal prinsipil dalam pernikahan.
Misalnya soal kebiasaan si dia menarik pakaian dari tumpukan yang rapi jali. Kesulitannya menemukan benda-benda miliknya sendiri seperti kunci motor, earphone sampai dompet. Sampai dia yang lupa menutup odol setelah menggosok gigi.
Atau perbedaan pola pikir pria dan wanita yang memang punya kecenderungan berbeda dari sononya. Dia yang otaknya dominan kiri dan fokus menyelesaikan masalah. Saya yang berputar-putar dengan otak kanan dan punya banyak cadangan kata tiap hari.
Mau tidak mau kami harus saling adaptasi. Meyakini bahwa memang tidak ada pasangan sempurna di dunia. Yang ada perilaku saling menerima dan melengkapi. Patah hati karena sikapnya yang kurang peka lalu besoknya jatuh hati lagi karena perhatian kecilnya. Mungkin ini yang dinamakan hal-hal menggemaskan dalam rumah tangga.
Masalah yang lebih rumit hadir ketika kamu memiliki anak. Ternyata kami begitu amatir sebagai orangtua. Bukan saja perkara teknis merawat bayi yang membuat kami kelimpungan. Tapi juga mengasuh dan mendampingi tumbuh kembangnya dengan baik.
Advertisement
Menjadi Orangtua
Yang pertama, kami berdua dibesarkan dengan pola asuh keluarga yang berbeda. Adat, budaya dan lingkungan yang tidak sama. Saya dari suku Jawa dengan latar belakang muslim abangan. Suami dibesarkan pada suku Bugis yang lebih kental nilai religiusnya daripada keluarga saya.
Kami memang menyepakati nilai-nilai kebaikan yang akan kami ajarkan sepanjang mengasuh anak. Kami juga berupaya mengasuh lebih baik daripada orangtua kami. Bertekad tidak meniru beberapa sikap dan pola asuh orangtua yang kami sadari keliru di kemudian hari.
Misalnya pola asuh keluarga yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Menyerahkan segala beban pekerjaan rumah tangga pada perempuan saja. Sikap wajib mengalah pada sosok kakak terhadap adiknya tanpa peduli siapa yang salah. Melabeli anak dengan julukan negatif. Mencubit atau memukul anak. Berbohong pada anak. Tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan anak. Dan banyak sekali tumpukan pengalaman pengasuhan yang buruk di masa lalu.
Sayangnya, tekad saja tidak cukup. Setulus apa pun saya mencintai anak-anak, kadang kala saya kelepasan. Otak saya otomatis melakukan hal serupa pada beberapa situasi bersama anak. Sekeras apa pun saya mencoba, saya kembali mengulang pola asuh orangtua terhadap saya.
Wajar sih. Dua puluh tahun tinggal dan diasuh orang tua, membuat saya melakukan respons yang sama. Seperti mesin fotokopi. Dulu kalau saya menangis, orangtua mengalihkan dengan sesuatu yang menyenangkan, misal permen. Sekarang punya anak, kalau nangis dikasih gadget. Tidak pernah saya biarkan dia menangis lama-lama. Atau saya tanyakan perasaannya.
Yang kedua, saya tidak pernah belajar ilmu pengasuhan sebelumnya. Saya tidak memiliki cara lain dalam mengasuh selain apa yang orang tua saya lakukan. Bisa saja saya membaca artikel parenting, tapi sungguh itu tidak banyak membantu. Saya, Anda, dan siapa pun butuh benar-benar belajar dan bersekolah sebelum mengasuh anak.
Saya beruntung. Di tengah kegalauan baru melahirkan anak ketiga, saya masuk grup belajar yang dimentori psikolog dan praktisi parenting. Ini grup berbayar yang anggotanya bebas bertanya apapun 24 jam. Di sinilah saya menyadari kedua situasi saya di atas.
Terus Berproses dan Belajar Hal-Hal Baru
Mengubah pengasuhan orangtua yang terlanjur lekat pada saya tentu tidak mudah. Selain ilmu, saya menyadari satu hal yang krusial tentang diri saya. Saya memiliki inner child.
Bayang-bayang anak kecil dalam diri saya ini kerap menganggu ketika saya mengasuh. Anak kecil dalam diri saya merasakan sesuatu yang belum tuntas. Kasih sayang, perhatian, cinta, penerimaan. Saya belum utuh mendapatkan. Dan kini dituntut harus memberikan setulusnya pada anak?
Bagaimana bisa?
Saya disadarkan tentang luka pengasuhan di masa lampau. Saya pun tidak bisa menyalahkan orangtua sepenuhnya. Era itu belajar parenting belum menjadi kebutuhan.
Yang bisa saya lakukan adalah memaafkan mereka. Menerima kesalahan mereka. Ini kunci penting sebelum mulai mengasuh.
Lalu belajar mencintai diri sendiri. Luka-luka pengasuhan itu tidak membuat saya membenci orangtua. Melainkan membuat saya rendah diri, merasa tidak berharga, tidak diterima dan tidak penting kehadirannya.
Konon, isi cangkir tergantung dari isi teko yang menuangnya. Sebelum saya mencintai orang lain, baik pasangan maupun anak-anak, saya perlu menerima diri saya terlebih dulu. Tidak mudah, tapi saya berproses. Dukungan pasangan salah satunya.
Saya tidak lagi mudah depresi. Saya bisa menyampaikan perasaan lebih gamblang. Saya menemukan kepercayaan diri pada titik ini. Setelah menerima diri dan memaafkan masa lalu, saya lebih mudah mencintai keluarga.
Ingat, kamu berharga. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti hatimu selain atas izinmu. Itu hatimu, kamu yang berkuasa mengelolanya. Kamu yang memilih untuk bahagia, bukan orang lain.
#ElevateWomen
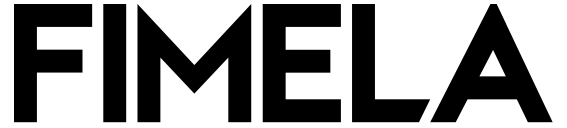
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/1783547/original/015968300_1743066229-WhatsApp_Image_2025-03-27_at_16.01.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3057434/original/090683400_1582345416-shutterstock_1605281122.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3336458/original/031610900_1609292003-anak_kembar.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3354036/original/013750900_1611118626-bacaan_anak.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5465029/original/070699400_1767756811-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share__1_.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441350/original/073314500_1765504657-Tanya_Jawab_tentang_Nutrisi_di_1000_Hari_Pertama_Kehidupan_Anak.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441342/original/057711100_1765504279-Novel_Tiga.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431754/original/099709900_1764747157-WhatsApp_Image_2025-12-03_at_14.16.57_a3e4af2d.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5436821/original/022017900_1765186364-pexels-anna-pou-8329902.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3286636/original/093458900_1604471471-pexels-photo-4239011.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5436788/original/050733500_1765773245-Depositphotos_812580836_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441338/original/025527600_1765504149-Every_Day_is_A_Sunny_Day_When_I_Am_with_You.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2981728/original/010002700_1575023913-ben-white-vJz7tkHncFk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5434360/original/073007100_1764924578-pexels-vanessa-loring-5082373.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2995662/original/061514500_1576230464-juliana-malta-YwutubGmzSU-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5434439/original/085265100_1764927392-Depositphotos_835881408_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452175/original/053343100_1766388567-front-close-view-young-attractive-female-white-t-shirt-doing-make-up-with-slight-smile-pink-background.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5469801/original/027902300_1768185276-Screenshot_2026-01-12_at_09.32.26.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5022084/original/003655100_1732601966-apa-itu-oktan-bensin.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3150829/original/023474200_1591940789-brooke-lark-3A1etBW5cBk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5468218/original/070585000_1767944463-SnapInsta.to_247420157_2936691426660037_1523452434376695794_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5466866/original/095592700_1767857119-Depositphotos_123039890_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4324626/original/083226200_1676436372-priscilla-du-preez-L3lznpRPZbI-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5290798/original/058084800_1753157649-Depositphotos_724888352_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5181762/original/017749800_1744002644-Depositphotos_414070156_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5466287/original/025720300_1767841427-IMG_7934-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5417131/original/095682400_1763522186-Depositphotos_565671370_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5318556/original/073929800_1755489328-Depositphotos_706629402_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5282172/original/002632900_1752467860-Depositphotos_712660360_XL.jpg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470465/original/083680600_1768206103-photo-grid_-_2026-01-12T150821.724.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069280/original/062057800_1735296697-asian-mother-are-quarreling-daughters-home-family-relationship-concept.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5453113/original/001165000_1766470409-WhatsApp_Image_2025-12-23_at_12.19.35__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5335102/original/017863700_1756786957-little-desperate-girl-looking-panic-holding-her-head-with-both-hands.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5271472/original/044739400_1751512018-front-view-two-sisters-playing-home-with-toys.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5468300/original/009638000_1767946480-Depositphotos_485939088_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452876/original/099231900_1766461807-FIMELA_FASHION_-_Lanvin_at_Its_Most_Glam__IG_Feed__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411718/original/027752400_1763019573-hujan.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5461229/original/053076900_1767348851-IMG_7216__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5152380/original/075031200_1741247115-KELIMUTU_OPSI_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470699/original/022373200_1768216488-Presiden_Prabowo_berkunjung_ke_IKN.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4843081/original/038659200_1716722680-Pidato_Megawati_Tutup_Rakernas_V_PDIP-ANGGA_5.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470654/original/001785900_1768213679-Tiga_tersangka_pengiriman_sabu_yang_dibongkar_polisi_di_Pelabuhan_Bakauheni.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5321481/original/056674800_1755674421-hemat_2.jpg)
![Menetap di luar negeri bersama sang suami, Tyler Bigenho, Aurelie membagikan deretan potret maternity shoot yang langsung mencuri perhatian publik. [@aurelie].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KeHYyLpjeVNWJZmoawB6Z6s91lI=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470346/original/015730200_1768203066-SnapInsta.to_613131607_18546847975020952_3433188746403215401_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470559/original/000337700_1768210483-pexels-majesticaljasmin-14664623.jpg)
![Reuni manis terjadi di karpet merah Golden Globe Awards 2026 saat Selena Gomez dan Miley Cyrus tampil berdampingan dengan aura bintang yang sama-sama kuat. [Dok/MTV].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/BlndG3bVQJHghcg0uX8y4I19g-E=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470236/original/056305500_1768200976-Web_Photo_Editor__8_.jpg)