Fimela.com, Jakarta Masih segar ingatan kita kasus Milen Cyrus beberapa waktu lalu. Ia tertangkap karena kasus narkoba. Namun yang lebih menjadi sorotan adalah, saat pihak berwajib memutuskan untuk menempatkannya di sel pria, sesuai gender yang tertera di kartu identitas Milen. Secara hukum memang tak ada yang salah dengan keputusan polisi, namun banyak pihak menganggap tindakan ini tidak tepat. Berbagai tanggapan muncul di sosial media, tak sedikit yang menyayangkan keputusan tersebut (walau kini akhirnya Milen dimasukkan ke sel khusus dan sendirian) dengan alasan menyalahi hak asasi.
Jujur saya pribadi juga merasa menempatkan Milen ke sel pria tidaklah bijak. Di luar konteks keagamaan atau hukum, di mata saya sebagai orang awam, Milen merasa dirinya adalah perempuan, dan saya (mencoba) merefleksikan perasaannya ke diri saya (yang juga perempuan). Jika saya melakukan kesalahan dan ditempatkan di sel pria, itu pasti menjadi mimpi buruk buat saya.
Advertisement
Cukupkah Menilai Gender Seseorang dari Kartu Identitas Semata?
Saya melakukan wawancara dengan Ika Putri Dewi, S.Psi.,Psikolog. Beliau kini menjadi salah satu psikolog di Yayasan Pulih, yang fokus pada pemulihan korban kekerasan. Ika sapaan akrabnya mengungkap bagaimana identitas gender setiap individu terbentuk.
Secara fisik, identitas gender tentu dilihat dari kelamin seseorang, namun dalam ilmu psikologi, gender seseorang juga bisa dilihat dari penghayatan mereka terhada gendernya sendiri.
“Ada yang melihat dirinya berbeda dengan seks biologisnya dan identitas gender tersebut disebut transgender.Namun bisa dilakukan pendampingan psikologis (wawancara, observasi atau pendampingan) mengenai penghayatan seseorang terhadap identitas gendernya. Hal ini diharapkan membantu pihak yang terkait dapat memahami bahwa seseorang bisa memiliki identitas gender yang berbeda dengan identitas seks biologisnya, sehingga paling tidak membuat pihak terkait dapat memahami dampak yang timbul jika seseorang ditempatkan dalam kelompok yang sebenarnya tidak mengacu pada penghayatannya atas identitas dirinya,” jelas Ika, sapaan akrabnya dalam wawancara dengan FIMELA beberapa waktu lalu.
Secara hukum tertulis di Indonesia, saat ini memang tidak ada yang mengatur penempatan sel sesuai dengan penghayatan gender seseorang, namun hanya dari apa yang tertulis di kartu identitasnya. Namun Ika juga menambahkan, sesungguhnya saat proses hukum, seorang psikolog bisa mendampingi para transgender agar bisa menjadi bahan pertimbangan pada pihak berwajib.
Bukan Kali Pertama dan Tak Hanya Ada di Indonesia
Tahun 2016 lalu sempat heboh berita soal transpuan yang diperkosa ribuan kali semasa di penjara. Ini terjadi di Queensland, Australia.
Mary, seorang transgender mengaku kerap dijadikan sasaran kekerasan seksual narapidana lain. “Saya lebih baik mati daripada dipenjara lagi (di sel pria). Mary masih bertahan, namun juga banyak transpuan yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan mengalami kekerasan di penjara.
Transpuan Memiliki Hak yang Sama dengan Manusia Lain
Ika menambahkan, hak transpuan harusnya sama dengan manusia yang lain. Mereka juga berhak mendapatkan pendampingan ahli agar tak mengalami kekerasan, mengingat di Indonesia, mereka masih merupakan kaum marjinal yang sarat menjadi sasaran kekerasan.
“Secara umum terhadap penjara dan proses hukum, perlu bebas dari budaya kekerasan apapun. Sikap dan perspektif penegak hukum perlu dikembangkan ke arah perspektif kesetaraan,” ujar Ika.
Kembali Melihat dengan Nurani
Perlu ditegaskan bahwa maksud saya menerbitkan artikel ini, bukan untuk membela perilaku yang mungkin dianggap tidak sesuai norma maupun agama. Namun mengajak pembaca untuk melihat sebuah masalah sebagai manusia dengan nuraninya. Menyadari bahwa setiap manusia, terlepas gendernya (atau pilihan gendernya) berhak mendapatkan perlindungan yang sama.
Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menghakimi bahkan mengamini perilaku kekerasan karena merasa derajat kita lebih tinggi.
Advertisement
Cek Video di Bawah Ini
Meghan Markle mengaku alami keguguran. Simak informasi selengkapnya di video di atas!
#ChangeMaker
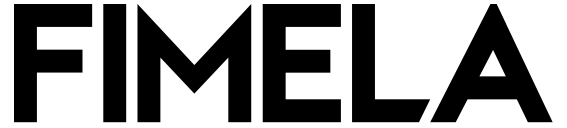
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/1783534/original/094885600_1536232429-photo_2018-09-06_18-10-27.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3310754/original/084806100_1606709062-shutterstock_1282882249.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3310756/original/060117700_1606709241-shutterstock_499741648.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3310757/original/053455300_1606709242-shutterstock_1657253119.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446056/original/088244600_1765871776-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446721/original/005950600_1765939085-IMG-20251217-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411995/original/098546600_1763028037-IMG_3023-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437620/original/023028500_1765258087-Depositphotos_804339058_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444636/original/037285600_1765784303-Desain_tanpa_judul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437822/original/092774500_1765264784-Depositphotos_618867182_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430234/original/024751500_1764656701-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430246/original/078844100_1764656929-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.55.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421696/original/066687600_1763957022-pexels-polina-tankilevitch-5468719.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421809/original/040895800_1763960008-pexels-emil-kalibradov-3013808-7085779.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3304346/original/025770100_1606121870-shutterstock_1819946462.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5160772/original/017170300_1741840102-Rambut_halus.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994359/original/026697200_1730937396-Depositphotos_513926280_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448482/original/048290000_1766030421-Foto_bersama_tamu_undangan_acara_peresmian.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446804/original/060156400_1765942120-pexels-daan-stevens-66128-939331.jpg)
![Lebih dari sekadar operasional internal, AYANA Bali juga melibatkan tamu dan komunitas dalam praktik berkelanjutan. Melalui AYANA Farm, area organik seluas dua hektare yang menanam lebih dari 130 varietas tanaman, tamu diajak mengenal pertanian organik dan prinsip sirkular secara langsung. [Dok/AYANA BALI].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/wSxxi2Nh7Q1NJLtzjPIoJgHgF70=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445903/original/006242400_1765867564-AYANA_Farm_Farm_Walk_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3562465/original/037038200_1630905705-jeshoots-com-fp1x-X7DwDs-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3154779/original/030653900_1592367704-8918.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5443189/original/085604800_1765630381-IMG_2367.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444779/original/096627700_1765788691-Depositphotos_305463478_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5299574/original/048097200_1753844577-Depositphotos_735660458_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444831/original/095331300_1765790013-Depositphotos_507090168_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5251284/original/063213100_1749792352-Depositphotos_247399436_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444079/original/017087300_1765770829-Depositphotos_221106062_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5414677/original/048577400_1763344579-IMG_4035-01.jpeg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448717/original/070007700_1766038449-Depositphotos_609334680_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3500830/original/034542100_1625446520-jimmy-dean-Qngdf0kgGB4-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5278182/original/094954900_1752056858-jessica-rockowitz-5NLCaz2wJXE-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2932381/original/055716500_1570429987-adorable-baby-boy-1374509.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4015359/original/003887100_1651889392-jose-ibarra-ifM0755GnS0-unsplash.jpg)
![Dipadu dengan jeans dan tas Hermes, Bunga Citra Lestari selesaikan tampilannya dengan sepatu suede [@itsmebcl]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/Z09-jZKTAewVch09BKkXMiqNnzE=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5438979/original/072744000_1765345043-SnapInsta.to_590481864_18548132539053347_3809798732195849625_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5231281/original/035535800_1748077534-WhatsApp_Image_2025-05-24_at_4.02.19_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5324690/original/050773600_1755858755-20250822-Noel_Ditahan-HEL_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448567/original/067225600_1766033308-1000630000.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/725520/original/Penjagaan-Daerah-140821.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2913252/original/006053400_1568693352-WhatsApp_Image_2019-09-17_at_10.57.35_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4016804/original/046265400_1652067919-KPK_4.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441661/original/089526700_1765514532-penampakan_warung_kalibata_yang_dibakar.jpg)
![Ternyata tidak hanya sebagai pelengkap penampilan saja, aroma parfum juga bisa dijadikan sebagai bentuk "terapi" untuk membantumu lebih rileks lho. [Dok/freepik.com]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/XGmLl7PMVoB4qDlZJfPd7HPHijs=/260x125/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5330269/original/084970000_1756357804-3d-rendering-personal-care-products-fondant-pink-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4598468/original/048272600_1696412875-pexels-ketut-subiyanto-4473774.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444585/original/041054100_1765781971-bride-holding-her-perfume.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5385782/original/049469700_1760944666-young-woman-beautiful-yellow-dress.jpg)