Hidup memang tentang pilihan. Setiap wanita pun berhak menentukan dan mengambil pilihannya sendiri dalam hidup. Seperti cerita sahabat Vemale yang disertakan dalam Lomba Menulis April 2018 My Life My Choice ini. Meski kadang membuat sebuah pilihan itu tak mudah, hidup justru bisa terasa lebih bermakna karenanya.
***
Tak banyak orang tahu menjadi wanita karier itu tidak melulu karena keegoisan individual semata. Ada yang memilih menjadi wanita karier dengan tujuan membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Contohnya aku.
Advertisement
Juli nanti genap lima tahun aku menjadi wanita karier. Hingga hampir dua tahun usia putriku, aku tetap memilih bekerja. Pro kontra orang terdekat pasti ada, bahkan cemooh orang tak sekali dua kali kudapatkan. “Ibunya S1 tapi anaknya kok diasuh lulusan SD?” atau nyinyiran orang yang lumayan membuat telingaku panas, “Buat apa kerja kalau semua waktunya habis di kantor, jarang ketemu anak." Sakit? Pasti. Apalagi aku termasuk wanita yang gampang sekali terbawa perasaan.
Cemoohan Selalu Saja Ada
Setiap kali cemooh orang terdengar telingaku, rasa bersalah pada putriku yang selama ini aku pendam langsung mencuat dan menjadi genangan air mata. Kenapa bukan aku yang menjadi saksi pertama ketika putriku pertama kali dapat melangkah. Kenapa bukan aku orang pertama yang dipanggil putriku “Ibu”.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2533301/original/072784500_1544758487-ibu-durhaka-bersama-anak.jpg)
Pernah sekali menjelang tahun keempat aku bekerja, ketika aku dalam kondisi begitu terpuruk, begitu sensitif, kubulatkan tekad untuk melayangkan “surat keramat” untuk berhenti bekerja pada atasanku. Mempertimbangkan masa kerjaku yang tidak sebentar, beliau memintaku memikirkan ulang dan berpikir masak-masak.
Aku tetap keukeuh pada keputusanku. Aku ingin di rumah mengasuh putriku tersayang, aku tidak ingin menjadi orang terakhir yang tahu tumbuh kembangnya, aku tak ingin jadi ibu durhaka yang ketika anaknya sakit tapi tetap bekerja. Atasanku hanya berkata, “Suratnya nggak saya buka dulu, saya ingin bicara dengan suamimu dulu tentang masalah ini."
Pertimbangan untuk Resign
Bicara dengan suami? Aku merasa terpojok. Sejujurnya, suamiku tidak 100% mendukung keputusanku berhenti bekerja. Ia bukan tipe lelaki menuntut istrinya harus kerja di rumah mengasuh anak. Seorang lelaki yang berpikiran modern, tidak kolot bahwa istri atau ibu itu harus di rumah mengasuh anak, bersih-bersih rumah, memasak, dll. ia memberiku banyak pertimbangan yang selama ini tidak pernah aku pikirkan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2533302/original/099475600_1544758488-ibu-durhaka-meja-kera.jpg)
Pertama, masalah ijazah pastinya. Kuliah empat tahun bukan waktu yang sedikit, dan berapa banyak uang yang sudah orangtuaku keluarkan demi menguliahkan aku. Tak sekali dua kali ibuku mencari pinjaman kesana kemari demi menutupi biaya kuliah dan biaya hidupku selama di luar kota menuntut ilmu. Terlebih aku anak satu-satunya yang berhasil mencapai bangku kuliah, dua orang kakakku hanya tamatan SMK dan STM. “Aku memang tidak ikut membiayai kuliahmu, tapi apa kamu pernah memikirkan perasaan ibumu jika kamu memutuskan berhenti bekerja?” suamiku berkata demikian.
Aku terpekur. Perasaan ibu? Hmm, bukankah seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya? Pastilah ibu mendukungku. Aku memberanikan diri menelepon ibuku membicarakan keputusan resignku. Beliau hanya menjawab, “Ya kalau memang itu keputusanmu, Ibu hanya bisa mendukung." Suaranya lemah, menyiratkan ada sedikit kekecewaan yang tak mampu terkatakan. Aku menutup telepon dengan kerutan di kening, jadi ibu ini sebenarnya sedih atau senang?

Kedua, masalah finansial tentunya. Suami menyuruhku menghitung apakah mencukupi gajinya untuk menghidupi bertiga? Aku angkat tangan namun tetap membantah, “Jelas nggak cukuplah tapi rezeki kan sudah ada yang atur, ya pasti ada jalan." Masalah kebutuhan primer memang tak perlu diragukan, namun bagaimana untuk kebutuhan sekunder? Bagaimana untuk tabungan masa depan anak? Untuk makan saja sudah sangat berhemat, yakin mampu menabung?
Suamiku menambahkan, “Lalu bagaimana cara kita membalas kedua orangtua kita? Apa kita masih mampu menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk membahagiakan mereka?” Keraguanku mulai bertambah.
Ketiga, gaya hidup. Karena aku memiliki penghasilan sendiri, setiap weekend kami memiliki budget sendiri untuk selalu jalan-jalan keliling kota quality time dengan putri kami. Entah ke mall, taman bermain, tempat wisata atau bahkan sekadar bertamu ke rumah teman-teman yang memiliki anak kecil. Tentunya ketika aku memutuskan untuk berhenti bekerja, kami harus diam di rumah, tak pergi kemana-mana untuk berhemat. Suami berkata, “Apa kamu siap?” Aku tersentak, jeraguanku semakin menjadi dan hatiku menjerit, “Tidaaaakkk aku tidak siap hidup serba pas-pasan. Aku masih butuh piknik."
Mengambil Keputusan
Dan segera kuraih handphoneku, kukirimkan pesan WhatsApp pada atasanku, “Selamat Malam, ini saya sudah bicara dengan suami, saya tidak jadi resign." Send, terkirim. Suamiku tersenyum. Masih dengan handphone dalam genggamanku, kupencet nomor ibuku, “Ibu, aku nggak jadi resign." Jawaban ibuku sungguh membuatku makin lega “Alhamdulillah, iya gitu, jangan terburu-buru memutuskan keluar." Ah ternyata keputusanku membuat semua orang bahagia.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2533303/original/059481500_1544758520-ibu-durhaka-pegan-hape.jpg)
Ibu bekerja... banyak orang memandang sebelah mata tanpa tahu realita sebenarnya. Aku bekerja untuk membuat suamiku tenang, orang tuaku bangga dan anakku bahagia di masa depannya. Apa yang salah dari ibu bekerja? Aku Deasy, seorang wanita karier berusia 27 tahun, seorang istri sekaligus seorang ibu dan aku bangga dengan pilihanku untuk tetap berkarier.
- Untuk Memilih Jurusan yang Tepat, Jangan Cuma Menuruti Gengsi
- Cinta Bisa Datang Belakangan Saat Sudah Sama-Sama Merasa Nyaman
- Harta yang Melimpah Nyatanya Tak Bisa Mengobati Kesepian
- Belum Diputus, Pacar Sudah Sebar Undangan Pernikahannya dengan Wanita Lain
- Mantan Pramugari Jadi Dosen, Bahagia Itu Memang Tak Cuma Diukur dari Materi
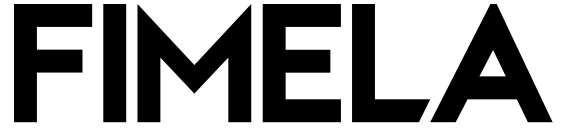

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2533300/original/052014400_1544758482-menjadi-wanita-karier-tak-lantas-membuatku-jadi-ibu-durhaka.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5048589/original/014913200_1734060747-WhatsApp_Image_2024-12-13_at_10.27.05_77b31f06.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055890/original/010999200_1734499535-HIGHLIGHT_FIMELA_DAY___IG_Feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055880/original/002353200_1734499127-HIGHLIGHT_day_3__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055871/original/038409700_1734498725-HIGHLIGHT_day_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055859/original/051857100_1734498130-HIGHLIGHT_day_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5036378/original/013812700_1733385978-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5032977/original/073652000_1733197790-FOTO_1.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5031960/original/055405000_1733118903-pexels-katerina-holmes-5905614.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5031999/original/051831100_1733119838-pexels-kampus-6481588.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033284/original/035244200_1733206299-pexels-rdne-10432436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5027652/original/7400_1732847912-DALL__E_2024-11-29_09.35.47_-_A_beautifully_arranged_plate_of_low-calorie_fried_tempeh__featuring_golden-brown_tempeh_slices_with_a_crispy_coating__lightly_dusted_with_herbs__serve.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5026609/original/066591600_1732775597-pexels-trista-chen-198334-723198.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5022621/original/4800_1732604869-DALL__E_2024-11-26_14.02.31_-_A_plate_of_low-calorie_shrimp_sambal_with_lemongrass__presented_in_a_kid-friendly_style._The_dish_includes_peeled_shrimp_cooked_in_a_light_red_sambal_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033038/original/000687200_1733198738-Snapinsta.app_468983269_422604517585625_3930891875784389755_n_1080.jpg)
![Seniman Galuh Anindita menciptakan aksesori yang diberi nama Mahija. [dok. Galuh Anindita]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WTXk5rkAsLcLcYIG39cRqwfZn1A=/0x1157:2624x2636/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035276/original/041670100_1733312960-FOTO_PROFIL_SENIMAN_-_GALUH_ANINDITA_WARDANA.JPG)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058958/original/065333600_1734685101-IMG_4392.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034833/original/043480800_1733296555-FIMELA_FASHION_-_BOUNDLESS_BEAUTY_WITH_WEEKEND_MAXMARA__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033477/original/089964900_1733210907-IMG_8172__1_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016705/original/043770800_1732230233-PERSONAL_STYLE_-_Febby_Rastanty__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994919/original/098462400_1730968814-FIMELA_FASHION_-_THE_WAY_SHE_WEARS_IT_WITH_LOEWE__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059635/original/096788700_1734747974-DSC02165.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059634/original/087205900_1734747459-DSC02133.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058639/original/072368600_1734673545-IMG_1824.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058636/original/055943600_1734673137-IMG_1782.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055868/original/076493100_1734498476-IMG_7979.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055853/original/052583600_1734497914-IMG_9747.JPG)
![Lihat di sini penampilan Irish Bella di pemotretan keluarga barunya. [@_irishbella_].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/CKo9RNfF_drGyLEpCznxcmVvqZo=/260x125/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5061538/original/026962000_1734870311-Snapinsta.app_470973280_18435141811075453_1403070050616814038_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059635/original/096788700_1734747974-DSC02165.jpg)
![Lihat di sini tampilan serasi Annisa Pohan dan Almira Yudhoyono di Hari Ibu. [@annisayudhoyono].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/9KjLDxgseFsuj2ol__vNArcHbRw=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5061537/original/063718700_1734870041-Snapinsta.app_470932747_18483580360025227_3590958600666601584_n_1080__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059634/original/087205900_1734747459-DSC02133.jpg)