Apakah ada sosok pahlawan yang begitu berarti dalam hidupmu? Atau mungkin kamu adalah pahlawan itu sendiri? Sosok pahlawan sering digambarkan sebagai seseorang yang rela berkorban. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Seperti kisah sahabat Vemale yang diikutsertakan dalam Lomba Kisah Pahlawan dalam Hidupmu ini. Seorang pahlawan bisa berasal dari siapa saja yang membuat pengorbanan besar dalam hidupnya.
***
Sahabat Vemale, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah inspiratif tentang seorang pahlawan sosial yang mungkin tak begitu dikenal. Sosok ini sungguh telah memantik pikiran saya sendiri, bahwa berbagi tidak pernah memandang seberapa banyak materi yang kita beri. Berbagi lebih menekankan pada keikhlasan untuk memberi apapun yang kita miliki.
Cinta, kasih, ilmu, bahkan sebuah pengorbanan yang dibalut dengan ketulusan adalah bentuk nyata pemberian yang sangat berarti. Sebetulnya, saya bingung hendak memulai menceritakan kisah ini dari mana. Pertemuan saya dengan pahlawan itu terjadi sangat singkat, sehingga hanya sedikit cerita yang bisa saya kulik dari dirinya. Semoga sepenggal kisah ini mampu memompa semangat kita untuk terus berbakti pada negeri atau minimal berbakti untuk lingkungan sekitar dan diri sendiri.
Advertisement
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2528188/original/084765400_1544665637-kyle-gregory-devaras-491943-unsplash.jpg)
Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 tahun lalu, saya memutuskan untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan sosial yang diadakan oleh Komunitas 1000 Guru Banten. Kegiatan ini bergelut di bidang pendidikan (Teaching) dan perjalanan wisata (Traveling). Dua kegiatan yang sangat menyenangkan menurut saya.
Hasil dari searching di akun instagram 1000 Guru Banten, saya mendapatkan informasi bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan di desa yang cukup terpencil di Cibaliung, Pandeglang, Banten. Sebuah daerah yang hampir menyentuh ujung barat dari Pulau Jawa. Bahkan, perjalanan untuk menuju kesana hampir memakan waktu kurang lebih 4 jam dengan titik pemberangkatan dari alun-alun Rangkasbitung.
Di sepanjang perjalanan, pikiran saya sudah berandai-andai tentang kehidupan di sana. Mungkin saya akan menemui sekolah berdinding tembok yang sudah berlubang, atau mungkin atapnya yang sudah bolong-bolong karena tidak terawat. Imajinasi saya juga melanglang buana memikirkan anak-anak di sana yang barangkali berangkat sekolah beralaskan sepatu tua yang ujungnya sudah robek. Atau bisa jadi mereka memakai baju seragam putih merah yang atasannya sudah menguning di makan usia. Pikiran-pikiran itu membuat saya tidak sabar untuk segera tiba.
Sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin sedikit bercerita. Sekarang, saya adalah seorang perempuan yang menyandang status sebagai mahasiswa strata-1 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di sebuah universitas swasta di Jakarta. Keputusan untuk memilih jurusan ini dilatarbelakangi oleh kecintaan saya terhadap dunia pendidikan.
Saya bukanlah seorang aktivis pendidikan, namun saya sedang berusaha untuk terus menggeluti passion dan juga cita-cita yang sudah saya pilih ini. Maka tidak heran, jika saya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan sosial di bidang pendidikan. Salah satunya kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas 1000 Guru Banten.
Selain untuk melakukan pengabdian dan berbagi dengan sesama, kegiatan-kegiatan sosial menyiratkan pesan moral tersendiri bagi saya, khususnya tentang memaknai rasa syukur di dalam menjalani kehidupan. Bukankah melihat ke bawah lebih baik daripada terus-menerus mendongak?
Kembali ke perjalanan saya menuju Cibaliung, Pandenglang Banten.
Saya beserta rombongan tiba di homestay sekitar pukul 04.00 WIB dini hari. Dinginnya malam yang menusuk tulang-tulang belakang tidak menyirnakan nafsu saya untuk segera menuju sekolah tempat saya akan memulai pengabdian. Tepat pada pukul 07.00 WIB perjalanan saya menuju sekolah SDN Sorongan dimulai.
Jalan perkampungan yang sempit menjadi jalan pembuka pada perjalanan pagi ini. Jalan setapak demi setapak telah dilalui. Hingga akhirnya keringat mengucur tidak terkira, saya dan rombongan belum juga sampai di tujuan. Jalanan mulai agak ekstrem.
Perkampungan warga telah terlewati, yang ada tinggallah hutan-hutan yang di sebelah kanan kirinya penuh ilalang tinggi. Tidak ada rumah. Yang ada hanyalah suara-suara binatang khas hutan, seperti tonggeret yang memekikkan telinga. Yang lebih menegangkan, saya harus melewati sebuah jembatan kayu yang sudah mulai lapuk. Padahal, di bawah jembatan tersebut terdapat sungai besar yang untungnya sedang kering karena musim kemarau. Saya banyak-banyak berdoa, meminta agar saya dapat pulang ke rumah dengan selamat.
Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya tibalah saya dan rombongan di SDN Sorongan.
“Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di SDN Sorongan nih, temen-temen."
Awalnya, saya merasa bingung ketika seorang panitia mengatakan bahwa kami telah sampai di sekolah yang menjadi tempat tujuan pada kegiatan ini. Saya tidak melihat ada bangunan berdinding tembok dan beratapkan genteng seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Yang saya temui hanyalah sepetak ruangan berukuran sekitar 4 x 4 meter yang terbuat dari bambu.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2528189/original/062295100_1544665638-jasa-guru-1.jpg)
Atapnya nampak terbuat dari jerami kalau dilihat sekilas. Lantainya benar-benar tanah, bahkan masih bergelombang—tidak rata. Di sekelilingnya terdapat sekitar 4 rumah penduduk yang juga tidak begitu bagus. Pikiran saya masih mengawang, belum benar-benar yakin jika itu adalah sekolah.
Setelah sesaat, barulah saya menyadari bahwa ruangan yang lebih layak disebut dengan “kandang ayam” itu adalah benar-benar sekolah—SDN Sorongan. SD ini adalah satu dari dua sekolah dasar yang ada di daerah sana. Satu sekolah dasar yang lain sudah cukup bagus, namun jaraknya tidak terjangkau oleh anak-anak. Untuk menempuh perjalanan ke SDN Sorongan saja butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan berjalan kaki.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2528190/original/032013500_1544665639-jasa-guru-2.jpg)
Jarak yang harus ditempuh kurang lebih 10 sampai dengan 12 kilometer. Seketika, air mata saya meleleh. Bagaimana mungkin tempat seperti ini pantas dijuluki sebagai sekolah? Akan tetapi, realita tetap saja realita. Ruangan itu memang benar-benar sekolah, tempat di mana anak-anak Cibaliung mencari secercah harapan akan masa depannya. Kaki saya melangkah perlahan untuk melihat keadaan di dalam sekolah tersebut.
Betapa hati saya tambah teriris melihat sepotong papan tulis berwarna putih terpasang di dinding sekolah tersebut. Di sana tertulis, “KELAS 1, KELAS 2, KELAS 3, KELAS 4." Satu ruangan itu dipakai untuk empat kelas. Bangku-bangku tersusun sangat rapat, hingga siswa yang berada di bagian belakang tidak bisa keluar. Jika ingin keluar, ia harus menginjak meja temannya yang lain. Seketika, saya baru menyadari dan merasa bahwa diri saya krisis akan “rasa syukur”.
Tak jauh dari saya berdiri, tampak seorang laki-laki gagah memakai kemeja berwarna krem dan memakai celana hitam. Saya berjalan mendekati bapak tersebut. Rasa penasaran saya mulai menggebu-gebu. Ingin saya mengulik banyak informasi dari laki-laki berhati mulia itu.
“Bapak guru di SD ini?”
“Iya, Mbak. Saya ngajar di sini sudah hampir 5 tahun.”
“Bapak kenapa mau mengajar di sini?”
“Panggilan jiwa, Mbak. Kasihan saya melihat anak-anak di sini. Pendidikannya masih sangat kurang. Jangankan khatam wajar 9 tahun. SD saja banyak yang tidak lulus. Daerah sini masih belum tersentuh dari segi pendidikannya.”
“Bapak lulusan pendidikan juga?”
“Bukan, Mbak. Saya orang Ekonomi aslinya. Tapi karena anak-anak di sini membutuhkan tenaga pendidik, jadi saya beralih saja jadi guru. Yang penting anak-anak bisa sekolah.”
Begitulah percakapan singkat saya dengan Pak Guru berhati malaikat itu. Hati saya seperti tercabik. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki background jurusan pendidikan berbesar hati untuk mendidik anak pedalaman dengan gaji yang tidak pantas?
Saya tidak pernah menyangka bahwa laki-laki dengan ketampanan dan kekekaran tubuh yang dimilikinya, rela tinggal di suatu tempat yang mungkin “kurang pantas” untuk dikatakan sebagai sebuah desa. Tidak ada lampu merkuri yang menyala di perempatan, tidak ada suara-suara azan yang berkumandang di setiap waktu salat tiba, apalagi mall-mall megah yang berdiri seperti di ibukota.
Bukankah jika beliau bekerja di kantoran, beliau akan mendapatkan gaji yang banyak? Saya malu dengan diri saya sendiri. Melihat kemuliaan bapak ini, saya kembali menguraikan air mata. Sayangnya, saya tidak sempat berkenalan dengan beliau. Bahkan, namanya saja saya tidak tahu. Saya telanjur terenyuh dengan sikap beliau yang penuh kedermawanan. Yang jelas, saya bangga dengan bapak.
Lalu, bagaimana kondisi anak-anak di sana?
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2528191/original/008827500_1544665640-jasa-guru-3.jpg)
Anak-anak sekolah di SD Sorongan tidak memakai seragam ataupun sepatu seperti anak-anak pada umumnya. Mereka berpakaian seperti anak-anak yang ingin bermain bola dengan temannya. Mereka juga tidak memakai sepatu. Jikalau ada, hanya satu atau dua orang saja. Kaki mereka hitam tampak terlihat putih karena balutan debu-debu ketika perjalanan berangkat menuju sekolah. Yang lebih memprihatinkan, mereka tidak pernah melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Ia tidak begitu hafal dengan lagu Indonesia Raya. Mereka juga tidak kenal dengan presiden kita. Mereka hanya tau bapak Rano Karno—yang menurut mereka beliau adalah bapak presiden Indonesia.
Akan tetapi, saya melihat wajah-wajah mereka penuh dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Semangat yang membara untuk belajar, terpancar dari binar mata mereka yang penuh akan asa. Hanya saja, mereka merindukan gedung sekolah yang dindingnya rapat, atapnya kuat, dan meja-meja yang tersusun rapi berderet. Mereka juga merindukan nyamannya seragam sekolah baru dan sepatu berwarna hitam yang cantik. Yang lebih penting, mereka merindukan sosok guru dari kota yang dermawan seperti gurunya saat ini.
Untuk menutup kisah ini, saya ingin menyampaikan sepenggal uraian kalimat untuk bapak guru.
Bapak Guru, kemurahan hatimu bak mata air di tengah gurun yang menyejukkan para musafir-musafir yang kehausan. Kebesaran jiwamu bak lentera di kesunyian malam yang menentramkan. Ketulusan kasihmu bak belaian lembut tangan ibunda yang menghangatkan.
Bapak Guru, ajari kami tentang berperang. Tidak dengan pedang, apalagi dengan senapan. Ajari kami berperang dan berkorban dengan welas dan asih pada anak bangsa, agar ia merdeka dari kebodohan yang mengungkung asa. Maaf, jika namamu terlupa. Tetapi, jasamu akan terngiang melewati angkasa.
Cibaliung, 18-20 Agustus 2018
- Pendamping di Awal Perjuangan, Belum Tentu Berakhir di Pelaminan
- Terima Kasih Saudara Sedarahku, Sudah Menguatkanku di Kala Duka
- Pengorbanan Bisa Berakhir Kekecewaan Tapi Belum Tentu Memberi Penyesalan
- Sungguh Bodoh Jika Hati Dikorbankan untuk Seseorang yang Tak Pernah Peduli
- Pria Hebat Itu Sering Menyembunyikan Mendung di Wajahnya
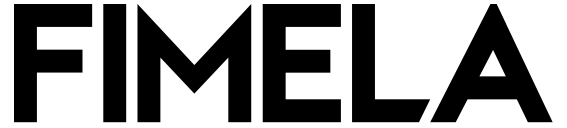

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2528186/original/039972400_1544665605-sebuah-nama-yang-terlupa-tapi-jasanya-untuk-bangsa-menembus-angkasa.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446056/original/088244600_1765871776-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446721/original/005950600_1765939085-IMG-20251217-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411995/original/098546600_1763028037-IMG_3023-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437620/original/023028500_1765258087-Depositphotos_804339058_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444636/original/037285600_1765784303-Desain_tanpa_judul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437822/original/092774500_1765264784-Depositphotos_618867182_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430234/original/024751500_1764656701-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430246/original/078844100_1764656929-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.55.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421696/original/066687600_1763957022-pexels-polina-tankilevitch-5468719.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421809/original/040895800_1763960008-pexels-emil-kalibradov-3013808-7085779.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3304346/original/025770100_1606121870-shutterstock_1819946462.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5160772/original/017170300_1741840102-Rambut_halus.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994359/original/026697200_1730937396-Depositphotos_513926280_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450270/original/033756400_1766135930-Foto_2__5_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448250/original/093199600_1766024444-Screen_Shot_2025-12-18_at_09.16.02.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449052/original/021526200_1766046562-1280x847_px.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448482/original/048290000_1766030421-Foto_bersama_tamu_undangan_acara_peresmian.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446804/original/060156400_1765942120-pexels-daan-stevens-66128-939331.jpg)
![Lebih dari sekadar operasional internal, AYANA Bali juga melibatkan tamu dan komunitas dalam praktik berkelanjutan. Melalui AYANA Farm, area organik seluas dua hektare yang menanam lebih dari 130 varietas tanaman, tamu diajak mengenal pertanian organik dan prinsip sirkular secara langsung. [Dok/AYANA BALI].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/wSxxi2Nh7Q1NJLtzjPIoJgHgF70=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445903/original/006242400_1765867564-AYANA_Farm_Farm_Walk_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5347725/original/027946100_1757731962-Depositphotos_743561216_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5374918/original/040849600_1759907026-Depositphotos_765307270_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445848/original/089097000_1765866385-Depositphotos_209737914_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445420/original/079190200_1765855454-Depositphotos_697365816_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5367561/original/018485600_1759307407-Depositphotos_684389538_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448942/original/017979400_1766042921-Depositphotos_741727416_XL.jpg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5377099/original/051631100_1760075985-IMG-20251010-WA0019.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4444272/original/047789800_1685269233-jochen-van-wylick-ex0pl-zo7NM-unsplash-min.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3042930/original/012138700_1580966089-the-honest-company-Ua9AK-pZ5cw-unsplash.jpg)
![SuperMom Awards didedikasikan untuk seluruh ibu di Indonesia, sebuah bentuk apresiasi bahwa setiap ibu layak mendapat ruang untuk dilihat, dihargai, dan dirayakan. [FOTO:FIMELA/ADRIAN].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/wkwzbyVkl5QFWu5j--08implLzQ=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451252/original/019027200_1766247664-WhatsApp_Image_2025-12-20_at_22.52.10__2_.jpeg)
![Bertepatan dengan momen Hari Ibu, Fimela menggelar SuperMom Awards di Wyl’s Kitchen, Hotel Veranda, Jumat (20/12). Acara ini sekaligus menandai peluncuran kanal parenting terbaru Fimela, Fimela Mom. [Dok/FIMELA/Adrian].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/j9qIQkRVoeQEn3iLW_FQBNlvVYg=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451245/original/009650800_1766246925-WhatsApp_Image_2025-12-20_at_22.52.12.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449873/original/089563900_1766117964-Depositphotos_832815214_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5231281/original/035535800_1748077534-WhatsApp_Image_2025-05-24_at_4.02.19_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450778/original/080041100_1766184841-kpk_bekasi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451317/original/066452800_1766278822-Kabid_Humas_Polda_Kepri_Kombes_Pol_Zahwani_Pandra_Arsyad.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451214/original/080194300_1766242824-banjir_bandang_guci_tegal.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451308/original/034413000_1766271710-Lokasi_penganiayaan_pengunjung_lapo_di_Pringsewu.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451302/original/041529800_1766270075-Banjir_bandang_terjang_kawasan_wisata_air_panas_Guci_Tegal.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5451235/original/040872700_1766244156-WhatsApp_Image_2025-12-20_at_21.36.32.jpeg)
![Burberry goddess parfum termasuk kedalam keluarga oriental-vanilla. [Dok/Burberry]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/pvDijhanQFZTt-JXz7kvaBGdxXg=/260x125/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450947/original/014565400_1766212947-WhatsApp_Image_2025-12-20_at_12.38.12.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447411/original/014416200_1765956316-Depositphotos_811448338_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4941733/original/058834000_1726027050-cute-couple-park-lady-gray-coat-people-pier.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5350155/original/020505500_1757992086-Depositphotos_736970776_XL.jpg)