Setiap orang punya kisah dan perjuangannya sendiri untuk menjadi lebih baik. Meski kadang harus terluka dan melewati ujian yang berat, tak pernah ada kata terlambat untuk selalu memperbaiki diri. Seperti tulisan sahabat Vemale yang diikutsertakan dalam Lomba Menulis Vemale Ramadan 2018, Ceritakan Usahamu Wujudkan Bersih Hati ini. Ada sesuatu yang begitu menggugah perasaan dari kisah ini.
***
Sebelumnya, aku ingin berterima kasih kepada Vemale.com yang telah memberiku kesempatan untuk berbagi cerita. Sebenarnya, aku tak tahu bagaimana aku harus menceritakan kejadian yang kualami ini. Mungkin, kata yang lebih tepat seharusnya, entah kepada siapa aku harus menceritakan semua kisah yang kualami saat ini.
Advertisement
Dulu, saat aku masih kecil, aku pernah bertengkar dengan temanku hingga aku menangis karena ia menjelek-jelekanku. Lalu, ayahku datang menghampiriku dan bertanya padaku, “Nak, kamu tahu air, kan?”
Tentu saja aku tahu. Aku mengangguk mengiyakan, sambil sesekali mengusap air mataku.
Ayah kemudian berkata lagi. “Jadilah seperti air. Saat disentuh, ia tak menimbulkan bekas, bukan? Selain itu, air juga selalu mengalir hingga ke tempat yang ia tuju—baik itu muara, sungai, bahkan laut sekalipun. Meskipun rintangan datang secara bertubi-tubi, walau dihadang oleh batu besar maupun kerikil, bahkan permukaan yang lebih tinggi sekalipun, ia selalu berusaha menemukan cara dengan usahanya sendiri supaya sampai ke tempat tujuannya.”
“Jadi, apa maksud Ayah mengatakan itu?” tanyaku tak mengerti.
“Nah, sebagai manusia, kita harus bisa memaafkan orang lain, seperti air yang bila disentuh takkan menimbulkan jejak. Kita juga harus selalu berpegang teguh pada prinsip, karena hidup ini tak selamanya mulus seperti jalan tol. Namun, ingatlah selalu akan satu hal. Walaupun rintangan selalu menghadang—tak peduli berapa banyak kesusahan yang kita alami—kita harus selalu ingat akan tempat tujuan kita nanti, yaitu akhirat.”
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2520454/original/055726400_1544455089-jadi-air-1-pixabay.jpg)
Ayahku melanjutkan, “Orang yang senang membicarakan kita, menjelek-jelekan kita, dan menjudge kita, sebenarnya iri dengan apa yang kita punya. Tidak perlu membalas, cukup taburkan saja senyum manis pada mereka.”
Hingga saat itu, aku tak pernah mengerti dan tahu-menahu perihal kerasnya kehidupan orang dewasa. Orangtuaku seringkali bertengkar—entah karena apa. Aku yang saat itu masih kecil bisa langsung mengetahui hal tersebut, karena mereka beberapa kali bertengkar di depan aku dan adikku. Hal yang menurutku tak seharusnya diperlihatkan pada anak seusia kami.
Ayah dan ibuku menikah saat ibuku berusia 18 tahun, sementara ayahku usianya baru menginjak 20 tahun. Mereka menikah pada usia yang sangat muda—bukan karena 'kecelakaan' tentunya, melainkan karena komitmen yang mereka bangun sendiri. Ibuku yang saat baru lulus SMU itu ditawari oleh nenekku untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah memilih menerima lamaran ayahku daripada melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Lalu, setahun kemudian, aku pun lahir sebagai putri pertama pasangan itu. Ketika teman-temanku menanyakan usia kedua orangtuaku, dengan santai aku menjawab, “Baru 36 tahun.” Dan seketika, teman-temanku pun menganga lebar saking kagetnya.
“Serius? Nggak bohong?”
“Nggaklah. Ngapain juga aku bohong.” balasku saat itu.
“Wah, masih muda, ya.” Beberapa dari mereka mengomentari seperti itu. Ada pula yang mengomentari dengan mengatakan bahwa ibuku tampak seperti kakakku.
Dalam hati, aku hanya bisa tertawa kecil. Ya, memang menggelikan mengetahui bahwa ibuku dan aku usianya hanya berbeda 18 tahun. Mungkin itulah sebabnya pasangan yang menikah muda cenderung lebih banyak bertengkar dibandingkan pasangan yang menikah di atas umur 25 tahun, karena kepribadian mereka yang masih terikat dengan 'jiwa muda' mereka dulu.
Yah, aku terbilang tak peduli dengan hal-hal semacam itu. Posisiku sebagai anak pertama menjadikan kedua orangtuaku lebih memprioritaskan adikku ketimbang aku—membuatku terbiasa melakukan segala sesuatunya sendirian. Secara otomatis, orangtuaku pun memberi sedikit kelonggaran padaku. Aku sedikit iri pada adikku, karena saat adikku pulang lebih telat sedikit saja, ibuku akan langsung terburu-buru mencarinya. Meskipun diberi kelonggaran, aku lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada menghabiskan waktuku dengan bermain bersama teman-temanku yang lain di luar rumah. Aku tahu, bahwa kelonggaran yang orangtuaku berikan merupakan bentuk dari kepercayaan mereka padaku.

Beranjak dewasa, perekonomian keluargaku mulai menurun. Ayahku yang bekerja membuka usaha sendiri mulai memecat beberapa karyawannya dan mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa pernah mengeluh sedikitpun. Minimnya pesanan juga turut mempengaruhi keadaan tersebut.
Untuk membiayai kehidupan sehari-hari kami, ibuku puntang-panting mencari pinjaman pada orang lain. Terkadang, beliau juga meminjam uang tabunganku atau adikku. Bahkan, ibu pernah menjadi driver ojek online—hanya supaya kami memperoleh uang untuk membeli beberapa potong baju lebaran. Dalam hati, aku bersyukur telah dilahirkan dari orangtua yang hebat seperti mereka.
“Tak apalah, toh aku kan masih bisa menabung lagi,” Begitulah setidaknya pikirku saat itu.
Namun, lambat laun, keadaan semakin memburuk. Usaha ayahku kembali sepi, dan jarang sekali ada pesanan yang datang. Hal itulah yang membuat ibuku kembali meminjam uang padaku. Dengan berat hati, aku memecahkan celengan ayamku yang baru kuisi selama kurang lebih dua bulan lamanya, lalu menyerahkan uang tersebut pada ibuku. Ibu lalu berterima kasih padaku, dan berjanji akan mengembalikan uang tabunganku secepatnya.
Sayangnya, karena keadaan yang semakin mendesak, Ibuku terpaksa menggadaikan handphone dan laptopku untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Ingin sekali aku bertanya pada ibuku, "Mengapa harus aku?" Namun, aku tak bisa mengatakannya, karena jika aku mengatakannya kuyakin hal tersebut malah semakin membebani orangtuaku. Sekali lagi, dengan berat hati aku menyerahkannya pada ibuku. Ada sedikit rasa iri yang melanda hatiku ketika melihat teman-temanku yang lain asyik memainkan gadgetnya, sementara aku hanya bisa memperhatikan mereka dari jauh.
Suatu ketika, salah satu temanku bertanya. “Hape kamu kemana? Bukannya kemarin masih kamu bawa-bawa, ya? Kok, sekarang nggak dibawa, sih?”
Aku bingung harus menjawab apa. Haruskah aku jujur dengan keadaanku saat ini, ataukah berbohong?
Bukannya kejujuran, kebohonganlah yang justru meluncur dari bibirku, “Ah, itu … dipinjam sama ibuku, hehe.”
Berkali-kali kutanya pada Ibu. “Bu, kapan hape sama laptop Kakak dibawa lagi?” dan berkali-kali pula ibuku menjawab. “Sabar, ya. Ibu usahain secepatnya. Makanya, doain semoga ayahmu ada kerjaan lagi.”
Aku hanya bisa meringis dalam hati. Bukannya bermaksud bagaimana, aku tak pernah lupa untuk berdoa siang dan malam setiap harinya. Aku selalu berdoa agar Allah melancarkan rezeki kedua orangtuaku. Berbeda dengan kedua orangtuaku yang hanya sibuk meratapi keadaan. Bahkan, aku pernah membolos kegiatan ekstrakulikuler selama beberapa kali hanya karena orangtuaku tak mempunyai cukup uang untuk memberiku uang saku.
Keadaan semakin diperparah dengan pertengkaran kedua orangtuaku. Puncaknya, dua hari menjelang tahun baru, ibuku membawa aku dan adikku untuk menginap di rumah sanak keluargaku yang lain—meninggalkan ayahku di rumah seorang diri. Seolah cercaan dari orang-orang di sekitarku yang mengiringi kepergian kami tak ada artinya, dan aku hanya bisa menutup telinga.
“Kasihan dia.”
“Apa orangtuanya akan bercerai?”
Dan berbagai macam perkataan menyakitkan lainnya yang menusuk hati.
Jujur, aku merasa tak enak dengan keadaanku saat ini. Ingin rasanya aku pergi sejauh mungkin dan tak kembali, namun aku tak tahu harus pergi kemana. Ingin rasanya aku bercerita pada temanku, namun sayangnya tak ada seorang pun yang dapat kupercayai. Ironis memang. Aku hanya ingin mereka mendengarkan ceritaku saja. Bagiku, itu saja sudah cukup. Bukannya malah menatapku iba, karena aku tidak suka dikasihani.
Selama ini, aku dan kedua orangtuaku tinggal di rumah nenekku. Hal itulah yang membuat ibuku terkadang menyampaikan isi hatinya padaku atas perlakuan tak mengenakkan nenek pada kami yang memperlakukan kami seolah berbeda dengan saudara kami yang lain. Hal itulah yang membuatku sadar, bahwa sakit yang dialami ibuku jauh lebih menyakitkan dari yang kualami saat ini.
Di satu sisi, aku merasa kasihan pada ayahku. Aku tahu, dibalik sifat pendiamnya, beliau tahu benar akan segala permasalahan yang kami alami saat ini. Sayangnya, ayah hanya diam saja—tanpa berniat meluruskan kesalahpahaman diantara mereka berdua. Sementara ibuku, yang menderita sakit terlalu banyak, hanya bisa menahan kembali segala gejolak emosinya, hingga akhirnya memutuskan untuk pergi.
Dan beberapa jam setelah itu, setelah kudesak untuk kesekian kalinya, aku akhirnya mengetahui bahwa ibuku ternyata menjual handphoneku—bukan menggadaikannya, sehingga hanya laptopku saja yang digadaikan. Bukannya terjual, handphone tersebut malah dibawa kabur oleh si calon pembeli tanpa membayar sepeserpun.
Ya Allah, cobaan apa lagi ini?
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2520455/original/015258400_1544455095-jadi-air-3.jpg)
Saat itu, aku marah. Merasa sakit hati juga pilu yang mendalam karena merasa telah dibohongi. Meski begitu, aku tak berani menampakkan kemarahanku di hadapan ibuku, sehingga aku menahan tangisku.
Dan aku, kepada siapa aku mengadu?
Maka, kepada Allah-lah aku mengadu. Menceritakan segala keluh kesahku yang tak sempat kuceritakan pada orang lain, berharap bahwa Ia akan memberikanku solusinya.
Aku, seorang remaja berusia 15 tahun, mengalami masa tahun baru terburuk sepanjang hidupku. Hari dimana seharusnya aku menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru yang lebih baik lagi, malah kuhabiskan dengan meratapi keadaan dan menangis seorang diri. Aku hanya bisa pasrah, setidaknya mungkin hanya itu satu-satunya cara agar aku dapat melalui segala cobaan yang kualami saat ini.
Malam pun berlalu. Keesokan harinya, ibu memutuskan untuk pulang kembali ke rumah tepat pada saat perayaan malam tahun baru. Di perjalanan, aku melihat seorang anak kecil berpakaian lusuh dan kumal tengah menjajakan dagangannya di pinggir jalan—sambil menenteng beberapa kantong plastik besar berisi kerupuk. Ada rasa iba melihat keadaan anak itu.
Dan saat itu juga aku tersadar. Kusadari bahwa aku selalu melihat ke atas, tanpa pernah melihat ke bawah. Aku selalu melihat orang-orang yang berkecukupan di atasku dengan perasaan iri, tanpa pernah berpikir untuk melihat orang-orang yang serba kekurangan di bawahku.
Aku pun tertegun. Allah seakan menegurku lewat segala cobaan dan segenap permasalahan yang kualami saat itu, supaya aku dapat mengintrospeksi diri.
Aku lupa untuk bersyukur pada-Nya atas nikmat napas, penglihatan, pendengaran, dan bahkan umur yang kumiliki saat ini.
Aku penuh dengan rasa iri pada orang lain, tanpa pernah sadar bahwa keadaanku saat ini jauh lebih baik daripada mereka yang lebih membutuhkan. Bahkan, aku kerap merasa iri pada adikku sendiri. Astaghfirullah.
Aku sombong dalam beribadah. Kesombongan yang bukan dalam artian senang mengumbar-umbar ibadahku pada orang lain, melainkan aku yang seringkali merasa bahwa akulah yang paling rajin beribadah—padahal nyatanya banyak sekali orang yang ibadahnya lebih baik dariku.
Aku lupa pada-Nya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2520456/original/077429600_1544455095-jadi-air-4.jpg)
Sesampainya di rumah, aku langsung berlari menuju kamarku, kemudian mengkaji ulang kisah-kisah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran. Aku kemudian teringat akan makna dari QS. Al-Insyirah ayat 5, bahwa di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Bahkan, hal tersebut ditegaskan kembali oleh Allah SWT. pada ayat berikutnya. Lalu, tiba-tiba saja aku teringat akan perkataan ayahku sewaktu aku kecil dulu. "Jadilah seperti air, Nak." Ah, iya, betul sekali. Memaafkan orang lain—seperti air yang bila disentuh takkan menimbulkan jejak. Aku baru menyadari bahwa perkataan ayahku saat itu ada benarnya dan berkaitan dengan keadaanku saat ini.
Malam itu, tepat pada tanggal 31 Desember, aku merasa menemukan sosok diriku yang baru. Dan aku seakan tersadar, bahwa masalah datang bukan hanya pada usia dewasa saja—remaja belia sepertiku pun tak luput dari masalah. Setiap orang pasti memiliki permasalahannya sendiri dan cara menyelesaikan masalahnya sendiri—tak terbatas pada usia tertentu saja, karena usia hanyalah sebuah angka, tak mencerminkan bagaimana kepribadian kita yang sebenarnya.
Maka, aku pun berterima kasih pada-Nya. Pasrah akan segala keputusannya, dan menikmati setiap cobaan yang Ia berikan sebagai sebuah pelajaran untuk ke depannya.
Anehnya, ikhlas menjadikan hatiku lebih tenang lagi.
Aku sadar betul bahwa dulu aku adalah seorang remaja belia yang naif, tak pernah bersyukur, dan tak pernah luput dari kesalahan. Sadar tak sadar, keterpurukan dan permasalahan yang kualami itu adalah sebuah bentuk proses alami menuju kedewasaan. Mungkin, saat itu aku belum sadar. Tapi, untuk kedepannya, hal ini berpengaruh besar di kehidupanku.
Dan alhamdulillah, hingga saat ini, hubungan kedua orangtuaku baik-baik saja—meski terkadang diiringi oleh pertengkaran-pertengkaran kecil. Aku berharap, semoga ke depannya pun begitu. Aamin.
Perjalananku masih panjang. Tidak seharusnya aku membuang waktuku sia-sia hanya untuk menyesali apa-apa yang sudah terjadi. Aku akan berjuang, sampai masaku habis, dan sampai tiba waktuku menghembuskan napas terakhir.
Ya Allah Ya Rabb, Engkaulah segalanya untukku.
- Cela Saja Kekurangan Fisikku, Tapi Nanti Aku Akan Lebih Sukses dari Kalian
- Menjadi Bahan Olokan di Kantor karena Gagal Menikah, Aku Kudu Kuat
- Pria Posesif yang Sudah Melanggar Privasi Itu Membuatku Jadi Wanita Bodoh
- Berdamai dengan 'Kapan Nikah', Tak Semua Orang Berhak Tahu Urusan Hati Kita
- Gagalnya Sebuah Hubungan Pasti Akan Digantikan dengan Jodoh yang Lebih Baik
(vem/nda)
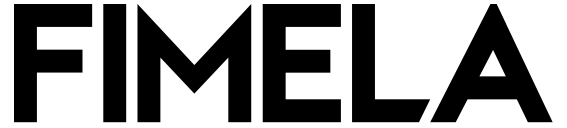

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2520453/original/026642000_1544455086-untuk-bisa-memaafkan-ibaratkan-dirimu-seperti-air.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446056/original/088244600_1765871776-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446721/original/005950600_1765939085-IMG-20251217-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411995/original/098546600_1763028037-IMG_3023-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437620/original/023028500_1765258087-Depositphotos_804339058_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444636/original/037285600_1765784303-Desain_tanpa_judul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437822/original/092774500_1765264784-Depositphotos_618867182_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430234/original/024751500_1764656701-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430246/original/078844100_1764656929-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.55.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421696/original/066687600_1763957022-pexels-polina-tankilevitch-5468719.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421809/original/040895800_1763960008-pexels-emil-kalibradov-3013808-7085779.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3304346/original/025770100_1606121870-shutterstock_1819946462.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5160772/original/017170300_1741840102-Rambut_halus.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994359/original/026697200_1730937396-Depositphotos_513926280_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450270/original/033756400_1766135930-Foto_2__5_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448250/original/093199600_1766024444-Screen_Shot_2025-12-18_at_09.16.02.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449052/original/021526200_1766046562-1280x847_px.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448482/original/048290000_1766030421-Foto_bersama_tamu_undangan_acara_peresmian.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446804/original/060156400_1765942120-pexels-daan-stevens-66128-939331.jpg)
![Lebih dari sekadar operasional internal, AYANA Bali juga melibatkan tamu dan komunitas dalam praktik berkelanjutan. Melalui AYANA Farm, area organik seluas dua hektare yang menanam lebih dari 130 varietas tanaman, tamu diajak mengenal pertanian organik dan prinsip sirkular secara langsung. [Dok/AYANA BALI].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/wSxxi2Nh7Q1NJLtzjPIoJgHgF70=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445903/original/006242400_1765867564-AYANA_Farm_Farm_Walk_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5367561/original/018485600_1759307407-Depositphotos_684389538_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448942/original/017979400_1766042921-Depositphotos_741727416_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5322422/original/036083000_1755746026-Depositphotos_685706088_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444779/original/096627700_1765788691-Depositphotos_305463478_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5299574/original/048097200_1753844577-Depositphotos_735660458_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444831/original/095331300_1765790013-Depositphotos_507090168_XL.jpg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449873/original/089563900_1766117964-Depositphotos_832815214_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5366353/original/094814400_1759224233-IMG-20250930-WA0029.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449771/original/003878000_1766114768-SnapInsta.to_573549944_18542491231006320_2904117580239073306_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449666/original/082808300_1766110223-SnapInsta.to_602006395_18550304539052084_2785223168873873253_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5419485/original/094619500_1763697852-rawpixel.com.jpg)
![Wulan Guritno dan ketiga anaknya yang kini sudah dewasa dan remaja. [@wulanguritno]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/75gwbMDLH3tDnqW4z5XTWSBCJQE=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449166/original/044337100_1766049610-IMG_2577.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5231281/original/035535800_1748077534-WhatsApp_Image_2025-05-24_at_4.02.19_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3187421/original/067871800_1595417306-jaksa_agung__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450526/original/085889800_1766143465-WhatsApp_Image_2025-12-19_at_18.17.47.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5289607/original/098662900_1753074718-WhatsApp_Image_2025-07-21_at_12.09.59.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450340/original/058125200_1766137785-banjir_bandang_di_sukabumi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2913252/original/006053400_1568693352-WhatsApp_Image_2019-09-17_at_10.57.35_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5139252/original/087217400_1740073376-WhatsApp_Image_2025-02-20_at_20.25.07_948b06da.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1509996/original/026407200_1487315956-Cucumber-face-mask__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5247915/original/091838400_1749549258-side-view-woman-getting-massaged-spa.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3292552/original/039205800_1605006560-photo-1562158467-f89e51f06266.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5306131/original/030623000_1754376969-pexels-sarah-chai-7262986.jpg)