Jodoh adalah rahasia Tuhan. Awalnya aku agak meragukan pernyataan tersebut, sebelum aku sendiri mengalaminya. Ya, jodoh adalah rahasia. Misteri yang tidak dapat ditebak akhirnya kepada siapa hati akan menamatkan kisah kasih itu.
Dulu aku tidak mengenalnya, meskipun kami satu SMP, satu kelas bahkan. Anehnya dia juga tidak mengenalku, padahal aku bisa dibilang cukup populer waktu itu, hehe. Hingga sebuah takdir mempertemukanku dengannya, mengawali kedekatan kami.
Saat itu aku dan teman-teman berencana mengadakan reuni SMP untuk melepas kerinduan kepada kawan lama. Kami telah berpisah dua tahun lamanya, ketika itu masih duduk di kelas dua SMA. Itu reuni pertama kami, dan kebetulan aku ditunjuk teman-teman untuk menjadi ketua panitia. Karena waktu itu belum secanggih sekarang, maka aku pun membuat undangan reuni dan mengantarkannya satu persatu ke rumah teman-teman.
Di situlah awal mula aku dan dia bertemu. Aku bersama seorang temanku mengunjungi rumahnya untuk mengantarkan undangan reuni. Wanita paruh baya yang ternyata ibunya, mempersilakan kami masuk lantas beliau memanggilkan si dia.
“Hai,” dia menyapa.
Deg! Jantungku serasa mau copot dari tempatnya. Si dia, telah banyak sekali berubah dari yang kutahu dulu. Auranya, wibawanya ... kuakui mampu membuat cewek mana saja terpesona. Hatiku kian berdesir saat dia menolak uluran tangan temanku untuk bersalaman.
“Maaf bukannya apa-apa, tapi aku nggak sentuhan sama perempuan yang bukan muhrim,” katanya menjelaskan. Ah, ragaku seperti melayang. Apa yang terjadi denganku, Tuhan?
“Oh, iya. Yang ini siapa, Widya?” dia bertanya pada temanku dengan polosnya. Sial! Batinku. Dia benar-benar tidak mengenalku.
“Aku Ayu. Kita pernah sekelas, by the way. Ah, memang kita nggak saling kenal. Tapi aku nggak percaya ada teman satu SMP yang nggak tahu aku, haha!” aku mencoba berkelakar.
“Oh, iya sorry. Aku kuper kali ya?” jawabnya sambil tertawa.
Obrolan kami sore itu tidak berarti apa-apa, kukira. Namun ternyata, tidak bagi si dia. Rupanya pertemuan kali ini tidak ingin diakhirinya begitu saja. Sejak itu kami mulai dekat. Awalnya dia sekadar SMS, bertanya seputar acara reuni yang akan dilaksanakan. Nomorku memang tertera di undangan sebagai salah satu contact person. Baru kutahu, ternyata sekarang dia nyantri di salah satu pesantren terkenal di Jawa Timur. Setiap Ramadhan dia pulang, liburan sampai Idul Fitri. Pantas saja dia begitu kalem, batinku.
Hari kemenangan tiba, reuni berlangsung dua hari berikutnya. Kami kembali bertemu, ya sekadar bertemu. Dia masih biasa saja, dan karena aku ketua panitia yang merangkap sebagai MC, maka aku sibuk luar biasa sehingga sama sekali tidak memperhatikannya.
Lebaran berakhir, aku tidak pernah lagi mendapat SMS darinya. Mungkin dia sudah berangkat, aku menerka.
Malam itu, beberapa bulan kemudian. Handphoneku berdering oleh sebuah panggilan masuk dari nomor asing.
“Assalamualaikum,” suara di seberang sana menyapa.
“Maaf, ini siapa, ya?” tanyaku.
“Ini aku, Panca. Maaf ya, aku berangkat nggak sempat pamitan. Ini aku juga nelpon nggak bisa lama-lama. Aku cuma mau bilang, kalau aku ... aku suka sama kamu, Ayu.”
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2494663/original/046076500_1543371656-penantian-pelaminan-1.jpg)
Aku bagaikan disengat listrik seribu volt, terkejut tak percaya mendengar pernyataannya. Namun saat itu aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak berpacaran lagi, dan ternyata dia pun sama. Akhirnya kami berkomitmen untuk menjaga perasaan ini sampai benar-benar disatukan oleh Dia, Sang Pemilik Hati.
Bertahun-tahun kami menjalani komitmen ini, hingga aku tiba di penghujung akhir masa kuliah. Teman-temanku mendesak supaya aku menuntut kejelasan hubungan kami darinya, mengingat ada beberapa lelaki yang bersiap melamarku seusai kuliah nanti. Aku menyetujui usul mereka. Hingga tibalah hari itu, sepuluh Ramadhan. Kuberanikan diri untuk mengajaknya buka bersama berdua saja di sebuah rumah makan. Kebetulan dia baru saja pulang dari tugasnya mengajar pesantren kilat di sebuah sekolah.
“Assalamualaikum,” sapaku. Dia telah lebih dulu datang di tempat kami bertemu, tengah asyik membaca buku.
“Hei, sudah datang kamu. Ayo, duduk. Mau pesan apa?” tanyanya.
Hatiku rasanya seperti diremas-remas. Keringat dingin menetes. Aku salah tingkah. Bagaimana tidak? Seseorang yang selama ini kutunggu-tunggu kini duduk tepat di hadapanku. Dan baru kali ini setelah lebih kurang empat tahun, kami bertemu berdua saja, duduk berhadap-hadapan seperti ini.
“Oh, iya. Maaf menunggu lama. Terserah kamu mau pesan apa, samain aja,” jawabku kikuk.
Akhirnya kuutarakan maksud hatiku padanya. Bahwa sebentar lagi aku lulus kuliah, dan ada beberapa lelaki yang sudah menungguku di luar sana.
“Aku ..., aku cuma pengen minta kepastian dari kamu, tentang komitmen kita. Apa ... apa aku masih harus menunggumu atau kamu melepaskanku, atau bagaimana? Kalau masih harus menunggu, berapa lama lagi?” aku bicara sambil menundukkan kepala, tidak berani sama sekali menatap wajahnya.
Diam. Tidak ada yang bersuara di antara kami berdua. Keheningan seketika menyelimuti. Aduh, apa yang sudah kulakukan? Keringat dinginku semakin deras mengalir.
“Aku akan menikahimu, di umurmu yang ke-24,” tiba-tiba dia bicara, mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa sulit digerakkan. Jantungku seperti berhenti untuk sekian detik.
“Maksudmu?” aku memberanikan diri mengangkat wajahku, menatap matanya.
“Jika kamu minta aku bertindak sekarang, aku belum siap. Aku masih harus menyelesaikan belajarku di pesantren. Aku akan menikahimu saat kamu berumur 24 tahun, tiga tahun dari sekarang. Jika dalam waktu tiga tahun itu ada yang telah siap menikahimu dan kamu menyukainya, silakan kamu terima. Tapi kabari aku dulu,” dia menjelaskan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2494664/original/017375000_1543371657-penantian-pelaminan-2.jpg)
Keraguan menyelimuti hatiku saat mendengar jawabannya. Akhirnya kuputuskan meninggalkan dia untuk lelaki lain yang tengah mendekatiku. Dari usahanya, lelaki ini terlihat begitu gigih, bahkan berani bilang pada ibuku untuk mengajakku jalan. Lelaki ini adalah salah seorang mantan kekasihku di zaman SMA dulu. Setahun kami mencoba memulai hubungan yang lebih serius dari masa SMA, namun dia juga tak kunjung memberi kejelasan. Aku sudah diwisuda, bahkan sudah bekerja.
Selama setahun itu pula aku tidak pernah mendengar kabar dari si dia yang ada di pesantren. Kami lost contact sejak aku memutuskan meninggalkannya. Dia sakit hati, membenciku dan menghapus semua kontakku. Saat itulah aku merasa menyesal telah mengingkari komitmen kami. Hingga siang itu, aku menerima sebuah pesan dari nomor baru.
‘Assalamualaikum, kamu kapan ada waktu? Aku boleh main ke rumah? Panca.’
Hatiku berdesir. Benarkah ini dia? Angin apa yang membuat dia mengirim pesan padaku? Rasanya seperti mimpi. Akhirnya kuberanikan diri membalas pesan itu.
‘Weekend aku free. Kalau cuma main, kenapa nggak boleh? Silahkan.’ Kupencet tombol send dengan hati yang tak karuan.
Keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu rumah. Dan betapa terkejutnya aku saat mendapati siapa yang berdiri di sana. Dia, seorang diri membawa parcel buah dan macam-macam cangkingan lainnya, menyapaku dengan senyum khasnya, “Hai!” Ya Tuhan, aku masih tidak percaya ini!
Kupersilakan dia masuk dan duduk. Seperti biasa, keringat dinginku mengalir. Ah, aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengan lelaki ini. Hatiku selalu tak menentu bila berada di dekatnya. Perasaan apa ini, Tuhan? Batinku.
“Aku mau ketemu ibumu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan,” katanya membuka percakapan.
Aku memanggil Ibu. Secara singkat kuperkenalkan dia dengan Ibu, karena mereka baru sekali ini bertemu.
“Bu, saya ke sini dengan niat menjalani hubungan yang serius dengan putri Ibu, Ayu. Kalau Ibu mengizinkan dan Ayu bersedia, secepatnya setelah ini keluarga saya akan datang ke mari untuk melamar Ayu.”
Deg! Kali ini jantungku benar-benar berhenti. Perkataannya baru saja bagaikan petir di siang bolong yang menyambarku.
“Ka ... kamu, serius?” tanyaku terbata-bata.
“Kamu pikir, aku main hanya sekadar main? Kamu masih mau memberiku kesempatan?”
Aku menelan ludah. Ibu memberikan keputusan sepenuhnya kepadaku. Aku belum memberikan jawaban hari itu. Kuberi tenggat waktu satu minggu agar dia mau menunggu. Aku ingin memantapkan hatiku, dan menyelesaikan urusan dengan hati-hati yang lain.
Advertisement
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2494665/original/096441200_1543371657-penantian-pelaminan-3.jpg)
Akhirnya setelah beristikharah dan meminta petunjuk, Tuhan memberiku kemantapan hati untuk kembali menerimanya. Segera kuakhiri kedekatan dengan mantan kekasih SMAku itu. Awalnya dia tidak terima, tapi setelah Ibu menjelaskan, akhirnya dia menyadari bahwa aku bukan takdirnya. Waktu itu dia masih kuliah, sementara si dia yang melamarku sudah memiliki pekerjaan mapan di luar kota. Ya, setelah lulus dari pesantren dia langsung mendapat tawaran pekerjaan yang membuatnya mantap untuk melamarku.
Dua bulan yang lalu kami menikah, tepat saat usiaku 24. Kucium tangannya dengan takzim, bersama berjuta syukur yang kupanjatkan pada Tuhan. Seseorang yang telah sekian lama kutunggu itu ternyata benar-benar ditakdirkan menjadi jodohku. Air mataku mengalir, mengingat aku pernah tak mempercayai ucapannya dan justru meninggalkannya untuk orang lain. Namun sejak awal bertemu aku sudah tahu, bahwa lelaki ini tidak hanya akan menjadi lelakiku yang biasa. Aku tahu bahwa dia adalah jawaban dari doa-doa.
- Jodoh Sejatiku Datang Saat Aku Sudah Dilamar Orang
- Terlambat Menikah Jauh Lebih Baik daripada Salah Memilih Pasangan
- Cinta Terhalang Takdir, Calon Suami Meninggal Saat Pernikahan di Depan Mata
- Memperjuangkan Cinta Lama Itu Boleh, Tapi Jangan Sampai Jadi Orang Ketiga
- Mamah Menunggu Izin Bapak untuk Embuskan Napas Terakhirnya
(vem/nda)
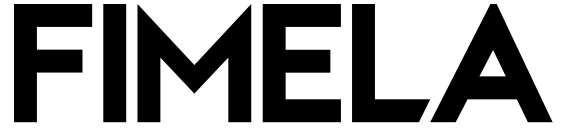

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2494662/original/048425300_1543371654-jodoh-terbaik-akan-selalu-temukan-jalannya-meski-menunggu-itu-menyakitkan.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055890/original/010999200_1734499535-HIGHLIGHT_FIMELA_DAY___IG_Feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055880/original/002353200_1734499127-HIGHLIGHT_day_3__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055871/original/038409700_1734498725-HIGHLIGHT_day_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055859/original/051857100_1734498130-HIGHLIGHT_day_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5036378/original/013812700_1733385978-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5032977/original/073652000_1733197790-FOTO_1.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035957/original/053181400_1733369335-pexels-naimbic-1618925.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5031960/original/055405000_1733118903-pexels-katerina-holmes-5905614.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5031999/original/051831100_1733119838-pexels-kampus-6481588.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033284/original/035244200_1733206299-pexels-rdne-10432436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5027652/original/7400_1732847912-DALL__E_2024-11-29_09.35.47_-_A_beautifully_arranged_plate_of_low-calorie_fried_tempeh__featuring_golden-brown_tempeh_slices_with_a_crispy_coating__lightly_dusted_with_herbs__serve.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5026609/original/066591600_1732775597-pexels-trista-chen-198334-723198.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033038/original/000687200_1733198738-Snapinsta.app_468983269_422604517585625_3930891875784389755_n_1080.jpg)
![Seniman Galuh Anindita menciptakan aksesori yang diberi nama Mahija. [dok. Galuh Anindita]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WTXk5rkAsLcLcYIG39cRqwfZn1A=/0x1157:2624x2636/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035276/original/041670100_1733312960-FOTO_PROFIL_SENIMAN_-_GALUH_ANINDITA_WARDANA.JPG)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058958/original/065333600_1734685101-IMG_4392.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034833/original/043480800_1733296555-FIMELA_FASHION_-_BOUNDLESS_BEAUTY_WITH_WEEKEND_MAXMARA__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033477/original/089964900_1733210907-IMG_8172__1_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016705/original/043770800_1732230233-PERSONAL_STYLE_-_Febby_Rastanty__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994919/original/098462400_1730968814-FIMELA_FASHION_-_THE_WAY_SHE_WEARS_IT_WITH_LOEWE__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5040014/original/041925800_1733585153-Screenshot_2024-12-07_222316.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4951584/original/095131100_1727156564-medium-shot-beautiful-business-woman.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4945624/original/003351800_1726546764-brooke-cagle-xcgh5_-QIXc-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4894841/original/050617300_1721281278-ilustrasi_ibu_dan_anak-20220624-298-adrian.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019956/original/070747400_1732500348-IMG_0122.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4881799/original/063836000_1719979407-woman-using-smartphone-technology.jpg)
![Melihat gaya serasi Hito Caesar dan Felicya Angelista yang merayakan ulang tahun anak kedua mereka bertema Minnie & Mickey Mouse. [@felicyangelista_].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WATB-HuEjldGnnjKUSAEZFXhCsc=/260x125/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5061216/original/023086800_1734834126-Snapinsta.app_470985717_18478956379041261_1084825750631131521_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5063451/original/060237300_1734949323-Pesona_Paula_Verhoeven_di_Jakarta_Fashion_Week_2025.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035957/original/053181400_1733369335-pexels-naimbic-1618925.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5040014/original/041925800_1733585153-Screenshot_2024-12-07_222316.jpg)