Kisah sahabat Vemale yang diikutsertakan dalam Lomba Menulis Surat untuk Ibu ini kembali menyadarkan kita akan satu hal. Bahwa ternyata seorang ibu memiliki sisi kesepiannya sendiri. Bahkan ada luka yang ia pendam sendiri.
***
“Tidak apa-apa.” Matanya sayu, memendam air mata yang disimpan rapat, rekat namun tetap terpancar hangat. Malam itu, aku sedikit membuka obrolan dengan Ibu. Sudah terhitung enam bulan aku tidak menatap wajahnya sedekat ini. Usia yang tidak dapat dipungkiri, Ibu semakin menua dari hari ke hari. Masih kuingat, pesan singkat yang mengatakan kondisinya pada skala baik-baik saja, seketika berubah menjadi status ‘awas’ sesudah melihat beban masalah di mata Ibu. Kelopak mata Ibu tidak dapat menipu. Apa yang dipendam Ibu? Apakah aku? Atau pilu yang terbendung sedari dulu?
Semua pesan Ibu terasa bermakna ganda. Dirinya menutupi sebuah luka, yang mengembun beberapa hari, mengkristal berbulan-bulan, dan membatu setiap tahun dengan memendam sendirian. Malam itu pula, luka itu dibagi, tanpa alasan untuk menagih pada Sang Kuasa untuk meluruskan jalan hidupnya kembali. Aku tidak tegar, aku tidak menangis, aku hanya memberi saran bak seorang anak yang mendapat banyak pembelajaran dari tanah perantauan. Padahal sama halnya, anak gadisnya ini juga termakan masalah setiap harinya yang tidak dapat terelakkan.
Ibuku mendapat banyak tekanan, baik di lingkungan kantornya maupun teman seperjuangannya. Direndahkan, diremehkan, tidak dipedulikan dan dianggap tidak punya apa-apa, itulah yang beliau keluhkan. Tiba-tiba, terasa ada duri kecil menyasar ulu hatiku. Ibu, jika aku menangis, Ibu pasti akan menangis maka aku akan menahannya, mencoba memberi saran yang membuat pertahanan di dalam kelopak mataku yang dalam.
Advertisement
“Semua orang pernah berbuat salah, Ibu. Pernah suatu kali, ada seseorang yang mengatakan padaku. Sesering apapun seseorang membuat kesalahan, maafkan, ingatlah sekecil apapun kebaikannya.” Walaupun membalasnya dengan tatapan tenang, dirinya mengelak. Aku paham, Ibu lebih lama menyelam samudera kehidupan dibandingkan dengan aku yang hanya anak ingusan. Tapi aku tidak ingin diam saja. Aku ingin membuat Ibuku tetap kokoh meskipun banyak arus yang menggetarkan akar-akar jiwanya.
“Bu, aku pernah mendapat masalah yang cukup besar saat perkuliahan. Aku enggan menceritakannya pada Ibu, teman, bahkan pada siapapun. Hingga aku berani menceritakan kisahku pada seorang biarawati yang mewawancaraiku untuk keperluan kegiatan perkuliahan.” Ibu menatapku tenang, aku melanjutkan, “Dia berkata, aku jarang fokus pada kebaikan kecil yang ada di sekitarku. Contohnya saat ini aku bisa bertatapan dengan ibu berjam-jam. Coba saja jika aku tidak memiliki determinasi tubuh yang kuat, mungkin di perjalanan kemarin aku bisa demam atau terserang sebuah penyakit.” Ibu mengangguk seakan paham.
“Tapi Nak, luka itu sering, tajam, dan tidak terlupakan.” Aku diam. Itulah kalimat pamungkas Ibu yang membuatku tak dapat menjawab.
Keheningan angin malam ingin aku pecahkan. Pikiranku semakin kalut dan mendalam. Menjadi seorang anak perempuan ataupun Ibu ternyata tidak hanya status dalam sebuah ikatan yang bernama keluarga. Ibu, sosok yang sering kudambakan menjadi seorang panutan, dirinya bisa terjun ke batas alam bawah sadar dan ingin jatuh terpendam. Tiba-tiba aku teringat akan sebuah hal. “Ibu, temanku pernah berkata, ketika seorang wanita sedang bercerita, seharusnya kita tidak memberi saran atau anjuran. Kita cukup mendengarkan. Mungkin dengan begitu, kejujuran sebuah luka bisa mengalir dan sembuh dengan bantuan mata yang saling bertemu atau sebuah pelukan yang menghangatkan," jawabku mantap.
Mata Ibu kembali berkaca-kaca. Dia hanya mengangkat kepala ke atas, tidak membiarkan air itu jatuh, kelopak matanya menciut, mengangguk seakan paham kembali dan merebahkan dirinya pada sebuah bantal beralaskan kasur. Perbincangan selanjutnya beliau jelaskan terus terang, masalah yang menimpanya, dimulai dari kerenggangan mahligai perkawinannya hingga masalah biasa yang tidak terdeteksi letak luka yang pasti. Ibu sangat kuat. Menahannya sendirian, sedangkan anaknya berada di tanah perantauan. Pergolakan batinnya merongrong, meminta melepaskan diri pada kehidupan yang semakin tidak ada arti. Orang-orang di sekitar yang menjadi support system-nya seakan menyusut dan alur kehidupannya mulai menjauhi titik fokus.
Malam itu aku belajar, Ibu, bagian dari kedua orang tuaku, ternyata memiliki sisi kesepian. Hidupnya kehilangan harapan meskipun sudah ada tanggungan. Mereka tidak selalu ingin tujuan yang sering kita elu-elukan, baik untuk sukses ke depan atau kehidupan mapan di masa depan. Bahkan saat ini, mendapat sebuah telpon dengan nama ‘anakku’ di layar telepon yang mereka kenakan merupakan suatu hiburan siang dan malam, bahwa harapannya di suatu tempat sudah tumbuh besar dan berkembang. Melanjutkan mimpinya yang padam, atau membawa obor kebaikan bagi semua orang ke depan.
Malam itu, aku menangis di saat Ibu sudah tertidur lelap dalam malam yang pekat. Matanya tidak lagi sayu namun menunjukkan sebuah kekuatan baru. Kejujuran luka itu nampak pada tidur kami yang nikmat pada balutan awan kelabu tapi tetap syahdu. Aku tetap di sini Ibu, di samping Ibu selalu. Bagi luka itu dengan aku.
- Ibu, Hijabkan Dirimu
- Aku Bahagia Hidup dengan 2 Ibu, Jadi Tak Perlu Memintaku Memilih Salah Satu
- Ibu Bukan Darah Dagingku, Tapi Kehadirannya Bagai Malaikat di Hidupku
- Ibu, Terima Kasih Telah Menjadi Wakil Tuhan Untukku di Dunia Ini
- Untuk Ibu yang Mengadu Nasib di Negeri Orang, Cepatlah Pulang Bu!
(vem/nda)
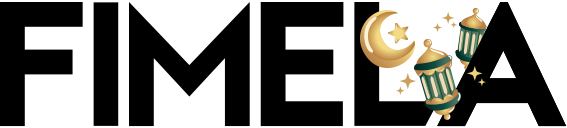

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2490661/original/006769200_1543343451-ibu-juga-memiliki-sisi-kesepiannya-sendiri.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2490662/original/076403300_1543343452-kejujuran-ibu-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2490663/original/042562800_1543343453-kejujuran-ibu-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/922320/original/032118700_1436335243-Untitled-11.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2293969/original/078275600_1532743622-20180727-Penampakan-Gerhana-Bulan-Total-di-Jakarta-TALLO-5.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5143936/original/005207500_1740559932-WhatsApp_Image_2025-02-26_at_3.45.19_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5167274/original/091207900_1742351630-assortment-delicious-fresh-cookies_114579-13166.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5166770/original/053276900_1742284290-aldo_s25_ramadan_group_00161_OPT2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5166112/original/055638700_1742223474-Foto_1_-_Havaianas__RayakanSejenak_Iftar_Event.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069010/original/025185800_1735287306-pexels-polina-tankilevitch-4518581.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5064546/original/065004900_1735022946-pexels-cottonbro-6970101.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5064532/original/051604600_1735022585-pexels-cottonbro-5990491.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4993686/original/004273900_1730894148-Screenshot_2024-11-06_183841.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5044050/original/083856400_1733829025-pexels-fotios-photos-1161682.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041610/original/060088700_1733732335-pexels-august-de-richelieu-4259707.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033038/original/000687200_1733198738-Snapinsta.app_468983269_422604517585625_3930891875784389755_n_1080.jpg)
![Seniman Galuh Anindita menciptakan aksesori yang diberi nama Mahija. [dok. Galuh Anindita]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WTXk5rkAsLcLcYIG39cRqwfZn1A=/0x1157:2624x2636/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035276/original/041670100_1733312960-FOTO_PROFIL_SENIMAN_-_GALUH_ANINDITA_WARDANA.JPG)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5175283/original/001243700_1742981077-IMG_9091.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5172662/original/068492800_1742784425-FIMELA_FASHION_-_MODEST_EID_STYLE_BENANG_JARUM_x_Raisa__YT_Post_.jpg)
![Perhiasan: Tiffany & Co. // Makeup: Laura Mercier // Hair: Shisheido Professional // Model: Mariyye from Studio47. [Foto: Adrian Putra/ Fimela.dok]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/YlBu6kBOJ7tfWEp3e6HTC8hU12g=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5143202/original/016928600_1740493988-0E6A2838-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5140051/original/040275900_1740135842-FIMELA_FASHION_-_GLEAMING_LOVE_STORY_WITH_TIFFANY___Co.__YT_Post.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069846/original/010151000_1735373948-FIMELA_FASHION_-_Luxury_in_Every_Stitch_with_MCM__IG_feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058958/original/065333600_1734685101-IMG_4392.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5037772/original/098458000_1733407832-Screenshot_2024-11-28_184516.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5073706/original/007465300_1735645381-Screenshot_2024-12-31_183017.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5100402/original/061791700_1737270367-Screenshot_2025-01-19_140113.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5047996/original/090208000_1734008292-Screenshot_2024-12-12_194204.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069375/original/004035600_1735304402-Screenshot_2024-12-27_194050.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041897/original/065093700_1733746217-Screenshot_2024-12-09_184000.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5156419/original/016105000_1741471246-steptodown.com721125.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3305652/original/081926700_1606213576-pexels-photo-3183197__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5037772/original/098458000_1733407832-Screenshot_2024-11-28_184516.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3983981/original/023032400_1649048978-Premium_Photo___Muslim_friend_and_family_laughing_together_when_lunch.jpg)