Ladies, di Indonesia jamu sebagai pengobatan tradisional ternyata juga memiliki filosofi yang sangat tinggi. Hal ini berdasarkan tradisi masyarakat yang tidak menciptakan apapun begitu saja, namun selalu dengan disertai tuntunan luhur untuk kembali kepada alam dan Tuhan.
Nah, yuk kita mengenal lebih dalam tentang sejarah dan filosofi jamu yang kerap kali terabaikan.
(vem/tey)Advertisement
Sejarah jamu
Jamu sudah dikenal luas dan diracik sejak zaman pra-sejarah terbukti dari adanya penemuan peralatan batu dari zaman Mesolithikum dan Neolithikum berupa lumping yang biasa digunakan untuk meracik jamu. Tidak hanya itu saja, relief tentang meracik jamu juga ditemukan di relief Karmawipangga pada candi Borobudur, relief Candi Brambang komplek candi Prambanan, candi Panataran, Sukuh, dan Tekalwangi serta pada prasasti candi Perot, Haliwangbang dan Kadadu.
Bukti tertulis penggunaan jamu juga ditemukan pada daun lontar dengan menggunakan bahasa jawa kuno, sansekerta dan bahasa bali. Sedangkan primbon terlengkap tentang jamu baru ditulis pada serat Centhini yang ditulis atas perintah Kanjeng Gusti Adipati Anom Amengkunegoro III yang memerintah Surakarta tahun 1820-1823 M. Sedangkan serat Kaoro Bap Djampi-Djampi atau tulisan tentang jamu Jawa yang ditulis tahun 1858 M memuat sebanyak 1734 ramuan Djampi.
Pada zaman Majapahit, jamu menjadi minuman kebesaran raja sekaligus menjadi gengsi bagi para pembesar dan mitra kerajaan di luar Majapahit. Paru pada akhir periode Majapahit, Raden Fatah yang juga penerus trah Brawijaya V mulai mempromosikan jamu sebagai ilmu sekaligus tatanan sakral kehidupan keraton yang terangkum dalam buku "Kawruh Djampi" di Jogjakarta dan Surakarta dan membuat jamu mulai merambah kalangan masyarakat bawah.
Meracik dengan doa
Masyarakat tradisi tidak pernah terpisah dari alam, karena itulah saat ada yang sakit, penyembuhan yang dipilih adalah yang tersedia dari alam seperti jamu atau obat-obatan tradisional. Kata jamu pertama kali muncul pada abad 15-16 Masehi dari kata djampi yang berarti doa dan oesodo yang berarti kesehatan. Sedangkan peracik jamu disebut acaraki.
Dalam masyarakat tradisi, seorang acaraki harus berdoa dulu sebelum membuat jamu. Ia juga harus melakukan meditasi serta berpuasa untuk dapat merasakan energi positif yang bermanfaat bagi kesehatan. Ritual ini diperlukan karena bagaimanapun juga masyarakat Jawa kuno percaya bahwa Tuhanlah sang penyembuh utama.
Jamu memiliki konsep majemuk karena tiap tanaman herbal memiliki efek positif dan negatif bagi tubuh. Efek negatif dari satu tanaman herbal harus dinetralisir dengan menciptakan formulasi khusus dari beberapa tanaman herbal lainnya tanpa menghilangkan khasiat utamanya.
Advertisement
Filosofi sesuai siklus hidup
Dari jaman Sultan Agung, setiap lapisan masyarakat memahami filosofi jamu, bahkan hingga tukang jamu gendong. Tukan jamu gendong selalu membawa delapan jenis jamu yang melambangkan delapan arah mata angin sekaligus lambang surya Majapahit, Wilwatikta. Delapan jenis jamu tersebut adalah kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, pahitan, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup/ gepyokan dan sinom.
Urutan meminum jamu yang ideal dimulai dari manis-asam, sedikit pedas-hangat, pedas, pahit, tawar, hingga manis kembali, sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Kunyit asam yang manis-asam merupakan simbol kehidupan yang manis ketika bayi hingga pra remaja yang mulai merasakan kehidupan yang sebenarnya.
Beras kencur melambangkan masa remaja dimana manusia mulai memiliki sikap egoisme dan baru sedikit mencicipi kehidupan yang sebenarnya. Hal ini dilambangkan dengan rasa sedikit pedas. Fase selanjutnya dilambangkan dengan Cabe Puyang yang pedas-pahit seperti kehidupan manusia di usia 19-21 tahun yang mulai labil.
Pahitan melambangkan fase kehidupan selanjutnya yang meskipun pahit, harus tetap ditelan atau dijalani. Kemudian kehidupan akan menjadi landai sebagai resolusi hidup. Hal ini dilambangkan dengan tepat oleh jamu Kunci Suruh. Kunci merupakan sebuah bumbu penyedap makanan, sedangkan suruh memiliki banyak khasiat dan penyembuh berbagai macam penyakit. Jadi dapat dilambangkan bahwa kesuksesan hidup kita saat itu didasarkan pada apa yang kita pelajari sejak kecil.
Fase selanjutnya dilambangkan dengan jamu Kudu Laos yang merupakan jamu penghangat. Hal ini melambangkan siklus kehidupan ketika manusia harus mampu menjadi penghangat dan pengayom bagi orang di sekelilingnya. Fase selanjutnya bersifat penetral dan rehabilitatif dan menunjukkan pengabdian diri seutuhnya dan kepasrahan tulus seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini dilambangkan oleh uyup-uyup/gepyokan.
Yang terakhir adalah sinom yang dapat diartikan sirep tanpa nampa. Dalam Bahasa Indonesia hal ini bisa bermakna diam (tidur/meninggal/moksa) dengan tidak meminta apa-apa. Rasa manis jamu ini melambangkan bahwa jika manusia di awal dilahirkan dengan fitrah, maka harus kembali kepada Tuhan dengan keadaan fitrah juga.
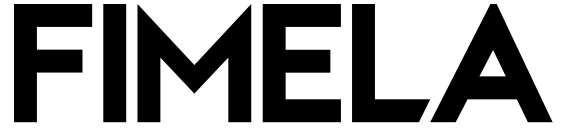

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2463143/original/013981800_1543213863-filosofi-jamu-indonesiaku.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2463144/original/060935800_1543213864-jamu-tradisional-untuk-mengatasi-anak-sakit-panas-v.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017053/original/075009000_1732250521-FD2025-1500x845.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995209/original/026181100_1730986853-Screenshot_2024-11-07_202711.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4988253/original/058148800_1730511774-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5014358/original/0800_1732092222-DALL__E_2024-11-20_15.31.31_-_A_plate_of_Indonesian_nasi_uduk__presented_in_a_healthy_and_appetizing_way._The_rice_is_white__fluffy__and_infused_with_coconut_milk__served_with_an_a.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4993334/original/5900_1730892238-DALL__E_2024-11-06_18.13.01_-_A_delicious_and_healthy_Indonesian_gado-gado_dish_served_on_a_plate._The_dish_features_vibrant__colorful_ingredients_like_blanched_green_beans__shredd.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4992558/original/055117100_1730862025-fried-chicken-tendon-serve-with-sauce.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010215/original/9200_1731903886-DALL__E_2024-11-18_11.21.28_-_A_realistic_close-up_of_fresh_green_stink_beans__Parkia_speciosa___also_known_as_petai__displayed_in_an_artistic_arrangement._The_beans_are_shown_both.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011349/original/068997400_1731980815-pexels-xmtnguyen-2664221.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5005449/original/029986600_1731580532-pexels-laarkstudio-13499754.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956033/original/000450000_1727615395-SGV8394.JPG)
![Salsabila Karsawinata Founder dan Coach Salsalivefit. [@salsavinandita]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/8-c19f1z2YmQAK91n6NRg19yEXI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4953767/original/026021300_1727338436-image_123650291_2053_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016705/original/043770800_1732230233-PERSONAL_STYLE_-_Febby_Rastanty__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994919/original/098462400_1730968814-FIMELA_FASHION_-_THE_WAY_SHE_WEARS_IT_WITH_LOEWE__IG_FEED.jpg)
![Lihat di sini tampilan glamor Marshada dengan gaya old hollywood di pemotretan terbaru. [@riomotret].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/7QoC1hvf6nBlU-3iwI2dd6kmDhg=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4966556/original/068171700_1728642180-Snapinsta.app_462598825_18464089717030499_6711654336387563985_n_1080__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4948469/original/092414300_1726801989-IMG_8194_re__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4948776/original/028552100_1726815806-FIMELA_FASHION_-_BUILT_TO_WIN_WITH_ALO__IG_Feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5014712/original/030399200_1732104518-Screenshot_2024-11-20_171959.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015546/original/089040000_1732165653-trending_topic.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4980759/original/086822200_1729941100-Screenshot_2024-10-25_110200.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016880/original/037822600_1732244158-IMG_0084.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4974905/original/027641600_1729510983-Screenshot_2024-10-21_182932.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016866/original/058611300_1732243729-IMG_0508.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017590/original/060192500_1732276166-Hello_NYC.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994680/original/000904800_1730955880-pexels-fotios-photos-2773854.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017406/original/006018900_1732266751-Screen_Shot_2024-11-22_at_15.53.12.jpg)
![Festival Film Indonesia 2024 tak hanya dihiasi dengan aktor Tanah Air yang kenakan kebaya. Laura Basuki hingga Anggi Marito buktikan tetap menawan meski tanpa kebaya [@laurabas @sharazaa @anggimarito]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/5KpbS-uvLoIOiynGtPvyAF8TepM=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017380/original/026884600_1732265576-Picsart_24-11-22_15-37-17-415.jpg)