Diantra Irawan tak tahu apakah ceritanya dapat menginspirasi tetapi Cosmo tetap ingin membagi ceritanya, terutama bagi Anda yang takut untuk bangkit lagi lantaran kondisi hidup yang kekurangan...
Jangan kira tak punya apa-apa itu sesuatu yang senantiasa membawa sial – justru kebalikannya, the “power” of not having anything menjadi pemicu perubahan dalam hidup saya, menggerakan saya untuk mencapai apa yang saya benar-benar inginkan dalam hidup.
Cukup ironis sebenarnya. Betapa hidup saya penuh dengan struggle, padahal kalau mau menuruti kemauan keluarga, selepas sekolah saya sudah masuk fakultas kedokteran, lalu mengikuti jejak Ayah – dan Ibu – saya menjadi tokoh yang sangat sukses dan influental, tak hanya di tempat saya di Makasar, tapi juga sampai luar negeri (Ayah saya pernah masuk majalah TIME). Dan mereka pun memang menuntut saya untuk mengikuti jejak mereka, untuk “menjadi” mereka. Tapi entah kenapa, semua tiga anaknya – terlebih saya anak paling sulung! – tak ada yang berminat. Saya tak tahu mengapa, tapi yang saya tahu jiwa saya tidak di sana.
Advertisement
Dan menjadi anak seorang yang sangat terpandang, ada enak dan tidak enaknya. Semua orang jadi tahu siapa saya, dan kalau saya dibilang pintar, pasti komentarnya, “Ya iyalah pintar, kan dia anaknya si Dr.X.” Tapi kalau tahunya tidak pintar? Hmm, belum pernah ada yang bilang langsung ke wajah saya sih, tapi pasti komennya, “Kok bisa ya, dia kan anaknya si Dr.X...” Mungkin saja, kan? That’s why I needed to get away. Selepas sekolah saya memutuskan untuk keluar dari Makasar dan memiliki kuliah di Bandung. Jurusan yang saya ambil pun sebenarnya cenderung ngasal: Hukum, karena saya pikir itu adalah salah satu jurusan yang “umum”.
The Sound of Music
Nah, di Bandung inilah saya mulai iseng-iseng belajar musik secara otodidak. Kalau Anda pikir I’m a social person dan jadi suka nge-band sana sini, well you’re wrong. Saya bukan tipe anak gaul, dan saya cukup menganggap serius mata kuliah yang saya pelajari, makanya nilai-nilai saya cukup bagus. Pengalaman pertama saya nge-band sendiri tidak sengaja: Berawal dari memiliki pacar yang bekerja sebagai Event Organizer, saat itu ia sedang kelimpungan mencari band untuk acara yang akan ia selenggarakan. Entah kenapa, saya langsung menawarkan diri. Why? Karena selama ini di kosan saya sering menghabiskan waktu mendengarkan lagu-lagu dari Feist, dan, saya berpikir, hmm, sepertinya saya bisa deh menyanyi seperti itu. Her voice sound so simple yet memorable. Pacar saya awalnya ragu-ragu, tapi setelah saya setengah memaksa, akhirnya ia pun mengiyakan. Saya langsung mengajak teman-teman dan adik saya dari Makasar yang sekarang juga kuliah di Bandung. Kita tidak pernah perform dan beberapa bahkan ada yang tak menguasai alat musik satu pun (termasuk adik saya!), tapi kita memiliki keberanian, and so the show must go on.
Well, mungkin bagi beberapa anak band beneran, tampil di acara yang sepi penonton merupakan sesuatu yang bisa bikin drop – but not for us! Ya, memang acaranya super sepi, but we were happy doing it. Terutama saya, yang merasa, hmm, rasanya saya suka dunia ini, dan mungkin saya bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang serius.
A Rushed Marriage
Tapi niat untuk serius di jalur musik untuk sementara mesti menunggu dulu selepas kuliah. Saya sempat bekerja di beberapa tempat, termasuk di sebuah law firm. Tapi sesekali, saya juga tetap nge-band di beberapa acara. Dan saya menikah. Yup, I was married. Tak lama selepas kuliah, saya menikah dengan seorang pria yang juga anak band yang baru saya kencani selama beberapa bulan. Alasan untuk menikah pun sebenarnya sangat tidak romantis: Saya didiagnosa memiliki sebuah tumor di rahim. Opsi untuk menanganinya hanya dua: Pertama, rahim mesti diangkat; kedua, saya mesti buru-buru punya anak supaya tumor tersebut bisa secara natural dikeluarkan. Akhirnya pacar saya mencetuskan ide tersebut dengan kasual, “Ya sudah, kita married saja kalau begitu”, dan saya pun, walaupun penuh keraguan (“Am I ready?”), hanya bisa menjawab, “Oke”.
And so we got married, dengan persetujuan penuh dari keluarga. Walaupun awalnya saya malu mengakuinya, tapi...it was unhappy marriage. Namun setidaknya saya memiliki anak (saya mengandung tak lama setelah menikah), whom I love to death! Selama pernikahan ini, hanya saya yang bekerja, sementara dia hanya leha-leha di rumah, tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu mengapa dia seperti itu, mungkin karena dia sebagai musisi sangat idealis. Saya tidak tahu, I don’t understand him. Maka untuk menghidupi rumah tangga ini, saya sampai memiliki tiga pekerjaan! Pertama, sebagai staf di bagian HRD di salah satu bank ternama; kedua, it’s quite embarassing, tapi saya tetap di kantor yang sama dan bekerja tapi sebagai telemarketer, jadi malam-malam saya akan pindah divisi; dan ketiga sebagai asisten dosen di kampus.
Walau begitu, selama dua tahun pernikahan, saya tak pernah mendapatkan apresiasi dari suami. Pernah, setibanya di rumah dengan tubuh yang sangat lelah, saya menyapa dia yang sedang selonjoran di sofa nonton TV. Tapi dia sama sekali tidak membalas sapaan saya – ia tetap cuek menonton TV. Saya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Selama dua tahun kami menikah, attitude yang dia berikan seperti itu. Sampai akhirnya, waktu bulan puasa, hanya ada dia dan saya di rumah, anak bersama kakek-neneknya di Makasar. Mendapatkan berita menggembirakan kalau saya diterima di perusahaan baru, saya pun langsung memberitahukan dia, hoping that I could share the excitement. Tapi apa yang terjadi? Malah luapan amarah yang saya terima tanpa saya tahu alasannya. Tentu saya tidak terima, dan akhirnya kami pun bertengkar sengit. Selama pertengkaran, saya sempat bersyukur anak saya tidak ada di sana, karena setidaknya ia tidak mendengar kata-kata abusive yang ia lemparkan ke saya. Sampai akhirnya, ia mengusir saya keluar dari rumah, dan ia tidak mengijinkan saya untuk kembali lagi. Saya bingung, dan juga takut – what just happened? Tak tahu mesti berbuat apa. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke tempat adik saya, di mana saya menghabiskan waktu lama di sana, meratapi kondisi hidup. Perasaan itu tetap saya bawa ketika saya kembali lagi ke Makassar. But at least I get to meet my son, which is comfort.
Pada saat itulah saya mulai menyadari...I have nothing. Padahal selama ini saya membanting tulang bekerja di tiga tempat, tapi...mana hasilnya? Ketika melihat saldo di bank, sepertinya hanya cukup untuk hidup sebulan, dan, saya bisa mengambil jalan pintas keluarga, tapi saya tak mau terus-terusan menggantungkan diri ke mereka. Saya tak punya tabungan, tak punya asuransi. Yang saya punya hanyalah lima pakaian dan satu sepatu – sisanya tetap tinggal di rumah suami. Saya pun mulai mengintrospeksi diri, I mean...I’m smart, nilai IPK saya tergolong tinggi di kampus, so why do I settle for less? Realisasi the power of not having anything begitu “membangunkan” saya dari alur hidup yang sepertinya saya jalani begitu-begitu saja.
Picking Up The Pieces
Pertama-tama, saya menceraikan suami saya (a big relief!), lalu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 saya, dan, thank God, saya berhasil melakukannya dengan menerima beasiswa. Lalu bersama band, saya mulai mengikuti kompetisi musik, dan di salah satu kompetisi musik independen yang terkenal, band kami berhasil keluar menjadi juara utama, dan kami mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 10 juta! That was one of my proudest moment.
Namun, di luar bermain musik, saya juga memikirkan sesuatu yang lebih serius. Saya ingin memiliki sebuah agency musik sendiri yang dapat menampung musisi-musisi berbakat di Bandung yang tidak tahu cara mendapatkan exposure. Mengapa saya memilih ini? Karena berdasarkan pengamatan saya saat berbaur dengan orang-orang di industri musik di Bandung, sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa membuat lagu-lagu mereka dikenal di acara-acara musik lokal. Walaupun ada, tapi mereka hanya tahu sistem royalti, atau “jual putus”, lalu setelahnya, miliki studio. Saya ingin mereka bisa membagi talent mereka dan bagaimana cara me-maintain hasil karya dari talent mereka tersebut. Saya ingin lebih mendewasakan industri musik di Bandung.
Klien-klien saya adalah teman sendiri, yang secara personal saya ajak untuk ikut gabung. Markasnya? Terpaksa saya mengadakannya di luar, karena saya tinggal di sebuah kosan yang kecil mungil. Tapi selain para musisi, saya juga ingin mengangkat kesejahteraan orang-orang di belakang industri musik, seperti para crew dan soundman – orang-orang “kecil” yang selama ini hanya menerima uang, tapi setelahnya hanya berakhir di sana. Setidaknya saya ingin mereka mendapatkan kepastian “jatah” juga, ini berarti menerima slip gaji. Saya tidak ingin mereka bekerja keras, but have nothing to show for their hard work.
Jalan saya tentu tak mulus pada awalnya, apalagi karena saya seorang wanita, yang di industri ini jarang sekali ada yang berperan di garda depan. Terkadang saya akan bertemu dengan orang-orang penyelenggara atau dari record label yang meremehkan saya semata karena saya wanita, lalu menganggap saya akan menuruti semua kemauan mereka. But not me, saya akan berusaha keras untuk bernegosiasi, apabila tidak bisa mendapatkan semuanya, setidaknya bisa mencapai kompromi yang akan membuat senang kedua belah pihak. (Ya, disinilah latar belakang hukum saya berperan besar) Terkadang saya merasa melakukan ini karena...I needed to prove something, bukan untuk orangtua saya, tapi lebih untuk diri sendiri. Dan, tepat setahun setelah saya merasa tidak punya apa-apa dalam hidup, saya sukses merubah hidup saya. Klien-klien yang saya pegang bisa meroket namanya tak hanya di kalangan penikmat, tapi juga di antara pelaku industri musik, beberapa bahkan bisa command fee yang tinggi saat pentas. Yang pasti, saldo di bank sudah bisa mendukung hidup saya lebih dari sebulan, dan saya bisa keluar dari kosan saya yang mungil dan sekarang saya bisa mencicil rumah dan mobil. Isn’t it amazing what the power of not having anything can do to you?
Source : Cosmopolitan Edisi Januari 2013 Halaman 198
(vem/Cosmo/dyn)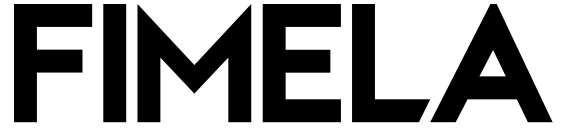

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2426741/original/094275400_1542915723-20528-tadinya-saya-tak-punya-apa-apa-092357.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017053/original/075009000_1732250521-FD2025-1500x845.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995209/original/026181100_1730986853-Screenshot_2024-11-07_202711.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4988253/original/058148800_1730511774-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5000607/original/4300_1731314395-DALL__E_2024-11-11_15.06.03_-_A_plate_of_healthy_homemade_dimsum_served_in_a_clean__child-friendly_style._The_dimsum_is_small__round__and_wrapped_neatly_in_thin_skins__filled_with_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4996154/original/022707900_1731067406-pexels-jsalamanca-61127.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5014358/original/0800_1732092222-DALL__E_2024-11-20_15.31.31_-_A_plate_of_Indonesian_nasi_uduk__presented_in_a_healthy_and_appetizing_way._The_rice_is_white__fluffy__and_infused_with_coconut_milk__served_with_an_a.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4993334/original/5900_1730892238-DALL__E_2024-11-06_18.13.01_-_A_delicious_and_healthy_Indonesian_gado-gado_dish_served_on_a_plate._The_dish_features_vibrant__colorful_ingredients_like_blanched_green_beans__shredd.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4992558/original/055117100_1730862025-fried-chicken-tendon-serve-with-sauce.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010215/original/9200_1731903886-DALL__E_2024-11-18_11.21.28_-_A_realistic_close-up_of_fresh_green_stink_beans__Parkia_speciosa___also_known_as_petai__displayed_in_an_artistic_arrangement._The_beans_are_shown_both.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956033/original/000450000_1727615395-SGV8394.JPG)
![Salsabila Karsawinata Founder dan Coach Salsalivefit. [@salsavinandita]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/8-c19f1z2YmQAK91n6NRg19yEXI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4953767/original/026021300_1727338436-image_123650291_2053_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016705/original/043770800_1732230233-PERSONAL_STYLE_-_Febby_Rastanty__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994919/original/098462400_1730968814-FIMELA_FASHION_-_THE_WAY_SHE_WEARS_IT_WITH_LOEWE__IG_FEED.jpg)
![Lihat di sini tampilan glamor Marshada dengan gaya old hollywood di pemotretan terbaru. [@riomotret].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/7QoC1hvf6nBlU-3iwI2dd6kmDhg=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4966556/original/068171700_1728642180-Snapinsta.app_462598825_18464089717030499_6711654336387563985_n_1080__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4948469/original/092414300_1726801989-IMG_8194_re__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4948776/original/028552100_1726815806-FIMELA_FASHION_-_BUILT_TO_WIN_WITH_ALO__IG_Feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021564/original/032042200_1732594573-young-charming-sensual-girl-listening-music-headphones.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4894752/original/011738700_1721274195-ilustrasi_ibu_dan_anak-20220624-035-adrian.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021278/original/014465200_1732584630-IMG_0129.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020027/original/083362600_1732503316-DSC01406.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020018/original/037904200_1732502827-DSC01470.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020012/original/096909000_1732502154-DSC00947.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021564/original/032042200_1732594573-young-charming-sensual-girl-listening-music-headphones.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021047/original/051385700_1732552759-WhatsApp_Image_2024-11-25_at_22.30.09.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021566/original/007985100_1732594635-p_headline_deretan-drama-korea-chae-soo-bin-yang-m-aaa343.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021356/original/004175000_1732588314-IMG_0571.JPG)