Advertisement
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2167714/original/030492200_1525678093-152567809372839why-3.jpg) Hari pertama: gagal itu…biasa!
Hari pertama: gagal itu…biasa!
Ketakutan nggak bisa menyelesaikan deadline karena liputan dadakan dan narasumber nggak bisa dihubungi sangat mengganggu pikiran dan membuat saya nggak bisa berkonsentrasi. Hasilnya, saya benar-benar nggak bisa menyelesaikan deadline, padahal nggak ada alasan untuk panik karena nggak ada satu pun hal yang saya khawatirkan itu terjadi. Kesimpulannya, kecemasan bertumpuk yang menghambat semuanya, bukan keadaan. Saya gagal, tapi saya belajar bahwa kegagalan sebenarnya bisa dicegah dengan pikiran positif. Pikir saya, inilah saat tepat menggunakan why not dan jauh-jauh dari kata what if yang menjebak.
Hari kedua: biar gagal tetap nekat…
Advertisement
Saya paling lemah dalam urusan menghapal jalan. Karenanya, hari berikutnya saya tertantang mencoba jalan yang belum pernah saya lewati sebelumnya, sekadar iseng. Bagaimana kalau nyasar, bagaimana kalau masuk jalur yang salah dan kena tilang, bagaimana, bagaimana, dan bagaimana lainnya. Saya pun menjawab semua pertanyaan itu dengan satu kata, nekat. Dan kenekatan saya ini berbuah hasil positif. Dua kali salah jalan, saya malah menemukan jalan alternatif yang lebih nyaman untuk pergi-pulang kerja. Selain itu, adrenalin yang terpacu, percampuran antara semangat, rasa cemas, dan was-was ternyata bikin hari ini jadi luar biasa. Kalau hal-hal baru ternyata nggak separno yang dibayangkan dan malah bikin hari nggak biasa, kenapa nggak coba terus berinovasi?
Hari ketiga: budayakan nekat, kenapa tidak?
Kalau nanti begini, kalau nanti begitu, kalau nggak begini, kalau nggak begitu….lama-lama waktu kita habis memikirkan apa yang sebenarnya belum dan mungkin nggak akan terjadi. Pikiran kita seringkali jadi pembunuh semangat yang andal, apalagi ketika belum mulai berjuang saja sudah dimentahkan oleh pikiran negatif diri sendiri. Memang nggak ada salahnya menyiapkan kemungkinan terburuk, asalkan kemungkinan itu nggak membuat kita malah jadi stuck dan takut move on. Jadi, nggak salah membudayakan nekat pada diri sendiri untuk membiasakan diri berpikir out of the box. Saya mendapatkan hal ini setelah melewati dua hari kemarin, sambil berpikir mau belajar apa lagi besok.
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2167715/original/073440300_1525678093-152567809379242why-1.jpg)
Hari keempat: berpikir logis
Hari berikutnya saya bertekad pulang cepat, hadiah untuk diri sendiri yang minggu ini cukup lelah. Saya memang berhasil pulang cepat dari kantor, tapi ada satu hal yang jadi masalah, bensin saya habis. Ada dua pilihan pom bensin. Pertama, tempat biasa saya mengisi bensin, yang paling dekat dengan rumah tapi antrenya bukan main. Kedua, sedikit lebih jauh tapi lebih sepi ketimbang pom pertama. Karena sudah terbiasa di pom pertama, juga takut terlalu jauh berjalan padahal sama jumlah antreannya, saya memilih opsi pertama. Seperti dugaan, antrenya lumayan lama. Belum selesai di situ, ternyata jalan yang biasa saya lewati ditutup, alhasil saya harus sedikit memutar jalur, melewati pom kedua yang memang jauh lebih sepi. Menyesal mengantre lama dan tetap berjalan lebih jauh untuk pulang, saya tahu kekhawatiran nggak beralasan itulah yang membuat saya nggak bisa berpikir logis. Sudah ada fakta jelas, masih saja lebih mempercayai apa kata hati. Sekali lagi, kenapa nggak nekat mencoba lari dari kebiasaan kalau hal baru terbukti bisa lebih menguntungkan?
Advertisement
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2167716/original/015899500_1525678094-152567809411417why-2_0.jpg)
Hari kelima: belajar dari laki-laki
Laki-laki juga nggak sepenuhnya lepas dari rasa khawatir, tapi kekhawatiran mereka masih dalam tahap wajar dan nggak berlebihan seperti perempuan, yang sampai membayangkan hal paling buruk (atau lebih buruk dari yang mungkin terjadi!). Dalam Women Who Worry Too Much: How to Stop Worry & Anxiety from Ruining Relationships, Work, & Fun, Holly Hazlett-Stevens menjelaskan, perempuan dikenal hobi memelihara kekhawatiran, berbeda dengan laki-laki yang cenderung berpikir logis mengatasi rasa khawatir itu. Menurut Steven Rhoads dalam Taking Sex Differences, semua itu ada penyebabnya. Pada zaman prasejarah, laki-laki bahkan nggak sempat berpikir “bagaimana kalau” atau “seandainya” ketika berburu. Mereka dituntut siap dengan segala risiko yang ada, tanpa pilihan. Sementara perempuan lebih sering merasa tegang dan khawatir ketika berjaga-jaga melindungi anaknya.
Tapi, kita nggak bisa menerima keadaan begitu saja. Karena belajar itu seru, ada untungnya juga kan, mencontek cara pandang laki-laki dan mencoba meminimalisasi kekhawatiran kita. Ayah saya tipe yang lebih tenang sehingga terkesan cuek. Berbeda dengan ibu yang lebih ekspresif. Ketika adik saya sulit dihubungi saat pergi bersama teman-temannya, ibu panik bukan main dan mulai berpikir terlalu jauh, sementara ayah saya lebih tenang dan mencoba berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang positif. Dari sana saya belajar seperti ayah untuk nggak mudah panik dan tetap berpikir logis, sementara dalam hal perhatian, ibu tetap yang nomor satu.
Hari keenam: kenapa tidak?
Pernah merasakan bedanya saat nekat melakukan sesuatu dan saat nggak yakin mau mencoba atau pilih menghindar? Kecemasan sama-sama kita rasakan, tapi mana yang lebih melegakan setelahnya? Lagi-lagi nekat! Ibarat belajar menyetir, ketika nggak ada keyakinan untuk maju, kamu nggak akan bisa mengendalikan kendaraan. Dan ketika kamu percaya diri, dengan cepat kamu bisa menguasai jalanan. Itu semua hanya masalah nyali. Ya, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak mencoba menjalaninya, tapi sangat sayang ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan terlanjur kehilangan kesempatan untuk mencoba. Jadi, kalau harus total mengerjakan sesuatu dan membuang kekhawatiran jauh-jauh, kenapa tidak? Ini kesimpulannya: hari keenam mencoba berpikir lebih terbuka ternyata manjur ajarkan saya banyak hal baru dan bikin hidup lebih berwarna ketimbang terus ada dalam kecemasan berlebihan. Bagaimana, ingin merasakan hal yang sama?
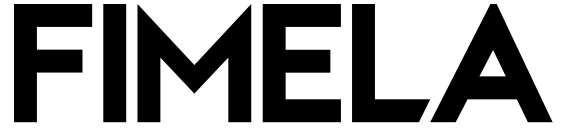

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055890/original/010999200_1734499535-HIGHLIGHT_FIMELA_DAY___IG_Feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055880/original/002353200_1734499127-HIGHLIGHT_day_3__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055871/original/038409700_1734498725-HIGHLIGHT_day_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055859/original/051857100_1734498130-HIGHLIGHT_day_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5036378/original/013812700_1733385978-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5032977/original/073652000_1733197790-FOTO_1.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5031960/original/055405000_1733118903-pexels-katerina-holmes-5905614.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5031999/original/051831100_1733119838-pexels-kampus-6481588.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033284/original/035244200_1733206299-pexels-rdne-10432436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5027652/original/7400_1732847912-DALL__E_2024-11-29_09.35.47_-_A_beautifully_arranged_plate_of_low-calorie_fried_tempeh__featuring_golden-brown_tempeh_slices_with_a_crispy_coating__lightly_dusted_with_herbs__serve.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5026609/original/066591600_1732775597-pexels-trista-chen-198334-723198.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5022621/original/4800_1732604869-DALL__E_2024-11-26_14.02.31_-_A_plate_of_low-calorie_shrimp_sambal_with_lemongrass__presented_in_a_kid-friendly_style._The_dish_includes_peeled_shrimp_cooked_in_a_light_red_sambal_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033038/original/000687200_1733198738-Snapinsta.app_468983269_422604517585625_3930891875784389755_n_1080.jpg)
![Seniman Galuh Anindita menciptakan aksesori yang diberi nama Mahija. [dok. Galuh Anindita]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WTXk5rkAsLcLcYIG39cRqwfZn1A=/0x1157:2624x2636/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035276/original/041670100_1733312960-FOTO_PROFIL_SENIMAN_-_GALUH_ANINDITA_WARDANA.JPG)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058958/original/065333600_1734685101-IMG_4392.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034833/original/043480800_1733296555-FIMELA_FASHION_-_BOUNDLESS_BEAUTY_WITH_WEEKEND_MAXMARA__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033477/original/089964900_1733210907-IMG_8172__1_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016705/original/043770800_1732230233-PERSONAL_STYLE_-_Febby_Rastanty__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994919/original/098462400_1730968814-FIMELA_FASHION_-_THE_WAY_SHE_WEARS_IT_WITH_LOEWE__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5052083/original/029880900_1734324123-beautiful-bright-girl-pink-t-shirts-blue-jeans-sitting-sunny-summer-park.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5052063/original/031487600_1734323157-portrait-beautiful-asian-woman-posing-city-while-wearing-yellow-dress.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059629/original/036752400_1734746718-DSC02196.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017641/original/013684000_1732277707-Screenshot_2024-11-22_190947.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059624/original/022482300_1734746051-DSC02409.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5059614/original/079724000_1734745523-IMG_1248.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5052083/original/029880900_1734324123-beautiful-bright-girl-pink-t-shirts-blue-jeans-sitting-sunny-summer-park.jpg)
![Lihat di sini tampilan Kahiyang Ayu sambut akhir tahun 2024. [@ayanggkahiyang].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/1iyN8yI0MwkoTaQ10yr7KwVFrVw=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5061129/original/042316600_1734825487-Snapinsta.app_470897395_8996324443816254_3232927263193590375_n_1080__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034068/original/060842900_1733239315-WhatsApp_Image_2024-12-03_at_22.20.53_c966d405.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5052063/original/031487600_1734323157-portrait-beautiful-asian-woman-posing-city-while-wearing-yellow-dress.jpg)