Fimela.com, Jakarta Memutuskan untuk menjalani operasi kelamin atau yang juga disebut RS, GRS, GCS-Sex Reassignment Surgery sebenarnya adalah pilihan yang sifatnya sangat pribadi. Sama dengan pilihan mau hidup sehat, atau nggak sehat.
Perkara operasi kelamin nggak berhenti sampai pro dan kontra yang kerap dikaitkan dengan moral dan sudut pandang masyarakat. Tapi masalah ini jauh lebih luas. Memutuskan untuk mengganti identitas seksualnya, dan menajalani operasi kelamin nggak mudah.
Advertisement
BACA JUGA
Apa lagi di negara-negara Asia dan belahan bumi lainnya yang masih belum bisa menerima dan melegalkan LGBTQ. Kalau pun bisa, ada banyak prosedur yang harus mereka lalui. Dilansir dari The Public Discourse, nggak semua orang yang ingin menganti gender boleh langsung menjalani operasi kelamin.
Di Amerika Serikat, calon 'pasien' (meskipun katanya LGBTQ bukan penyakit, tapi di kasus ini mereka akan menjalani operasi di rumah sakit yang dilakukan oleh ahli bedah kelamin dan saluran kencing yang handal. Jadi saya pikir nggak apa-apa menyebut mereka pasien) harus berkunjung ke transgender psychiatrist, untuk mengetahui apakah 'pasien' tadi mendapat diagnosa gender dysphoria.
Dilansir dari Hello Sehat, gender dysphoria merupakan suatu kondisi yang diderita orang-orang yang dikenal dengan sebutan transgender, di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan atau rasa tertekan karena ada ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender mereka.
Proses konsultasi ini nggak berjalan dengan singkat. Pasien biasanya harus terus-menerus melakukan konsultasi. Bahkan, the Public Discourse, proses ini bisa memakan waktu tahunan. Baru setelah ada diagnosa gender dysphoria, pasien bisa mengajukan dan menjalani operasi kelamin.
Tapi sayangnya, kehidupan usai operasi besar yang menguras banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga dompet, belum tentu lebih baik dan membuat mereka lebih bahagia. Dilansir dari the Guardian, lebih dari 100 penelitian kedokteran internasional mengenai keadaan pasien paca operasi yang dilakukan the University of Birmingham Aggressive Research Intelligence Facility menunjukkan, tidak ada bukti ilmiah yang kuat kalau operasi kelamin efektif secara klnis.
Karena, setelah jangka waktu yang lama, sekitar 15 tahu usai menjalani operasi, banyak dari mereka yang mengalami depresi. Mereka merasa nggak bahagia dan kecewa dengan apa yang sudah mereka lakukan. Banyak dari mereka yang ingin kembali ke gender mereka seperti semula. Ujung-ujungnya mereka lari ke minuman keras, depresi dan mengalami gangguan mental lainnya, bahkan melakukan banyak percobaan bunuh diri.
Eksklusif, Proses Dena Rachman Jadi Transgender
Advertisement
Operasi Kelamin Belum Tentu Jadi Solusi Efektif
Jadi, pada awalnya, tulis the LGBTQ Nation, para psikiater dan dokter ahli bedah memberikan fasilitas operasi kelamin sebagai jawaban dari 'perihnya' mengalami gender dysphoria. Betul mereka merasa 'terperangkap' di dalam tubuh yang salah. Mereka depresi karena merasa diri mereka bukan diri mereka yang sesungguhnya.
Tapi, hasil penelitian yang sudah disebutkan di atas menunjukkan kalau operasi kelamin nggak efektif lantaran banyak transgernder di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa menyesal telah menjalani operasi kelamin. Sebagian juga ada faktor lain seperti medical care di sana nggak bisa membanti para transgender ini menjalani kehidupan yang baru usai operasi.
Chris Hyde, direktur dari Arif mengatakan kepada the Guardian, jumlah para transgender yang mengalami trauma usai operasi sangat banyak. Ada yang menyesal karena meskipun sudha berfisik seperti perempuan, mereka tetap tidak bisa melahirkan anak.
Ada juga yang justru mendapatkan perlakukan buruk dari masyarakat sekitar. Dan ini merupakan masalah baru yang timbul lantaran kegegabahan tim psikiater dan juga dokter yang mengoperasi. Atau simply karena mereka sebenarnya nggak butuh operasi kelamin untuk bisa coping dengan diforia gender yang mereka miliki.
Masalahnya, tulis LGBTQ Nation, psikiater dan dokter langsung memutuskan dan memberi izin bagi mereka untuk menjalani operasi kelamin. Beberapa tahun usai operasi, mereka memang akan terlihat dan mengaku lebih nyaman serta bahagia. Tapi setelah 10-15 tahun, mereka mulai mengalami berbagai gangguan kejiwaan. Mulai dari anxiety, stres, depresi, dan bahkan suicidal.
Nggak sedikit yang akhirnya mengakhiri hidup usai berganti gender dan alat kelamin. The Public Discourse menulis, 41 persen transgender melaporkan kalau mereka pernah melakukan percobaan bunuh diri. Angka ini besar, bahkan 25 kali lebih besar dari angka percobaan bunuh diri pada populasi umum. Lantas, siapa yang harus disalahkan?
Untuk bisa menjalani operasi ini, pasien membutuhkan 'izin' dari psikiater dan dokter berupa diagnosa. Gender dysphoria. Tapi masalahnya, ada banyak masalah kejiwaan lain yang mereka miliki selain disforia gender ini. The problem is, not many people know that those things may lead to gender dysphoria.
Saya bukan psikiater. Bukan dokter. Bukan juga seorang transgender. Tapi sebagai sesama manusia, tentu saja ini menjadi perhatian. Bukan cuma bagi saya, tapi juga orang lain yang begitu peduli dengan angka kematian akibat bunuh diri di dunia ini. Tapi izinkan saya berangan.
Kalau saja proses berbincang-bincang dengan dokter dilakukan lebih lama untuk melihat dan menimbang, apakah memang perlu dilakukan operasi kelamin, mungkin angka kematian dan juga angka percobaan bunuh diri akan menurun di kalangan para transgender. Kalau saja mereka menemukan ada gangguan-gangguan kejiwaan lain yang (mungkin) menjadi trigger munculnya disforia gender pada diri pasien, dan mengobati gangguan tersebut terlebih dahulu, mungkin juga angka dilakukannya operasi kelamin nggak setinggi sekarang ini.
Tapi ini cuma angan. Di negara saya, banyak yang lebih mementingkan komentar pedas di postingan IG para transgender. Angka kematian tinggi mah bukan urusan kita.
Karla Farhana,
Editor Sex and Health Bintang.com
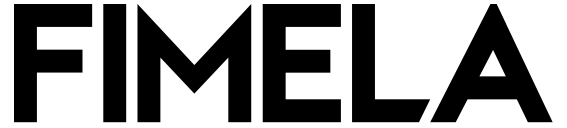
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/351016/original/021495500_1436056011-AkXoOdTcG-18WQxjC_ZSS1ipEecOqNRANZDdqe9zK4qZ__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2032721/original/014053500_1522062165-iStock-823410672.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2032095/original/066467400_1522052801-6-Fakta-tentang-Operasi-Kelamin-By-nimon-shutterstock.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446056/original/088244600_1765871776-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2995662/original/061514500_1576230464-juliana-malta-YwutubGmzSU-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5434439/original/085265100_1764927392-Depositphotos_835881408_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452175/original/053343100_1766388567-front-close-view-young-attractive-female-white-t-shirt-doing-make-up-with-slight-smile-pink-background.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446721/original/005950600_1765939085-IMG-20251217-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411995/original/098546600_1763028037-IMG_3023-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437620/original/023028500_1765258087-Depositphotos_804339058_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444636/original/037285600_1765784303-Desain_tanpa_judul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437822/original/092774500_1765264784-Depositphotos_618867182_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430234/original/024751500_1764656701-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430246/original/078844100_1764656929-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.55.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421696/original/066687600_1763957022-pexels-polina-tankilevitch-5468719.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421809/original/040895800_1763960008-pexels-emil-kalibradov-3013808-7085779.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4598468/original/048272600_1696412875-pexels-ketut-subiyanto-4473774.jpg)
![Bersepeda merupakan olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular sekaligus memperkuat otot kaki. [Dok/freepik.com/jcomp]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/U3ODXnqLEwCzQainSPGnJX-m778=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5393086/original/042681400_1761541747-close-up-cyclist-woman-outdors.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5392971/original/044473200_1761538233-young-children-making-diy-project-from-upcycled-materials.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5450270/original/033756400_1766135930-Foto_2__5_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448250/original/093199600_1766024444-Screen_Shot_2025-12-18_at_09.16.02.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449052/original/021526200_1766046562-1280x847_px.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5373277/original/017310400_1759817607-Depositphotos_727499338_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5350322/original/077529400_1757996584-Depositphotos_748346252_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5214847/original/019381000_1746781436-0E6A3471-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445780/original/091527900_1765864739-Depositphotos_209673936_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5326460/original/099516800_1756102918-Depositphotos_225996612_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5347725/original/027946100_1757731962-Depositphotos_743561216_XL.jpg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452932/original/013300800_1766463176-Depositphotos_828456356_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4480557/original/011177200_1687687972-vivek-kumar-a-_1PPjnbUg-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3200839/original/019897300_1596697245-Photo_by_Hello_Revival_on_Unsplash__2_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4445544/original/006659900_1685354565-ann-danilina-c_rnPbSYVFM-unsplash-min.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5304819/original/024259400_1754286750-polina-lavor-Uf4ti10VMgY-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5276665/original/038631000_1751959019-ashton-bingham-SAHBl2UpXco-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452876/original/099231900_1766461807-FIMELA_FASHION_-_Lanvin_at_Its_Most_Glam__IG_Feed__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1850759/original/071249300_1517310694-PicsArt_01-30-05.55.57.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5303081/original/010753100_1754044504-1000408667.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1817306/original/097946200_1514746860-Kembang-Api-Monas1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5406416/original/006889800_1762572152-Kapolri.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5453537/original/091898000_1766480835-WhatsApp_Image_2025-12-23_at_16.05.14.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5192462/original/050458400_1745140716-6532fa38-c5db-48aa-94ae-60eccec5f5b3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5453630/original/026197100_1766483302-HUAWEI_MatePad_Air_Product_Creative_Lifestyle_Shot.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4947651/original/065426800_1726720377-wang-odds-qc703GaemGo-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5453507/original/089313300_1766479544-SnapInsta.to_604236621_18542113321050124_6155181722598152097_n.jpg)
![Amanda Manopo Jelang Natal Kenakan Head To Toe Serba Ungu. [@amandamanopo]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/vPVRJAb6MuUhyYvwP_rksKm1XFE=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5453416/original/070063600_1766477755-IMG_2680_1_.jpeg)