Fimela.com, Jakarta Hari di akhir Juli itu cukup cerah. Penerbangan pagi dari Kuala Lumpur ke Penang tak hanya diliputi cemas, lantaran si Wi-Fi portable yang disewa di tanah air belum mau terhubung, namun juga rasa kantuk. Maklum, mata baru terpejam sebentar di ruang tunggu Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 2.
Setelah masalah koneksi internet berhasil terpecahkan, saya bersama dua orang teman langsung bergegas ke sisi kiri bandara, tempat menunggu rapid (semacam bus di Malaysia) yang bakal membawa kami ke jantung George Town. Sepanjang perjalanan menuju utara, jujur, saya dibuat kaget dengan tempat yang juga dikenal dengan nama Pulau Pinang itu.
Advertisement
BACA JUGA
Sambil berbincang dengan orang Indonesia yang tengah membawa salah satu anggota keluarga berobat (ya, Penang memang dikenal sebagai salah satu tujuan berobat ke luar negeri bagi orang kita), juga sesekali berpegangan karena sopir rapid yang melajukan bus tak berbeda jauh seperti pengemudi kopaja di Jakarta, saya dibuat tercengang akan mewahnya seliweran mobil-mobil.
"Kuala Lumpur kalah ya," batin saya kala itu mengenang perjalanan tahun sebelumnya di ibu kota Malaysia. Usai mengisi perut dengan seporsi mee goreng kenamaan di Bangkok Lane, kami pun kembali naik rapid menuju hostel tempat bermalam di Love Lane.
Tak sulit untuk menemukan hostel tiga lantai, seperti kebanyakan gedung sekitar George Town, bergaya bangunan kolonial Inggris tersebut, lantaran Love Lane hanya merupakan satu jalan lurus yang ujungnya bisa terlihat dari sisi berlawanan.
Langkah pertama saya di Red Inn @ 39 memang sudah demikian ringan, juga menyenangkan. Bagaimana tidak, pernak-pernik Beatles, kebanyakan foto, terpampang di lobi hostel. Tapi, tak pernah saya menyangka keputusan menginap di si hostel merah akan mengantarkan pada kisah baru.
Lewat Traveling, Tarra Mengenal Karakter Gya Sadiqah saat dirinya Mengunjungi Melbourne.
Advertisement
Kisah Orang Asing di Tanah Asing
Masih di hari yang sama, singkat cerita, saya bersama dua orang teman baru saja pulang dari Gurney Drive Hawker Centre. Kami memang memilih kembali tak terlalu malam ke hostel karena ingin istirahat cukup. Membalas tidur kurang di malam sebelumnya.
Turun dari taksi online, lobi hostel ternyata cukup ramai. Saya agak kaget sebenarnya, mengingat saat datang hanya seorang lelaki paruh baya yang menyambut dan mengantarkan kami ke kamar di lantai dua. Tapi, sekarang ia tengah berbincang dengan setidaknya empat orang kawan yang saya duga berusia sebaya.
Awalnya, saya hanya bertukar senyum. Mereka membalas (tentu saja) dengan ramah, tapi tampak canggung. Karena ingin membeli minuman, kami duduk lah sejenak di bawah. Sambil meneguk lemon tea kaleng yang tak ada di Indonesia dan sungguh saya rindukan itu, telinga saya menangkap bunyi familiar.
"Ah, ini When I'm Sixty Four-nya The Beatles," pikir saya kala itu. Eh, tunggu dulu. Kok liriknya beda? Dari keinginan hendak bertanya (tadinya mau protes) itu lah kemudian percakapan terajut. Usut punya usut, mereka memang tengah mempersiapkan penampilan untuk reuni tahun depan dengan mengganti lirik lagu dari album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tersebut,
Pengakuan saya yang suka The Beatles kemudian ditimpali pertanyaan 'memang umurmu berapa?' dari uncle pemilik hostel dalam Bahasa Inggris. Suasana makin cair, sang uncle pemilik hostel bahkan membawakan lagu Beatles kesukaan saya.
Malam itu, setelah sekian lama, saya merasa kembali bisa membicarakan The Beatles dengan luwes, sangat luwes. Kalimat demi kalimat terucap, pengalaman dan jerit hati yang lebih pribadi terungkap setelah perbincangan kasual tersebut kemudian muncul.
Kotak-kotak Etnis di Malaysia
Salah satu uncle, saya lupa namanya siapa, menarik saya dalam percakapan tentang istri dan anaknya. Tentang ia yang baru saja pulang dari overland trip di Britania. Dengan antusias, ia memperlihatkan foto demi foto dan dengan begitu sabar, melayani pertanyaan-pertanyaan saya.
Dari perbincangan tersebut, saya sempat dibuat diam sejenak mendengar pernyataan dari si uncle. "Saya tak menyangka ada Muslim yang seterbuka ini berbicara," kurang lebih begitu lah ucapanya kala itu sambil menunjuk hijab yang saya kenakan.
Topik itu pun kemudian menarik perhatian beberapa temannya yang tengah asyik mengobrol dengan kedua teman saya. Dengan kompak mereka setuju dengan pernyataan tak pernah berbincang seperti ini dengan seorang Muslim, terutama perempuan.
Kamu mungkin juga mengetahui bila Malaysia setidaknya dihuni tiga etnis, yakni Melayu, India, dan Tionghoa. Kali pertama ke sana, saya memang merasakan jarak antar ketiga etnis tersebut, meski tak sedikit juga yang membaur dan mengobrol. Namun, jarang, sangat jarang.
Asumsi saya ternyata dibenarkan malam itu. Tentang perempuan Muslim Melayu yang tabu terlihat berjalan, apalagi saat malam, dengan lelaki bukan saudara atau keluarganya. Soal kotak-kotak pertemanan dengan orang yang itu-itu saja.
Dari bentukan budaya yang demikian, jadi sangat wajar bila pertemanan dengan satu etnis, terlebih mereka biasanya mengenyam jenjang demi jenjang pendidikan bersama, akan demikian erat. Opa-opa itu saja masih terus bertemu di usia mereka yang tahun depan menjejek 64 tahun (karena itu mereka pilih lagu The Beatles).
Sebagai orang luar, saya tentu tak bisa menarik kesimpulan siapa dalang dari tak berbaurnya tiga etnis penghuni Malaysia. Saya hanya bisa mendengarkan dan bersyukur bisa berbagi cerita. Jadi pelaku obrolan malam di hostel merah.
Cantik lanskap Penang tentu tak perlu diragukan lagi. Jajaran bangunan tua, lengkap dengan sederet makanan kaki lima yang super murah dan enak, siapa tak tergelitik mampir? Namun, tuturan kisah dari orang asing yang sama sekali tak terasa asing malam itu lah yang masih saya ingat hingga hari ini.
Kiranya penggalan memori ini bisa mengingatkan saya, kamu, kita bahwa perjalanan bukan hanya soal potret, namun juga kisah tiada terganti. Tanpa ada judgement. Tanpa ada penetapan kambing hitam, tanpa bukti. Karena kita hanya tamu di tanah orang.
Asnida Riani,
Editor Celeb Bintang.com
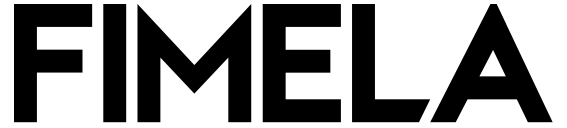
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/342404/original/077297200_1734360117-IMG_3333.jpeg)
![[Bintang] Malaysia](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/XYjp-P-gINELZ5OXDo4qIz1K1LI=/680x383/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1811573/original/076056200_1514109692-1.jpg)
![[Bintang] Malaysia](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/Nv4tZxTwjyUo2x9xdUqbwiI9oDA=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1387913/original/084542800_1477635177-10.jpg)
![[Bintang] Editor Says](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/lHvZNDglsoaFKsRqnt8rvVKOmFI=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1811606/original/083116800_1514114007-WhatsApp_Image_2017-12-24_at_5.54.33_PM.jpeg)
![[Bintang] Malaysia](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/1TATFQG9a2xHR033MAVPSTlaCBo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1387900/original/047969200_1477634410-7.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446056/original/088244600_1765871776-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446721/original/005950600_1765939085-IMG-20251217-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411995/original/098546600_1763028037-IMG_3023-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437620/original/023028500_1765258087-Depositphotos_804339058_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444636/original/037285600_1765784303-Desain_tanpa_judul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437822/original/092774500_1765264784-Depositphotos_618867182_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430234/original/024751500_1764656701-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430246/original/078844100_1764656929-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.55.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421696/original/066687600_1763957022-pexels-polina-tankilevitch-5468719.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421809/original/040895800_1763960008-pexels-emil-kalibradov-3013808-7085779.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3304346/original/025770100_1606121870-shutterstock_1819946462.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5160772/original/017170300_1741840102-Rambut_halus.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994359/original/026697200_1730937396-Depositphotos_513926280_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5433199/original/090502700_1764838758-Depositphotos_657162262_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5320875/original/030072700_1755656896-Depositphotos_286916248_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5365037/original/010459400_1759133617-solo_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5364747/original/028093100_1759124694-pexels-nurseryart-346885.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446804/original/060156400_1765942120-pexels-daan-stevens-66128-939331.jpg)
![Lebih dari sekadar operasional internal, AYANA Bali juga melibatkan tamu dan komunitas dalam praktik berkelanjutan. Melalui AYANA Farm, area organik seluas dua hektare yang menanam lebih dari 130 varietas tanaman, tamu diajak mengenal pertanian organik dan prinsip sirkular secara langsung. [Dok/AYANA BALI].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/wSxxi2Nh7Q1NJLtzjPIoJgHgF70=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445903/original/006242400_1765867564-AYANA_Farm_Farm_Walk_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3562465/original/037038200_1630905705-jeshoots-com-fp1x-X7DwDs-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3154779/original/030653900_1592367704-8918.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5443189/original/085604800_1765630381-IMG_2367.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5386677/original/013317800_1761019831-Depositphotos_759464940_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444779/original/096627700_1765788691-Depositphotos_305463478_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5299574/original/048097200_1753844577-Depositphotos_735660458_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444831/original/095331300_1765790013-Depositphotos_507090168_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5251284/original/063213100_1749792352-Depositphotos_247399436_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444079/original/017087300_1765770829-Depositphotos_221106062_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5414677/original/048577400_1763344579-IMG_4035-01.jpeg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3284091/original/027952300_1604288711-juan-cruz-mountford-AMFWArSckYM-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3947629/original/058073600_1645989084-xavi-cabrera-6bnH1v-IQK0-unsplash.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5330224/original/038041300_1756357544-kevin-delvecchio-7noZJ_4nhU8-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4795383/original/093104100_1712303074-3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3395224/original/007940700_1615106339-WhatsApp_Image_2021-03-07_at_8.41.57_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446825/original/096940700_1765942759-Depositphotos_216533906_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5231281/original/035535800_1748077534-WhatsApp_Image_2025-05-24_at_4.02.19_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441661/original/089526700_1765514532-penampakan_warung_kalibata_yang_dibakar.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5442683/original/005284800_1765564258-IMG_6625.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5424860/original/067292800_1764161681-banjir_bandang_malalak.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5423875/original/035710600_1764118547-WhatsApp_Image_2025-11-25_at_22.04.57__2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448056/original/043135100_1765977918-Taman_Nasional_Rawa_Aopa_Watumaohai_Konawe_Selatan.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5442670/original/096213000_1765556052-IMG_6604.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4274862/original/073458900_1672208845-food_in_refrigerator.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4764711/original/006489200_1709783406-myriam-zilles-tEJm9fvlju8-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5292579/original/070025000_1753258709-mathilde-langevin-ymEgsqhdOXw-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5242166/original/037075700_1749020420-pexels-ron-lach-8624596.jpg)