Fimela.com, Jakarta Bapak, hari ini ternyata Hari Ayah Nasional. Tapi aku hampir lupa lantaran kesibukanku di kantor dan mengurus adik-adik yang juga ternyata sudah tumbuh dewasa. Si Bungsu kini sudah membawa laptop ke mana-mana. Harus mencicil skripsi pelan-pelan katanya. Anak Bapak yang perempuan, yang dulu suka bermain petak umpet denganku saat Bapak membaca koran di ruang tamu pun baru saja diterima sebuah perusahaan besar.
Tak terasa sudah 7 tahun berlalu, sejak Bapak terbaring di rumah sakit, dengan alat-alat bantu pernapasan. Aku mendengar denyut jantung Bapak. Tapi bukan lagi di dadamu, seperti waktu aku berumur 4 tahun yang terlelap pulas dipelukanmu. Tapi di sebuah kotak asing dengan grafik naik-turun, seperti di layar lebar yang menunjukkan pergerakan saham dan nilai mata uang di tempatku bekerja.
Advertisement
BACA JUGA
Dulu aku mengatakan padamu ingin sekali menjadi dokter. Agar tak perlu tangan-tangan asing mengaduk jantung dan paru-parumu yang sudah melemah digerogoti kanker dan penyakit busuk lain. Agar aku, anak sulungmu, yang membuatmu kembali gagah. Biar aku yang memapahmu usai menjalani operasi yang panjang. Bukan orang lain.
Tapi sayang, cita-cita berubah seiring dengan pergantian zaman. Bapak tak pernah melarangku untuk mengubah cita dan mimpi. "Mimpi itu berkembang bersama pemikiran yang semakin luas dan tajam," begitu katamu usai aku dicaci guru lantaran raporku 'kebakaran.' Maaf, Pak, bukan aku yang membedah jantungmu saat itu, saat pembuluh darah di jantungmu telah merekah dan menyebabkan pendarahan hebat dalam tubuhmu.
Aku yang masih berada 11.718 km dari Jakarta, tergopoh-gopoh naik dan turun pesawat. Pulang, hanya untuk Bapak. Begitu aku turun dari taksi, lantas memasuki pintu utama rumah sakit, aku berlari sambil terus berdoa. "Tuhan tolong jangan ambil nyawanya." Tapi hanya isak tangis Mama yang tambah meledak ketika melihatku tiba di depan ruang operasi. Aku lemas. Aku takut. Aku marah. Marah pada diriku sendiri yang tak bisa mewujudkan mimpi untuk menyelamatkan Bapak.

Hidup sejak itu tak lagi berwarna. Tak ada lagi senda gurau khas yang dulu aku dengar di meja makan. Apa lagi menjelang Tahun Baru. Setiap tahun, aku memendam sesal dan sedih di hati dengan bekerja sekuat tenaga. Aku biarkan adik-adikku menggapai mimpi mereka. Aku biarkan Mama di Jakarta bersama mereka. Agar tak kesepian sepertiku yang juga kedinginan meski pakai jaket tebal berlapis pada musim dingin kali ini, di London.
Apa yang ada di London, tak aja di Jakarta. Sebaliknya, yang ada di Ibu Kota, juga tak ada di sini. Terutama kehangatan yang hanya tercipta oleh Bapak. Kehangatan itu tak sanggup dikalahkan tungku panas dan mesin penghangat mana pun di sini. London dingin, Pak. Tapi lebih dingin lagi hatiku yang dirundung rindu padamu. Melihat wajahmu di sebuah foto usang tak sanggup mengobatinya.

Maafkan aku, karena jarang pulang dan sangat sibuk di negeri orang. Bapak, Mama kirim salam. Kata Mama, sekarang toko roti yang Bapak dulu buka sudah ramai. Bahkan dekorasinya kekinian. Untung ada si Bungsu yang hobi dekorasi ruangan. Mama punya banyak karyawan sekarang. Kata Mama, toko jadi ramai bukan karena ada yang tanam modal. Tapi ternyata, kehadiran dan hangatnya cinta Bapak kepada kami yang terus mengepul, seperti roti-roti gemuk yang baru keluar dari oven.
Pak, aku tak bisa memberikan apa pun. Cita-cita aku tinggalkan begitu saja. Rumah pun aku tinggal. Bahkan Mama dan adik-adik aku tinggalkan sementara di Jakarta. Tapi satu hal, Pak. Doaku untukmu tak pernah aku tinggalkan. Lewat tiap bait doa, ada sejumput rindu, yang mudah-mudahan sampai kepada Bapak. Dan juga, di Hari Ayah ini, aku ingin memperkenalkan Siska, calon menantu Bapak. Selamat Hari Ayah, Pak. Kami di sini tak akan pernah berhenti mencintaimu.
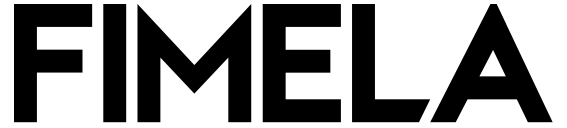
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/351016/original/021495500_1436056011-AkXoOdTcG-18WQxjC_ZSS1ipEecOqNRANZDdqe9zK4qZ__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5465029/original/070699400_1767756811-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share__1_.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441350/original/073314500_1765504657-Tanya_Jawab_tentang_Nutrisi_di_1000_Hari_Pertama_Kehidupan_Anak.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441342/original/057711100_1765504279-Novel_Tiga.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431754/original/099709900_1764747157-WhatsApp_Image_2025-12-03_at_14.16.57_a3e4af2d.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5436821/original/022017900_1765186364-pexels-anna-pou-8329902.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3286636/original/093458900_1604471471-pexels-photo-4239011.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5436788/original/050733500_1765773245-Depositphotos_812580836_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5441338/original/025527600_1765504149-Every_Day_is_A_Sunny_Day_When_I_Am_with_You.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2981728/original/010002700_1575023913-ben-white-vJz7tkHncFk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5434360/original/073007100_1764924578-pexels-vanessa-loring-5082373.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2995662/original/061514500_1576230464-juliana-malta-YwutubGmzSU-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5434439/original/085265100_1764927392-Depositphotos_835881408_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452175/original/053343100_1766388567-front-close-view-young-attractive-female-white-t-shirt-doing-make-up-with-slight-smile-pink-background.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5469801/original/027902300_1768185276-Screenshot_2026-01-12_at_09.32.26.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5022084/original/003655100_1732601966-apa-itu-oktan-bensin.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3150829/original/023474200_1591940789-brooke-lark-3A1etBW5cBk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5468218/original/070585000_1767944463-SnapInsta.to_247420157_2936691426660037_1523452434376695794_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5466866/original/095592700_1767857119-Depositphotos_123039890_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4324626/original/083226200_1676436372-priscilla-du-preez-L3lznpRPZbI-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5290798/original/058084800_1753157649-Depositphotos_724888352_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5181762/original/017749800_1744002644-Depositphotos_414070156_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5466287/original/025720300_1767841427-IMG_7934-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5417131/original/095682400_1763522186-Depositphotos_565671370_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5318556/original/073929800_1755489328-Depositphotos_706629402_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5282172/original/002632900_1752467860-Depositphotos_712660360_XL.jpg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069280/original/062057800_1735296697-asian-mother-are-quarreling-daughters-home-family-relationship-concept.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5453113/original/001165000_1766470409-WhatsApp_Image_2025-12-23_at_12.19.35__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5335102/original/017863700_1756786957-little-desperate-girl-looking-panic-holding-her-head-with-both-hands.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5271472/original/044739400_1751512018-front-view-two-sisters-playing-home-with-toys.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5468300/original/009638000_1767946480-Depositphotos_485939088_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5412723/original/076594300_1763102766-IMG-20251114-WA0008.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452876/original/099231900_1766461807-FIMELA_FASHION_-_Lanvin_at_Its_Most_Glam__IG_Feed__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470654/original/001785900_1768213679-Tiga_tersangka_pengiriman_sabu_yang_dibongkar_polisi_di_Pelabuhan_Bakauheni.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470650/original/054391100_1768213199-Screen_Shot_2026-01-12_at_17.17.28.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4691704/original/038668600_1702980308-Bawaslu_tangani_pelanggaran_kampanye-FANANI_12.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5467311/original/035350200_1767870813-Screenshot_2026-01-08_174617.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4938922/original/005732500_1725702494-Screenshot_20240907_142113_WhatsApp.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470508/original/073891900_1768208322-Tangkapan_layar_video_viral_warga_geruduk_penginapan_di_Bandar_Lampung.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5468124/original/051005700_1767942064-Depositphotos_636857656_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5470555/original/094778700_1768210298-asasa.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5468179/original/020237100_1767942883-Depositphotos_708163156_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5230324/original/062328200_1747988979-f.jpg)