Fimela.com, Jakarta Normal, satu kata sederhana dengan makna yang tak sesederhana itu. Aksara familiar tersebut nyatanya sangat mungkin berdampak jauh lebih dalam dari yang pernah saya dan kamu imajikan. Meski tak pernah ada deklarasi indikator secara gamblang, namun penduduk Bumi nampaknya telah memahami hukum tak tertulis akan normal.
Seperti kebanyakan perihal, situasi yang bisa dikatakan saklek dan tentatif di waktu bersamaan ini pun enggan absen dari ritme kehidupan. Jika saya boleh menyederhanakan, berbeda secara pemikiran mainstream bisa jadi antonim dari normal. Sehingga, berbagai hal di luar pakem umum bisa dikategorikan dalam ketidaknormalan, termasuk nomaden.
Advertisement
Entah globalisasi, modernisasi, atau hal lain yang bisa dijadikan kambing hitam, cara hidup demikian sungguh tak akrab dengan saya dan miliaran masyarakat dunia. Konsep hidup berpindah dengan rute yang, sebagaimana diterapkan sejumlah suku di Himalaya, konstan sepertinya jauh dari nalar.
Punya 'rumah' tak bergerak tentu jadi salah satu tolak ukur hidup layak bagi saya yang dibesarkan dengan cara berpikir general. Namun setelah (dengan tekun) membaca lembahan buku lusuh koleksi tua papa, saya kembali berpikir ulang akan konsep normal dan layak tersebut.
Selepas belasan halaman, saya baru menyadari kalau normal ternyata sangat tentatif, teramat bergantung pada siapa yang berpikir dan menyimpulkannya. Bagi kaum nomad yang sekarang dominan terlihat di jalur-jalur terjal nan menawan nun jauh di atap dunia sana, kotak-kotak kota mungkin malah jadi cara hidup 'alien'. Siapa sangka, bukan?
Kali ini, saya akan coba membawamu berpikir akan hidup dari persepsi bangsa Nomaden. Jauh dari 'buku panduan' yang secara tak sadar banyak dibaca, diikuti dan dibudayakan lebih dari setengah penduduk dunia. Tentang bagaimana memaknai hidup dan bagaimana cara menjalaninya.
What's On Fimela
powered by
Advertisement
Nomaden adalah bentuk perlawanan akan hukum modernisasi?
Sebelum berbicara lebih jauh, izinkan saya menjabarkan sedikit pengetahuan teoritis tentang bangsa Nomad. Menurut beberapa buku, kaum ini sebenarnya berasal dari berbagai komunitas masyarakat, di mana mereka lebih memilih hidup berpindah dibandingkan menetap di suatu tempat.
Terkait asal, jawabannya masih simpang siur. Pasalnya, bangsa Nomad bisa diklasifikasikan lagi ke beberapa masyarakat, termasuk gypsy dan hippie. Kemunculannya berpusat di beberapa kawasan, yakni Amerika, Eropa dan Asia Selatan. Yang jelas, cara hidup berpindah ini mulai didapati sejak tahun 1960.
Dengan pemilihan demikian, mereka membuat saya berpikir apa sebenarnya yang dibutuhkan dalam hidup. Rumah tetap? Pekerjaan layak? Atau sekelumit kebutuhan lain yang dikesankan mendesak? Tanpa menyita waktu lama, kamu pun sepertinya telah bisa menjawab pertanyaan tersebut meski dengan bertapi-tapi.
Saya pernah membaca salah satu feature yang dimuat BBC tentang bangsa Nomad di kungkungan megah Himalaya. Bagaimana mereka menjalani keseharian tanpa pusing berpikir hari ini rupiah melemah atau sebaliknya, juga tak repot mengkhawatirkan kredit mobil yang masih akan rampung dalam belasan bulan mendatang.
Bukan berarti saya bilang hidup mereka hanya melulu soal bahagia, tentram, aman dan sejahtera. Namun yang ditekankan, yakni refleksi kesederhanaan dalam tindak-tanduk keseharian. Daripada repot mengkritisi soal Britania Raya yang keluar dari Uni Eropa, saya pikir mereka akan lebih khawatir jika ternaknya hilang dalam jumlah selusin (suku Nomaden biasanya berpindah sesuai dengan kebutuhan ternak mereka).
Hidup di alam dengan pakaian sederhana yang dimaksudkan sebagai pelindung diri, baik dari terik matahari maupun terpaan angin dingin 'menggigit', bukan untuk unjuk diri masih jadi konsep lugas yang saya kagumi. Jangan harap mereka repot membuat strata sosial. Semua sama, berada di 'garis' horizontal yang itu-itu juga.
Dengan 'jurang' yang membentang di antara keduanya, saya sepertinya kurang setuju jika Nomaden dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum modern. Pasalnya, keputusan untuk tak punya rumah konstan bisa dilatarbelakangi banyak faktor.
Bisa saja, beberapa dari mereka hanya penghuni negeri stan yang menolak dirumahkan Soviet, bukan 'orang modern' yang sekonyong-konyong meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menjadi bangsa Nomaden. Mungkin juga bagi mereka, Nomaden adalah zona aman.
Tanpa mengintimidasi pihak manapun, saya pikir setiap orang bisa memetik satu-dua makna hidup, baik dari kategori 'normal' atau tidak. Lantaran, bagi saya, semua perihal di Bumi ini hanya tinggal bagaimana menentukan sudut pemahaman hingga akhirnya berkonklusi, termasuk soal bangsa Nomaden. Karena, tak ada mayoritas jika minoritas ambyar, bukan?
Asnida Riani
Editor Kanal Style Bintang.com
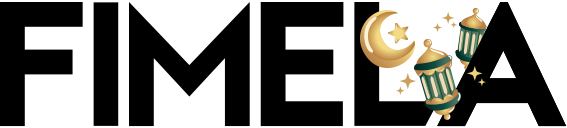
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/342404/original/077297200_1734360117-IMG_3333.jpeg)
![[Bintang] Himalaya](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/IVT1EJ6GDrD6UVR8F5jnVe1lHyw=/680x383/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1241646/original/055835200_1463979458-1.jpg)


![[Bintang] Himalaya](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/IRdQFF1AMOTV84Mppk9QNTnEvZ0=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1241866/original/090577400_1463986261-14.jpg)


:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5167274/original/091207900_1742351630-assortment-delicious-fresh-cookies_114579-13166.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5166770/original/053276900_1742284290-aldo_s25_ramadan_group_00161_OPT2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5166112/original/055638700_1742223474-Foto_1_-_Havaianas__RayakanSejenak_Iftar_Event.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5153058/original/040426000_1741321009-WhatsApp_Image_2025-03-07_at_11.13.20_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5154409/original/003534200_1741355838-WhatsApp_Image_2025-03-07_at_8.51.02_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3476898/original/008373900_1623203809-gracia-dharma-qTlbO6mkQH0-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069010/original/025185800_1735287306-pexels-polina-tankilevitch-4518581.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5064546/original/065004900_1735022946-pexels-cottonbro-6970101.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5064532/original/051604600_1735022585-pexels-cottonbro-5990491.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4993686/original/004273900_1730894148-Screenshot_2024-11-06_183841.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5044050/original/083856400_1733829025-pexels-fotios-photos-1161682.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041610/original/060088700_1733732335-pexels-august-de-richelieu-4259707.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033038/original/000687200_1733198738-Snapinsta.app_468983269_422604517585625_3930891875784389755_n_1080.jpg)
![Seniman Galuh Anindita menciptakan aksesori yang diberi nama Mahija. [dok. Galuh Anindita]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WTXk5rkAsLcLcYIG39cRqwfZn1A=/0x1157:2624x2636/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035276/original/041670100_1733312960-FOTO_PROFIL_SENIMAN_-_GALUH_ANINDITA_WARDANA.JPG)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
![Perhiasan: Tiffany & Co. // Makeup: Laura Mercier // Hair: Shisheido Professional // Model: Mariyye from Studio47. [Foto: Adrian Putra/ Fimela.dok]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/YlBu6kBOJ7tfWEp3e6HTC8hU12g=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5143202/original/016928600_1740493988-0E6A2838-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5140051/original/040275900_1740135842-FIMELA_FASHION_-_GLEAMING_LOVE_STORY_WITH_TIFFANY___Co.__YT_Post.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069846/original/010151000_1735373948-FIMELA_FASHION_-_Luxury_in_Every_Stitch_with_MCM__IG_feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058958/original/065333600_1734685101-IMG_4392.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034833/original/043480800_1733296555-FIMELA_FASHION_-_BOUNDLESS_BEAUTY_WITH_WEEKEND_MAXMARA__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033477/original/089964900_1733210907-IMG_8172__1_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5100402/original/061791700_1737270367-Screenshot_2025-01-19_140113.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5047996/original/090208000_1734008292-Screenshot_2024-12-12_194204.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069375/original/004035600_1735304402-Screenshot_2024-12-27_194050.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041897/original/065093700_1733746217-Screenshot_2024-12-09_184000.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041772/original/009683400_1733738762-Screenshot_2024-12-09_143018.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5024811/original/023675700_1732629208-Screenshot_2024-11-26_194022.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5160238/original/055875400_1741778325-two-young-pretty-girls-looking-dresses-try-it-while-choosing-shop_155003-9328.jpg)
![Desainer Harry Halim gelar pertunjukkan busana untuk Winter 2025 bertajuk Finality pada Jumat (21/3). Pertunjukkan busana ini diramaikan oleh Cinta Laura, Adinia Wirasti hingga Chicco Jerikho yang tampil dengan busana bernuansa dark nan dramatis [@claurakiehl @snap.nuel]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/f-u5D8jwGdZJ1pkzIlh-AUfcJ2Q=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5171502/original/062183500_1742641573-photo-grid__37_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5171494/original/062445100_1742641122-Inara_Rusli.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5071624/original/012080600_1735540374-1735029041132_resep-kue-putu-ayu-kukus.jpg)