Intan Paramaditha, Macquarie University
Artikel ini adalah yang kedua dalam seri tulisan memperingati Hari Aksara Internasional yang jatuh pada tanggal 8 September.
Advertisement
Dalam berbagai forum tak jarang kita temukan pertanyaan: Buku fiksi Indonesia mana yang perlu dibaca?
Sering kali, jawaban atas pertanyaan itu terbatas pada apa yang beredar di toko buku besar. Sebagian buku tak disebut lagi karena sulit dicari dan tidak menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Realitas ini, ditambah keinginan memperbincangkan buku-buku favorit, mendorong saya untuk mengumpulkan delapan buku fiksi wajib baca sebelum usia 30.
Daftar yang saya buat bersifat subjektif dan strukturnya disusun berdasarkan tema dan kecenderungan tertentu. Kedelapan buku ini, secara umum, menawarkan jawaban beragam atas pertanyaan besar: bagaimana membayangkan, memaknai, dan mereka ulang Indonesia?
Baca juga: Sembilan nonfiksi Indonesia yang wajib Anda baca sebelum usia 40
Empat karya pertama dalam daftar memantulkan pertanyaan yang lebih spesifik: bagaimana membayangkan Indonesia dan dunia dalam perjalanan? Ini adalah bagian dari upaya untuk, satu, melampaui dikotomi lokal-asing; dua, menelusuri jejak kosmopolitanisme di luar tema menggapai cita-cita dan cinta hingga ke New York/Paris/Kairo (silakan isi sendiri), yang lazim kita temukan dalam novel maupun film populer masa kini.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485778/original/095679200_1543328884-file-20170828-1533-1rnayio.jpg)
Saya juga memasukkan karya-karya penulis perempuan yang mempertanyakan norma, budaya, dan keindonesiaan melalui sudut pandang feminis. Selain itu, sebagai alternatif dari tema-tema optimis semanis gulali yang dominan dalam industri perbukuan, saya juga memilih karya-karya yang menghadirkan wajah Indonesia secara gelap dan distopis (kebalikan utopis).
Daftar ini sama sekali tidak komprehensif. Saya tidak menyebut banyak buku yang biasanya masuk kurikulum sekolah, seperti buku-buku angkatan Balai Pustaka maupun yang terbit beberapa dekade sesudahnya.
Buku Robohnya Surau Kami yang kita baca di SMA, misalnya, tentu masih sangat relevan untuk Indonesia hari ini, ketika kesalehan terus-menerus dipertunjukkan di ruang publik. Dan meski gagasan modernitas dalam Layar Terkembang bisa diperdebatkan, buku ini menghadirkan tokoh perempuan intelektual berkesadaran politis di luar model ibuisme Orde Baru maupun model istri taat suami berbungkus jargon agama.
Daftar yang saya buat juga tidak mencakup buku-buku yang sudah mencapai status “kultus” maupun mendunia, seperti tetralogi Pramoedya Ananta Toer, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, maupun Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Buku-buku yang demikian penting ini, saya yakin, sudah dibaca banyak orang sebelum usia mereka genap dua puluh.
‘Orang-Orang Bloomington’, Budi Darma (1980)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485779/original/082746600_1543328886-file-20170828-1601-83gj.jpg)
Orang-orang Bloomington (OOB), buku favorit saya sepanjang masa, menyodorkan perspektif kosmopolitan yang unik. Indonesia tak hadir di sini. Berlatar kota Bloomington, daerah pelajar yang tidak hingar bingar seperti New York, buku ini menghadirkan sekumpulan manusia usil-obsesif yang tak kalah ajaib dengan tokoh-tokoh film David Lynch.
Terkadang kita tak tahu pasti latar budaya narator yang sedang bercerita. Apakah ia pelajar Indonesia di Bloomington seperti Budi Darma? Apakah ia orang Amerika berkulit putih? Yang jelas para tokoh OOB menyiasati ruang sosial mereka dengan menjadi voyeur (pengintip) dan melakukan kejahatan-kejahatan kecil agar tak kesepian.
Menghadirkan keterasingan secara dingin dan sadis ketimbang larut dalam kerinduan romantik atas rumah, buku ini membuat kita berpikir tentang keterhubungan dunia dan tempat kita di dalamnya. Melalui OOB, kita memasuki dunia seorang pengarang yang menerjemahkan gagasan “warga dunia” dengan caranya sendiri.
‘Seribu Kunang-Kunang di Manhattan’, Umar Kayam (1972)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485780/original/066847700_1543328888-file-20170828-1549-13wn176.jpg)
Beberapa cerpen Umar Kayam berlatar New York dalam Seribu Kunang-Kunang di Manhattan menggambarkan upaya tokoh-tokoh asal Indonesia dalam memahami dan menghubungkan diri dengan lingkungannya. Upaya ini sering kali terasa gagap, sebelum akhirnya gagal.
Salah satu cerpen berkisah tentang istri pelajar yang kesepian dan berusaha berteman dengan perempuan eksentrik bernama “Madame Schlitz”. “Madame Schlitz” sendiri adalah sebuah fiksi; ia kemudian lenyap ditelan kota.
New York kerap digambarkan cantik, dingin, tetapi juga keji (“raksasa pemakan manusia”, meminjam istilah salah satu narator). Sebaliknya, Indonesia dari kejauhan terkadang jadi kelewat romantik, seperti tokoh Marno yang tinggal bersama perempuan Manhattan namun dihantui oleh suara jangkrik dan ratusan kunang-kunang di desanya.
Dalam karya Umar Kayam kita melihat tatapan takjub, heran, sekaligus berjarak atas yang Liyan. Buku ini menawarkan potret keterhubungan yang penuh tegangan, nostalgis, dan mungkin problematis, tapi jelas ia bukan gambar kartu pos.
‘Student Hidjo’, Mas Marco Kartodikromo (1918)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485781/original/051530900_1543328890-file-20170828-1590-1prfo46.jpg)
Sebuah potret lain tentang Indonesia dalam perjalanan, Student Hidjo adalah Mas Boy dengan kecenderungan hipster versi peralihan abad 20.
Hidjo dikirim oleh ayahnya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Teknik di Delft supaya tak kalah gengsi dengan rekan-rekan sesama pejabat di Jawa. Dalam Student Hidjo, kita lihat gagasan nasionalisme hadir bersama-sama (kadang terkait, kadang berbenturan) dengan kosmopolitanisme lewat tokoh-tokoh yang—sebagaimana Mas Marco—dandy dan mementingkan fesyen. Melalui tokoh-tokoh yang sepertinya punya banyak waktu untuk pelesir dan minum limun, buku ini memantulkan gambaran modernitas Indonesia masa kolonial dalam Engineers of Happy Land (Rudolf Mrázek, 2002).
Student Hidjo bukan tanpa masalah sebab representasi perempuan Belanda di dalamnya sungguh membuat kening saya berkerut. Tetapi ia “menghibur” dengan cara yang aneh, berakhir bahagia namun penuh tanda-tanya, dan dengan cerdas menangkap kontradiksi zamannya.
‘Pada Sebuah Kapal’, Nh. Dini (1973)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485782/original/040880700_1543328892-file-20170828-12314-1hs996g.jpg)
Nh. Dini kerap dimasukkan ke dalam kotak “penulis perempuan”, sebuah kategori yang terkadang juga membatasi beragam tema yang diolah penulis-penulis kontemporer seperti Ayu Utami, Leila S. Chudori, Nukila Amal, atau Linda Christanty (dan ya, saya anjurkan Anda membaca karya-karya mereka).
Di tahun 1970 dan 1980-an, penulis perempuan bahkan dianggap “hanya” mengolah tema asmara dan pernikahan ketimbang hal-hal yang lebih penting seperti persoalan sosial politik. Oposisi biner dunia perempuan/laki-laki, domestik/publik, maupun hubungan personal/politik justru luruh bila kita menyelami karya-karya Nh Dini.
Melalui sudut pandang tokoh perempuan yang hidup di luar negeri sebagai kekasih atau istri seseorang, Pada Sebuah Kapal dan buku-buku Nh. Dini lainnya mengajak kita berpikir ulang tentang konsep bangsa dan nasionalisme.
Salah satu tokoh Nh. Dini secara tegas mengklaim dirinya sebagai “citizen of the world” dan menghadapkan kita pada pertanyaan tentang posisi etis dan politik sebagai warga negara sekaligus warga dunia. Bila sempat, baca pula Keberangkatan yang berkisah tentang pengalaman seorang perempuan Indo, subjek yang membayangkan Indonesia dalam posisi “di antara”.
‘Raumanen’, Marianne Katoppo (1977)
Raumanen, ditulis oleh teolog feminis Marianne Katoppo, saya masukkan di sini sebagai ajakan membaca melawan arus. Kita perlu memberi makna lebih dalam atas karya-karya perempuan di masa sastra Indonesia, didominasi oleh penulis/kritikus laki-laki, cenderung menyingkirkan tulisan perempuan ke wilayah “kurang serius”.
Sebagian pembaca sastra mungkin menganggap Raumanen “sekadar” melodrama (tapi mengamini Linda Williams, pengertian melodrama tak terbatas pada genre melainkan moda yang bisa dipakai di mana-mana; artinya, karya-karya kanon pun bisa mengolah elemen melodrama).
Raumanen tidak hanya mengangkat kisah percintaan tragis namun mengajukan pertanyaan tentang “Indonesia” yang dibayangkan utuh, hubungan antara agama dan patriarki, dan rapuhnya posisi perempuan muda. Dibandingkan pacar yang menghamilinya, tokoh Raumanen sebagai seorang perempuan harus berhadapan dengan norma yang lebih represif dan sistem sosial yang jauh lebih tidak memihak. Akan menarik pula bila kita hubungkan jejak Marianne Katoppo di sini dengan karyanya dua tahun kemudian, Compassionate and Free (1979), sebuah buku teologi feminis Asia pertama yang terbit dalam bahasa Inggris.
‘Calon Arang: Kisah Perempuan Korban Patriarki’, Toeti Heraty (2000)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485784/original/015092800_1543328896-file-20170828-1549-1yik4ne.jpg)
Meski sebagian besar buku dalam daftar ini adalah novel atau kumpulan cerpen, saya menggunakan kata “fiksi” secara longgar dan memasukkan sebuah prosa liris penting karya penyair/aktivis/akademisi feminis Toeti Heraty.
Calon Arang: Kisah Perempuan Korban Patriarki adalah salah satu karya yang menyodorkan pembacaan ulang atas legenda si tukang sihir dari Bali (lihat Goenawan Mohamad, Sardono W. Kusumo, Pramoedya Ananta Toer, Cok Sawitri, Ayu Utami), dan bisa dibilang yang paling awal mengajukan interpretasi feminis.
Calon Arang di sini tetap mengerikan (“mempersembahkan mayat-mayat dalam kepingan”), namun telaah kritis atas patriarki yang dilakukan Toeti Heraty menghadirkan kompleksitas posisi Sang Rangda dari Dirah. Buku ini menggambarkan kelindan antara gender, seksualitas, dan politik. Calon Arang, perempuan berilmu dan berkuasa, mesti musnah sebab ia mengancam otoritas raja dan pemuka agama.
‘Malam Jahanam’, Motinggo Boesje (1961)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485785/original/007192200_1543328898-file-20170828-1557-n6i4qi.jpg)
Saya tumbuh sebagai pembaca naskah drama, dari Shakespeare hingga Tennessee Williams, dan inilah salah satu naskah yang saya anggap paling menghantui.
Seperti sederetan buku, film, dan drama yang menjadi inspirasi kepengarangan saya, Malam Jahanam menampilkan kekejian yang membunuh perlahan.
Isu seksualitas, kelas, dan moral muncul secara rumit, kelabu, jauh dari suara didaktis dan moralis. Pemenang sayembara penulisan drama tahun 1958, Malam Jahanam menggambarkan kampung sebagai dunia yang gelap, realitas Indonesia yang sakit, jauh dari sederhana maupun mengharu-biru.
Dalam lakon ini juga kita dapati gagasan maskulinitas yang retak atau hancur berantakan, tema yang mengemuka dalam banyak karya-karya pasca kemerdekaan, termasuk buku Jalan Tak Ada Ujung (Mochtar Lubis) atau film Lewat Djam Malam (skenario Asrul Sani, sutradara Usmar Ismail).
‘Babi Ngepet’, Abdullah Harahap (1980?)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485786/original/097827500_1543328899-file-20170828-1572-9xnw7v.jpg)
Dalam hidupnya, seseorang harus membaca satu-dua karya Abdullah Harahap, penulis horor populer tahun 1970-1980an. Ratusan buku Abdullah Harahap (ia sendiri tidak ingat berapa tepatnya) sering kali terbit tanpa ISBN dan dianggap “picisan”. Lalu mengapa Abdullah Harahap?
Saya, Eka Kurniawan, dan Ugoran Prasad telah menulis cukup panjang tentang itu dalam pengantar Kumpulan Budak Setan, kumpulan cerita horor yang kami dedikasikan untuk beliau. Singkat kata, kami menemukan ruang-ruang subversif dalam cerita horor Abdullah Harahap yang, secara permukaan, dipenuhi tema dan imaji horor konvensional: arwah penasaran, rahasia gelap, dendam kesumat.
Tokoh utama dalam Babi Ngepet, misalnya, adalah seorang lelaki yang terperangkap dalam kelas sosialnya dan tak bisa keluar. Horor Abdullah Harahap adalah potret Indonesia yang buram; ketika negara, lembaga hukum, dan tatanan sosial tak bisa menjanjikan keadilan, orang tak punya cara selain bersekutu dengan setan.
Intan Paramaditha, Lecturer in Media and Film Studies, Macquarie University
Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.
(vem/kee)
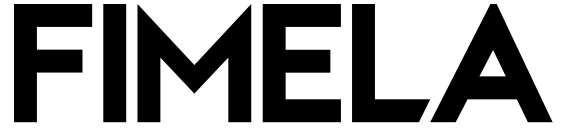

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2485777/original/024820900_1543328883-107508-ladies-ini-8-buku-fiksi-indonesia-yang-wajib-kamu-baca-sebelum-usia-30-104809.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2485783/original/029236500_1543328894-file-20170828-1557-1gcunx7.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995209/original/026181100_1730986853-Screenshot_2024-11-07_202711.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4988253/original/058148800_1730511774-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4992558/original/055117100_1730862025-fried-chicken-tendon-serve-with-sauce.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010215/original/9200_1731903886-DALL__E_2024-11-18_11.21.28_-_A_realistic_close-up_of_fresh_green_stink_beans__Parkia_speciosa___also_known_as_petai__displayed_in_an_artistic_arrangement._The_beans_are_shown_both.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011349/original/068997400_1731980815-pexels-xmtnguyen-2664221.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5005449/original/029986600_1731580532-pexels-laarkstudio-13499754.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994694/original/3500_1730956721-DALL__E_2024-11-07_12.10.22_-_A_pile_of_fresh_green_beans_on_a_clean_white_background._The_beans_are_bright_green__crisp__and_arranged_in_a_natural_pile._Some_beans_have_slight_wat.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3416426/original/041409700_1617192182-pexels-alex-green-5693041.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956033/original/000450000_1727615395-SGV8394.JPG)
![Salsabila Karsawinata Founder dan Coach Salsalivefit. [@salsavinandita]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/8-c19f1z2YmQAK91n6NRg19yEXI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4953767/original/026021300_1727338436-image_123650291_2053_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994919/original/098462400_1730968814-FIMELA_FASHION_-_THE_WAY_SHE_WEARS_IT_WITH_LOEWE__IG_FEED.jpg)
![Lihat di sini tampilan glamor Marshada dengan gaya old hollywood di pemotretan terbaru. [@riomotret].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/7QoC1hvf6nBlU-3iwI2dd6kmDhg=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4966556/original/068171700_1728642180-Snapinsta.app_462598825_18464089717030499_6711654336387563985_n_1080__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4948469/original/092414300_1726801989-IMG_8194_re__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4948776/original/028552100_1726815806-FIMELA_FASHION_-_BUILT_TO_WIN_WITH_ALO__IG_Feed.jpg)
![Tampilan memesona Beby Tsabina yang dampingi suami bertugas saat HUT ke-79 RI. Ia mengenakan kebaya putih yang dipadukannya dengan amat apik mengenakan selendang merah. [Foto: Instagram/bebytsabina]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/NCQb0vCZyujjIY8HUpn0Nfi8RmI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4922980/original/072102300_1724131209-6_Gaya_Artis_Pakai_Kebaya_Putih_saat_Rayakan_HUT_ke-79_RI__Beby_Tsabina__Tissa_Biani__hingga_Prilly_Latuconsina__3_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4972696/original/046879900_1729252895-Screenshot_2024-10-18_185512.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4987926/original/062198100_1730466297-Screenshot_2024-10-17_183258.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015441/original/084438300_1732162387-GridArt_20240605_212126929.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015419/original/039963000_1732161840-0E6A0321_edited.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015380/original/001956000_1732160589-IMG_8265.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4979365/original/016637300_1729822402-young-beautiful-business-woman-working-computer-cafe__2_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5000452/original/001908600_1731307337-IMG-20241111-WA0038.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016026/original/070233000_1732179549-Snapinsta.app_449071619_1531874414425922_2230883605529953947_n_1080.jpg)
![Syifa Hadju dan Cut Syifa di Ajang Penghargaan SCTV Award 2024. [Instagram]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/HL-7nG925_ocuvhhIdVHHwB46TY=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015561/original/093672500_1732166211-IMG_2416.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016044/original/020390900_1732180041-Inspirasi_Kebaya_Wisuda_Margin_Wieheerm.jpg)