Advertisement
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2167887/original/018687800_1525678510-152567850963741buku-1.jpg) Gitanyali, sang tokoh utama, digambarkan sebagai sosok yang cinta kebebasan. Sebagai bagian dari produk sejarah yang kelam, dicap sebagai keturunan PKI yang konon terpinggirkan, Gitanyali bahkan terkesan tak ingin berlarut dalam label politik itu. Ketika kedua orangtuanya “dijemput” serombongan orang yang membawa senapan tahun 1965, misalnya, dia memilih tetap fokus belajar, seperti pesan orangtuanya ketimbang memikirkan capnya sebagai anak PKI. Walaupun terkesan cuek, label PKI mau tak mau juga tetap mempengaruhi mentalnya. Buktinya Gitanyali bersyukur ketika akhirnya bisa keluar dari kampung halamannya, kaki Gunung Merbabu. Dengan begitu label politiknya itu bisa dia lepaskan.
Gitanyali, sang tokoh utama, digambarkan sebagai sosok yang cinta kebebasan. Sebagai bagian dari produk sejarah yang kelam, dicap sebagai keturunan PKI yang konon terpinggirkan, Gitanyali bahkan terkesan tak ingin berlarut dalam label politik itu. Ketika kedua orangtuanya “dijemput” serombongan orang yang membawa senapan tahun 1965, misalnya, dia memilih tetap fokus belajar, seperti pesan orangtuanya ketimbang memikirkan capnya sebagai anak PKI. Walaupun terkesan cuek, label PKI mau tak mau juga tetap mempengaruhi mentalnya. Buktinya Gitanyali bersyukur ketika akhirnya bisa keluar dari kampung halamannya, kaki Gunung Merbabu. Dengan begitu label politiknya itu bisa dia lepaskan.
Jakarta, tempat hijrahnya pertama kali, dianggapnya sebagai tempat pembebasan. Di sanalah Gitanyali menjalani hari-harinya sebagai anak muda normal yang ikut larut dalam zamannya. Latar PKI dipakai sekaligus dilepaskan, menunjukkan bahwa keturunan PKI tak selalu terpinggirkan seperti yang selama ini kita tahu, dan bahwa tak selalu produk sejarah itu mempengaruhi hidup seseorang. Kalaupun mempengaruhi hidup Gitanyali, setidaknya tak membuatnya tersingkir dan merana, meratapi nasib jadi anak PKI.
Kecerdasan bawaan sejak lahir yang ia punya membuatnya selalu beruntung. Sejak kecil Gitanyali sudah dikenal paling pandai di kelas. Sifat ingin tahunya yang sangat besar juga membuat Gitanyali makin menonjol dibandingkan teman sebayanya. Saat yang lain sibuk bermain, dia sudah membaca buku apa saja, terutama soal musik dan film, lalu mulai menulis di majalah dan mengumbar sajak-sajak gombalan untuk teman SMP yang ditaksir sahabatnya, juga menulis rayuan-rayuan untuk runner up Ratu Kecantikan lewat radio. Ketika dewasa, dalam 65 juga diceritakan sederet keberuntungan yang memihaknya, dalam hal karier maupun perempuan.
Advertisement
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2167889/original/056460100_1525678510-152567851081644buku-2.jpg)
Gitanyali ternyata juga memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam hal seks. Dia bahkan sudah merasakan orgasme saat masih kecil, ketika tidur bersebelahan dengan Mbak Kadar, yang usianya jauh di atasnya. Di situlah petualangan seksnya dimulai. Beberapa kali juga dia pun menyukai perempuan yang jauh lebih tua dan berfantasi tidur dengan mereka satu persatu—saat dewasa beberapa di antaranya akhirnya benar-benar berhasil dia tiduri.
Dalam 65 nama-nama perempuan masa lalunya tak diceritakan lagi, kecuali Nita, sepintas, dan Rosa, yang dalam Blues Merbabu kisah percintaannya dengan Gitanyali belum sempat dimulai. Sementara itu, perempuan baru yang diangkat Gitanyali dalam 65, antara lain Hilda yang janda beranak satu dan dijodohkan dengan laki-laki tua asal Belanda, Christine si gadis oriental yang menggemaskan, dan tentu saja Emma Tan, perempuan oriental keturunan garut dan Hang Zhou, pemilik galeri Emmaretta Contemporary di Bangkok.
Gitanyali menggunakan cara pandang anak-anak dan remaja ketika bercerita dalam Blues Merbabu, kemudian dalam 65 barulah dia bercerita dengan cara pandangnya yang sudah jauh lebih dewasa. Tapi, satu hal yang tak berubah, Gitanyali tetap membawa masa lalunya di tahun ‘65, bukan lagi dalam bentuk sejarah muram, melainkan lewat kisah percintaannya dengan Emma Tan, yang kebetulan banyak berkaitan dengan angka 65. Angka sakral bagi Gitanyali.
Berkebalikan dengan kisah 65-nya yang kelam, 65 yang ditemuinya setelah bersama Emma membawa cinta dan harapan baru. Ia memilih Emma, perempuan yang jarang ia ceritakan kelebihannya, berbeda dengan Mbak Kadar yang punya senyum manis, Li Hwa yang juga manis, Mbak Tutik yang kalem dan penuh pengertian, Khotifa yang makin cantik dengan potongan rambut sebahu, atau Adila yang ia serahi keperjakaannya saat SMP. Bukan tanpa alasan, Gitanyali memang telah beranjak dari masa lalunya. Bukan untuk melupakan sejarah—buktinya sesekali dia masih teringat Rosa—Gitanyali hanya melangkah maju ke dunia baru yang tanpa labelisasi. Gitanyali sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
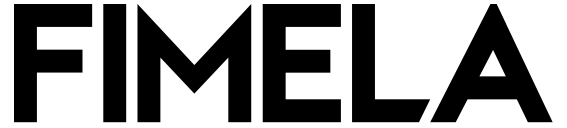

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446056/original/088244600_1765871776-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446721/original/005950600_1765939085-IMG-20251217-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5411995/original/098546600_1763028037-IMG_3023-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437620/original/023028500_1765258087-Depositphotos_804339058_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444636/original/037285600_1765784303-Desain_tanpa_judul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5437822/original/092774500_1765264784-Depositphotos_618867182_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430234/original/024751500_1764656701-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5430246/original/078844100_1764656929-WhatsApp_Image_2025-12-02_at_13.22.55.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421696/original/066687600_1763957022-pexels-polina-tankilevitch-5468719.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5421809/original/040895800_1763960008-pexels-emil-kalibradov-3013808-7085779.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3304346/original/025770100_1606121870-shutterstock_1819946462.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5160772/original/017170300_1741840102-Rambut_halus.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4994359/original/026697200_1730937396-Depositphotos_513926280_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448250/original/093199600_1766024444-Screen_Shot_2025-12-18_at_09.16.02.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449052/original/021526200_1766046562-1280x847_px.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448482/original/048290000_1766030421-Foto_bersama_tamu_undangan_acara_peresmian.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446804/original/060156400_1765942120-pexels-daan-stevens-66128-939331.jpg)
![Lebih dari sekadar operasional internal, AYANA Bali juga melibatkan tamu dan komunitas dalam praktik berkelanjutan. Melalui AYANA Farm, area organik seluas dua hektare yang menanam lebih dari 130 varietas tanaman, tamu diajak mengenal pertanian organik dan prinsip sirkular secara langsung. [Dok/AYANA BALI].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/wSxxi2Nh7Q1NJLtzjPIoJgHgF70=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5445903/original/006242400_1765867564-AYANA_Farm_Farm_Walk_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3562465/original/037038200_1630905705-jeshoots-com-fp1x-X7DwDs-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444779/original/096627700_1765788691-Depositphotos_305463478_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5299574/original/048097200_1753844577-Depositphotos_735660458_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444831/original/095331300_1765790013-Depositphotos_507090168_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5251284/original/063213100_1749792352-Depositphotos_247399436_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5444079/original/017087300_1765770829-Depositphotos_221106062_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5414677/original/048577400_1763344579-IMG_4035-01.jpeg)
![Buat kamu yang sering males bawa tas, this might be your new everyday essential. [@ninjalabsx].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/JmPHj_AUqE0OF1amNJyGoeHJEqw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5431872/original/017250000_1764749869-SnapInsta.to_464376048_18021797717608173_6667940723387353151_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5428609/original/023315200_1764553676-MIUCCIA_PRADA_HONORED_WITH_THE_LIFETIME_ACHIEVEMENT_AWARD_AT_THE_FASHION_TRUST_ARABIA_AWARDS_CEREMONY_2025__1_.jpg)
![Jennie BLACKPINK Berkolaborasi dengan Haribo. [@jennierubyjane]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/aV4GRPgoYJp6CPnLCXQZBu2qm5o=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426470/original/076048800_1764306557-IMG_1424_2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426531/original/055682400_1764308639-Screenshot_2025-11-28_123440.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426229/original/035642400_1764297400-tong-su-1xx1hq2RJts-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426004/original/019931600_1764246120-Nov_27__2025__07_20_48_PM.png)
![Wulan Guritno dan ketiga anaknya yang kini sudah dewasa dan remaja. [@wulanguritno]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/75gwbMDLH3tDnqW4z5XTWSBCJQE=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449166/original/044337100_1766049610-IMG_2577.jpeg)
![Tak hanya memberi jawaban, peran ayah juga menjadi teladan nyata tentang bagaimana seorang laki-laki bersikap. Dok/freepik.com/jcomp]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/bsuiPOPdpuLCbduV2yU_-d3PNkY=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5366198/original/086964900_1759220188-father-son-playing-park-sunset-time-people-having-fun-field-concept-friendly-family-summer-vacation-father-son-legs-walk-across-lawn-park.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448717/original/070007700_1766038449-Depositphotos_609334680_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3500830/original/034542100_1625446520-jimmy-dean-Qngdf0kgGB4-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5278182/original/094954900_1752056858-jessica-rockowitz-5NLCaz2wJXE-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2932381/original/055716500_1570429987-adorable-baby-boy-1374509.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3353795/original/056458100_1611093586-beautiful-elegance-luxury-fashion-pink-women-handbag_1203-7653.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5416947/original/076643700_1763480454-IMG_4832.jpg)
![Tasya Farasya memilih gaun rancangan Sapto Djojokartiko berwarna nude lembut yang memancarkan aura elegan dan feminin. Detail renda dan bordir bunga yang menjalar di seluruh permukaan dress memberi kesan etereal, seolah Tasya melangkah dengan sentuhan magis di setiap langkahnya. [@tasyafarasya].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OqVnUTOel9W48rzP0VmUfvkZ43Y=/0x0:1080x608/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5401013/original/058481200_1762154715-SnapInsta.to_572802011_18541861090004502_6731982056297577983_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5395367/original/014527000_1761705838-FIMELA_FASHION_-_BLUSH_ELEGANCE_TO_SCULPTED_GRACE__IG_FEED_ls__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5231281/original/035535800_1748077534-WhatsApp_Image_2025-05-24_at_4.02.19_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5139252/original/087217400_1740073376-WhatsApp_Image_2025-02-20_at_20.25.07_948b06da.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449484/original/002213100_1766064996-KPK_segel_ruang_Bupati_Bekasi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449480/original/029142300_1766063506-Ayah_Prada_Lucky_Namo__Pelda_Chrestian_Namo.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4317579/original/035812000_1675846348-5cce7248-6d36-43e1-b73a-2d7bf7bee282.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5403280/original/021285400_1762322691-ipul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449389/original/028860600_1766057744-konpers_gelar_perkara_khusus_kasus_ijazah_palsu_Jokowi.jpg)
![Yuk, simak rekomendasi menu clean eating yang low budget dan mudah dibuat! [Dok/freepik.com]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/RdAEFdzNT5QrQ3igWhMu0VdWx9c=/260x125/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5365178/original/040753200_1759141335-smiling-woman-holding-glass-bowl-with-salad-2.jpg)
![Di konser Encore Korea Selatannya, G Dragon tampil mengenakan setelan jas putih dari jas dan celana yang memiliki aksen hitam. Dipadukan inner kemeja putih. [Dok. CHANEL]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/2LgF-38CXJBEsCOwPv-LMKr0c9o=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449196/original/024699400_1766050332-IMG_2604_1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5309451/original/088618600_1754626917-Depositphotos_571793940_XL.jpg)
![Wulan Guritno dan ketiga anaknya yang kini sudah dewasa dan remaja. [@wulanguritno]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/AQiB5CLlG6wCMa-TIIzUHpqbTLk=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5449166/original/044337100_1766049610-IMG_2577.jpeg)