Advertisement
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2163008/original/020227100_1525666074-152566607427049yenniwahid.jpg) Setelah sukses terpilih sebagai Ketua Umum PKB, masih ada kegelisahan yang masih mengganjal di diri Yenny. Dalam sebuah wawancara tentang PKB, Yenny memandang bahwa PKB didirikan oleh Gus Dur seperti sebuah rumah. Dinding dulu, beton, jendela, pintu, lantas ketika telah jadi seperti dicuri orang.
Setelah sukses terpilih sebagai Ketua Umum PKB, masih ada kegelisahan yang masih mengganjal di diri Yenny. Dalam sebuah wawancara tentang PKB, Yenny memandang bahwa PKB didirikan oleh Gus Dur seperti sebuah rumah. Dinding dulu, beton, jendela, pintu, lantas ketika telah jadi seperti dicuri orang.
“Konflik di tubuh PKB itu awalnya berangkat dari perbedaan nilai. Gus Dur mengajarkan pada kami, terutama pada kader-kader PKB yang bertahan di PKB Gus Dur, untuk mendahulukan idealisme. Namun, sebagian teman-teman mungkin tidak sabar, sehingga buat mereka jabatan itu penting sekali, posisi di pemerintahan misalnya, itu penting sekali. Gus Dur padahal di sisi lain mengatakan bukan posisinya, tapi nilainya yang harus kami kejar, pembelaan terhadap masyarakatnya yang harus kami dahulukan. Nah, itu sebagian teman-teman nggak sabar. Ini menurut saya juga adalah sebuah saringan-saringan, ujian-ujian. Yang namanya dunia politik, ujiannya memang seperti itu.”
Pemecatan Gus Dur dari hierarki PKB menyisakan segurat luka di hati Yenny. Dan, andaikan bisa, ia ingin mengubah sejarah itu.
Advertisement
“Dalam sejarah PKB, Gus Dur diberhentikan. Saya tidak ingin itu terjadi. Itu harus dibersihkan dulu. Sama dulu Gus Dur pernah dilengserkan. Para pelaku pelengserannya kemudian menyesal, bahkan minta maaf ke Gus Dur, tapi sejarah masih mencatat seperti itu. Demikian juga dengan PKB, Gus Dur pernah diberhentikan. Lagi-lagi saya tidak ingin sejarahnya seperti itu. Kalau bisa Gus Dur dikembalikan lagi posisinya secara legal sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, sejarahnya di-clear-kan lagi. Saya nggak minta posisi, silakan, monggo. Saya nggak mau apapun, yang penting itu saja.”
Wahid Institute ia dirikan karena gelisah. Bukan karena gelisah tidak bisa berkuasa, tapi karena ia merasa tidak seberani ayahnya.
“Ketika saya mendirikan Wahid Institute, berangkat dari sebuah kegelisahan. Waktu itu saya baru pulang dari Amerika dan kemudian saya berpikir, ini Bapak sudah sakit-sakitan, kalau kemudian pergi, saya akan menggantikan posisi Beliau. Saya sadar diri, tidak mempunyai kemampuan, kepintaran, keberanian Beliau. Semuanya saya nggak punya. Sehingga harus didukung oleh sebuah sistem dan institusi. Karena itu, saya memutuskan untuk membentuk Wahid Institute dan di situlah kami menaungi banyak sekali aktivis, rata-rata muda, yang pikirannya sama seperti Gus Dur. Isu kemanusiaan yang menjadi salah satu fokus kami. Kami punya program beasiswa, namanya Beasiswa Riyanto. Riyanto ini adalah anggota Banser yang meninggal ketika menjaga gereja pada tahun 2000. Pada waktu itu ada gejolak politik dimana gereja-gereja diancam dan kemudian dikirimi parsel-parsel berisi bom. Ini memang upaya untuk membuat kestabilan politik kisruh. Gus Dur memerintahkan kepada anggota Banser untuk membantu polisi mengamankan gereja. Riyanto termasuk anak yang pergi mengamankan. Sebetulnya dia sudah capek setelah pulang kerja, tapi karena yang menyuruh Gus Dur, dia berangkat. Sampai di gereja, dia menemukan bungkusan yang mencurigakan, diambil, dibuang tapi nggak sampai jauh, begitu dia lari untuk ambil bungkusan itu - untuk dimusnahkan atau diamankan - ternyata meledak. Inilah namanya jihad yang sesungguhnya. Jihad untuk membiarkan semua manusia beribadah sesuai keyakinannya. Untuk menghormati heroisme itu, kami menciptakan Beasiswa Riyanto. Karena bagi kami, Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang menaungi seluruh semesta yang membawa kedamaian dan pesan toleransi ke semua.”
Tidak ada satu kekuasaan pun yang begitu berharga sehingga harus dipertahankan dengan pertumpahan darah.
“Saya ingat betul ketika Bapak akan lengser, pendukung-pendukung fanatik Beliau kan banyak sekali, mau datang ke Jakarta, bukan sekadar demo, bahkan mereka pamit kepada keluarganya untuk Jihad buat Gus Dur. Rela mati, karena bagi mereka ini adalah jalan menuju surga. Sampai di Jakarta, disuruh pulang lagi sama Gus Dur, kalau mau demo tapi demo yang damai, nggak boleh merusak. Di situlah saya mau nangis ketika melihat itu, karena kalau saja Beliau mau melakukan perusakan-perusakan, kekuatan itu bisa dimanfaatkan. Venezuela sampai sekarang bertahan dengan cara itu. Dulu Mbak Mega dengan PDI juga pernah membumihanguskan Solo dan Bali, dan itu membuat tekanan politik yang sangat besar di Indonesia. Artinya bahwa, bisa saja proses politik itu ditahan, sehingga Beliau tidak jadi dilengserkan, itu sangat mungkin. Tapi, banyak orang yang tidak berdosa yang jadi korban. Dan Beliau memilih untuk tidak melakukan itu. Itu buat saya luar biasa sekali. Dan, kemudian ternyata Beliau walau di luar sistem, tidak lagi duduk di kursi kekuasaan, tapi kekuasaan yang dia punya adalah kekuasaan informal. Kekuasaan formal tidak Beliau punyai, tetapi karena karakter Beliau luar biasa; modal intelektual, keberanian, dan lain sebagainya, maka Beliau menjadi pemimpin informal yang juga sama efektifnya.”
Dan rasanya belum lengkap bila tidak menanyakan soal FPI kepadanya...
FPI, dari penelitian yang kami lakukan, mereka itu melakukan begitu banyak tindakan kekerasan. Bahkan kalau dikuantifikasi, hampir setiap 10 hari sekali mereka melakukan tindakan kekerasan, ini di tahun 2010 saja. Jadi, luar biasa pembiaran yang dilakukan terhadap tingkah polah seperti itu. Ini seharusnya tidak boleh ditolerir,oleh kami semua, bukan cuma oleh negara, tapi terutama instrumen konstitusi adalah negara, aparat keamanan. Merekalah garda terdepan untuk berhadap-hadapan dengan semua ormas yang anarkis, bukan cuma FPI. FPI kebetulan karena namanya saja. Kalau dibilang FPI Front Pembela Islam, saya juga pembela Islam, tapi Islam yang seperti apa? Islam yang sejuk, Islam yang damai, itu yang saya yakini, bukan Islam yang merusak.
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2163009/original/070648900_1525666074-152566607484704yenny-wahid.jpg)
Selesai berbicara tentang politik, Yenny menyilahkan kami untuk pindah mengobrol di bagian belakang rumahnya yang asi, berdekatan dengan kolam renang favoritnya dan pohon besar rindang yang membuat rumah puteri kedua Gus Dur ini semakin nyaman.
Kepergian Gus Dur di Desember 2009 adalah titik balik hidupnya. Dan setelah Beliau sudah pergi, baru ia mengingat kembali tanda-tanda yang mengisyaratkan kepergian ayahnya.
“Kalau tanda-tanda sebetulnya banyak, cuma sebagai anak dan keluarga, kami tidak mau mengakui tanda-tanda itu sampai ketika Beliau sudah pergi. In denial lah kira-kira. Tapi tanda-tandanya banyak yang mengisyaratkan Bapak akan pergi. Setahun sebelumnya atau awal 2009, Bapak kan sedang sakit. Terus kemudian saya tanya waktu ngobrol, tahu-tahu Bapak bilang ”Ah nggak apa-apa nak, nanti akhir tahun juga sudah selesai,”. Saya deg juga waktu itu, cuma saya mikir “Ah, saya nggak mau mikir kaya gitu. Jangan-jangan itu soal politik, mungkin krisis atau konflik selesai,”. Tapi ketika Bapak sudah pergi, baru teringat semuanya lagi. Bapak sudah ngasih tanda-tanda. Kemudian, seminggu sebelum beliau wafat, Beliau pergi ke Jombang, di sana ketemu saudara sepupunya, beliau mengatakan, “Dek, aku minggu depan ke sini lagi. Tunggu aku ya di sini di deket makamnya Mbah,”. Ya memang betul, seminggu kemudian kami bawa Beliau ke Jombang dalam keadaan sudah meninggal dan dimakamkan di dekat makam Mbahnya Bapak. Saya sebagai anak termasuk agak cengeng. Memang ketergantungan saya kepada Bapak besar sekali secara emosional. Karena memang, beberapa tahun belakangan sampai Bapak wafat, saya banyak sekali meluangkan waktu bersama Bapak. Dan mungkin di situ ketika Bapak sudah nggak ada, jadi ada kehilangan yang sangat mendalam. Banyak sekali memori yang membuat sangat sedih. Apalagi anak saya nggak sempat digendong oleh mbah-nya.”
Ia yang mengubah Gus Dur menjadi penyayang.
“Kenangan yang paling mengesankan terjadi jauh sebelum Bapak menjadi Presiden, yaitu ketika saya SMA. Bapak saya itu kan dari kultur masyarakat Jawa, pesantren pula, dimana kaku dalam mengekspresikan kasih sayangnya. Saya melihat teman-teman saya kalau sama bapaknya gelendotan, sama bapakku nggak bisa nih, Bapak kaku gitu ya. Apalagi biasanya antara laki-laki dan perempuan ada jarak kalau dalam pesantren. Tapi saya ingin banget (gelendotan), kemudian berpikir Bapak nggak akan berubah, harus aku sendiri yang memulai. Suatu hari kami lagi duduk-duduk di sofa kaya’ gini (posisi duduk AE dan Yenny Wahid), kemudian saya duduk di sebelah Bapak, trus saya giniin (peluk) Bapak. Bapak badannya langsung tegang, bingung, diam. Saya juga bingung habis ini mau ngapain. Kami duduk berdua begini diam aja, lima menit Bapak tegang, tapi saya bertahan dengan segala kebingungan itu, lama-lama Bapak jadi lemes badannya, rileks lagi, terus biasa. Sejak saat itu, barrier di antara kami cair. Saya mau gelendotan atau apa nggak masalah. Bapak lebih memahami bahwa anaknya agak-agak ngeyel, hahaha...”
Ia adalah orang yang tenang, tapi bisa panik saat tas makeup-nya ketinggalan dan nggak pakai maskara.
Hahaha, itu dulu sebelum menikah. Sekarang nggak kepikir, yang penting jangan botol ASI anak yang ketinggalan. Kecantikan yang paling utama buat saya adalah ketika seseorang menjadi hidup. Ketika seorang menjadi hidup, kecantikan akan keluar dan menjadi hidup ketika dia menemukan sebuah passion, sebuah hal yang membuat dia bersemangat, mengalahkan semua hal dalam hidupnya, sehingga dia nggak mikir lagi soal pernak-pernik kecil. Itu kecantikan utama akan keluar, yang dikatakan inner beauty dan lain sebagainya. Semua yang menempel hanya menyempurnakan.
Rumahnya ia buka selebar-lebarnya untuk tempat nongkrong segala kalangan.
Saya dan suami kebetulan berangkat dari komunitas yang rileks, komunitas NU apalagi. Semuanya, budayawan, pematung, perupa, wartawan apalagi, semua kami terima, kemudian aktivis politik, ngobrol sampai jam 3-4 pagi, itu biasa. Ketika bertukar pikiran, kemudian ide-ide mengalir, itu membuat hidup bersemangat, menjadi tidak statis. Termasuk ritual di rumah ini yang selalu menceburkan siapa pun ke kolam renang sebelum mereka pulang. Setiap malam kami sedia sarung dan kaos, itu pasti, dan handuk banyak. Karena, setiap tamu harus melewati ritual diceburin ke kolam renang, dia mau atau tidak mau. Pernah ada penulis biografi Gus Dur, orang Australia, saking pasrahnya karena tahu konsekuensinya seperti itu, dia copot bajunya semua dan ganti sarung, baru nyebur dengan sukarela.”
Advertisement
Next
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2163010/original/011409100_1525666075-152566607519008yenny2.jpg)
Saat break syuting, Yenny menyempatkan menggendong puteri tunggalnya, Maica Aurora Madhura, dan mengatakan bahwa anaknya itu adalah calon anak yang akan memerintah orangtuanya. Dan seketika perhatian orang-orang di ruangan tersebut tersedot kepada anak perempuan cantik bermata besar itu.
Bukan memutuskan untuk menikah, tapi ia akhirnya mendapatkan jodoh.
“Memang jodoh itu perkara susah-susah gampang. Saya merasa memang persoalan jodoh itu sudah garis tangan dari Yang Di Atas. Dan, banyak intervensi dari “langit” melalui orangtua. Dalam artian, doa orangtua sangat mengiringi proses saya bertemu dengan suami. Jadi salah satunya ketika saya diberi nasihat oleh seorang ulama, minum air cucian kaki ibu saya. Ya sudah, saya lakukan. Eh, nggak berapa lama ketemu calon suami saya, dan yang lebih lucu, ternyata dia melakukan hal yang sama, tapi kami sama-sama nggak tau. Baru setelah dekat tahu. Ini sesuai dengan ramalan yang mengatakan saya akan menikah di umur 29 atau 35 tahun.”
Mendapatkan Maica adalah prestasi yang paling tinggi dari semua prestasi yang mungkin pernah ia capai.
”Dalam hidup, saya mendapatkan satu dua penghargaan atau prestasi, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Maica. Dengan anter dia ke sekolah, melatih dia berenang, dia duduk pertama kali, itu sebuah kebahagiaan yang betul-betul besar. Hal yang ingin saya contoh dari Bapak Ibu saya dalam mendidik anak adalah bahwa Beliau menanamkan kecintaan pada buku. Kemudian, ada rasa curiosity atau keingintahuan yang dipupuk, anak bebas bertanya, bebas mencari tahu ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya contoh. Kalau yang nggak ingin saya contoh apa ya? Kayak-nya, so far sih, banyak yang positif semua. Mungkin satu hal yang nggak ingin saya lakukan adalah kalau orangtua zaman dulu kan strict banget. Kalau nggak mau apa terus dicubit. Dan, sebisa mungkin Maica cari dunia yang lain saja, jangan politik, karena bebannya berat sekali.”
Formula sukses untuk keluarga bahagia di matanya.
“Kebahagiaan paling hakiki menjadi seorang istri adalah ketika kami bisa hidup berdampingan berdua, menjalani hidup tanpa ekspektasi yang terlalu berlebihan, ada pengertian, semuanya tulus. Menurut saya dalam sebuah keluarga yang sukses ketika formulanya tepat. Kalau biasanya satu tambah satu sama dengan dua, sukses adalah ketika satu tambah satu bukan lagi sama dengan dua, tapi tiga, empat, lima, enam. Jadi, potensi kami malah semakin berkembang. Suami mendukung, istri juga mendukung, dua-duanya tidak ada pengekangan, saling memberikan support. Saya bersyukur suami saya amat sangat suportif. Dia hanya mengingatkan jangan sampai kecapean. “Ayo cepet tidur, besok kamu pesawat jam berapa?” biasanya dia ngomong gitu. Nggak ada mengekang harus begini harus begitu. Santai. Saya beruntung.”
Obrolan beralih ke balkon mencakup teras yang terletak di lantai dua. Yenny yang berganti baju dengan setelan lebih kasual, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lebih santai.
Gus Dur menjadi panutannya untuk bergaul dengan banyak orang.
“Saya mencontoh Gus Dur saja. Beliau bisa diterima oleh semua kalangan karena Beliau bersikap apa adanya, jadi diri sendiri saja, rileks, santai, nggak usah sok jaim, biasa aja, jadi mau kemana aja nggak ada masalah. Kalau mau jaim, dari awal kami kan harus terus mempertahankan jaim itu, dan itu capek.”
Di antara masa lalu dan masa kini Yenny.
“Dulu saya suka dugem, kalau sekarang paling sama suami nonton atau makan. Dulu suka datang ke acara musik, kalau sekarang sama suami main gitar atau teman-temannya pada datang ke rumah. Dulu saya juga suka Salsa waktu Cafe Salsa baru pertama kali muncul di Jakarta. Bersama teman-teman cewek, kalau fitness sudah capek, supaya kurus sekaligus fun, Salsa jadi pilihan saya, karena dinamis, seminggu minimal dua kali. Untuk sekarang, kebetulan saya dan suami memang dasarnya adalah orang rumahan, jadi ketika sudah ketemu komunitasnya, klop, mendingan di rumah.”
Masa muda, saatnya melakukan banyak hal gila.
“Hal tergila yang saya lakukan berkaitan dengan profesi, salah satunya ketika saya jadi wartawan dan liputan di Timor Timur tahun 1997-1999. Kalau sekarang disuruh lakuin itu, belum tentu mau lagi. Di situ kemungkinan kehilangan nyawa besar sekali, cuma waktu umur-umur segitu nggak dipikir. Pernah juga saya terperangkap dalam proses baku tembak antara kelompok Pro Kemerdekaan dan Pro Integrasi, itu menjelang dan setelah referendum. Saya terperangkap dengan teman wartawan dari CNN, kami lari di antara orang tembak-tembakan. Kemudian, saat proses reformasi saya meliput dan saya menjadi korban intimidasi oleh pria berseragam dari instansi tertentu yang menodongkan pistol ke dahi saya. Ya seperti begitu. Itu hal tergila yang pernah saya lakukan.”
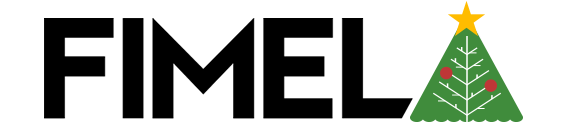

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055890/original/010999200_1734499535-HIGHLIGHT_FIMELA_DAY___IG_Feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055880/original/002353200_1734499127-HIGHLIGHT_day_3__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055871/original/038409700_1734498725-HIGHLIGHT_day_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055859/original/051857100_1734498130-HIGHLIGHT_day_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5036378/original/013812700_1733385978-LINE_UP_FIMELA_DAY__LANDSCAPE_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5032977/original/073652000_1733197790-FOTO_1.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4993686/original/004273900_1730894148-Screenshot_2024-11-06_183841.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5044050/original/083856400_1733829025-pexels-fotios-photos-1161682.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041610/original/060088700_1733732335-pexels-august-de-richelieu-4259707.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041651/original/052511200_1733733345-pexels-fauxels-3184195.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5038491/original/043304100_1733466445-pexels-mart-production-7491188.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035957/original/053181400_1733369335-pexels-naimbic-1618925.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4956917/original/029939300_1727700981-danilla1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874794/original/056293100_1719334724-0E6A6448-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4874912/original/075484000_1719364615-0E6A6414-01.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918193/original/031121600_1723633856-Fimela_Fame_Story_-_INSECURE_ITU_MANUSIAWI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033038/original/000687200_1733198738-Snapinsta.app_468983269_422604517585625_3930891875784389755_n_1080.jpg)
![Seniman Galuh Anindita menciptakan aksesori yang diberi nama Mahija. [dok. Galuh Anindita]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WTXk5rkAsLcLcYIG39cRqwfZn1A=/0x1157:2624x2636/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5035276/original/041670100_1733312960-FOTO_PROFIL_SENIMAN_-_GALUH_ANINDITA_WARDANA.JPG)
![Tertarik menjadi fashion content creator? Yuk, intip perjalanan dan tips dari Nayla Azmi yang bisa jadi inspirasi. [@nayazmi].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6WON4f2PkNzlpypg1TlGJkgWh3I=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989661/original/023402000_1730689725-Snapinsta.app_361932262_18371303764043247_8459029759776216861_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986993/original/047294000_1730391129-Snapinsta.app_449371914_489107260348112_6233073337143813000_n_1080.jpg)
![Vania Theola Konten Kreator Dengan Iron Limb. [@vaniatheolaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/KLFl12PO_uZK3GtnVGgBycTLC5w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4986876/original/029781800_1730379813-WhatsApp_Image_2024-10-16_at_21.02.22.jpeg)
![Ingin hadirkan kesan modern, paduan area mata dominan juga bisa diimbangi dengan riasan bibir yang lebih minimalis. Gaya ini akan sempurnakan tampilan yang memikat di hari raya. [Foto: Instagram/ Tasya Farasya]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RxVQ20Y0uaYrguFkZvpvaQ2gbZ4=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792011/original/006533600_1712053715-Screen_Shot_2024-04-02_at_16.48.37.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5069846/original/010151000_1735373948-FIMELA_FASHION_-_Luxury_in_Every_Stitch_with_MCM__IG_feed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5058958/original/065333600_1734685101-IMG_4392.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034833/original/043480800_1733296555-FIMELA_FASHION_-_BOUNDLESS_BEAUTY_WITH_WEEKEND_MAXMARA__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5033477/original/089964900_1733210907-IMG_8172__1_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016705/original/043770800_1732230233-PERSONAL_STYLE_-_Febby_Rastanty__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999682/original/032662400_1731301929-Screen_Shot_2024-11-11_at_11.54.17.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012134/original/044919600_1732014088-Screenshot_2024-11-19_155938.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4977924/original/015611700_1729681356-Screenshot_2024-10-23_175531.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4954877/original/041297300_1727434824-Screenshot_2024-09-27_174524.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5076410/original/027199600_1735880672-IMG_1971.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5076380/original/046077400_1735878995-IMG_1882.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5076369/original/036697100_1735878336-IMG_2044.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4818719/original/066152700_1714567587-01d7210e-4e50-4be0-89e3-97f23b04ce2e.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5049624/original/030339300_1734072037-DSC00943.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2735684/original/091845500_1550825020-kimchi-709607_1920.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012134/original/044919600_1732014088-Screenshot_2024-11-19_155938.jpg)