Fimela.com, Jakarta Punya pengalaman suka duka dalam perjalanan kariermu? Memiliki tips-tips atau kisah jatuh bangun demi mencapai kesuksesan dalam bidang pekerjaan yang dipilih? Baik sebagai pegawai atau pekerja lepas, kita pasti punya berbagai cerita tak terlupakan dalam usaha kita merintis dan membangun karier. Seperti kisah Sahabat Fimela yang diikutsertakan dalam Lomba Menulis April Fimela: Ceritakan Suka Duka Perjalanan Kariermu ini.
***
Oleh: Sri M. - Surakarta
Meniti Karier adalah Menjalani Setiap Ketetapan dan Perjalanan Tanpa Putus Asa
Melihat seseorang yang sukses dalam berkarier pastilah ada keinginan untuk menuju ke arah itu. Dengan menghasilkan ekonomi yang kuat dan juga jabatan yang disegani pastilah akan membuat iri semua orang. Terlebih jika yang mendapatkannya adalah sosok wanita. Wanita dengan karier yang sukses mungkin masih menjadi tabu. Karena mereka dianggap menghilangkan fitrah mereka sebagai perempuan. Wanita karier dianggap telah melupakan jati dirinya sebagai perempuan yang seharusnya tinggal di rumah dan menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anaknya.
Namun kenyataannya zaman sudah berubah. Meski di era lalu sudah banyak kaum perempuan yang menunjukkan tajinya, namun seiring berkembangnya waktu, kini kedudukan wanita sudah bisa sebanding bahkan melebihi kaum laki-laki. Meski demikian, untuk meraih sebuah karier yang tinggi ternyata tidak melulu diperlukan intelektual yang tinggi pula. Semua wanita bisa meraih karier tertinggi dalam hidup mereka asal mereka mempunyai dua hal paling mendasar. Niat dan tekad.
Reuni beberapa waktu lalu ternyata membuat pikiranku terbuka. Bahwa ternyata aku dengan masa lalu pendidikan yang buruk bukan menjadi pengahalang untukku menyetarakan diri sebanding dengan teman-temanku yang sudah mempunyai karier cemerlang di sebuah instansi atau di atas usahanya sendiri.
Tak Bisa Melanjutkan Sekolah
Aku yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD tidak membuatku patah semangat dan rendah diri. Saat itu perhatian orang tuaku fokus kepada kakakku yang mempunyai keterbelakangan mental dan lebih mementingkan pendidikan ketiga adikku karena dinilai mereka lebih membutuhkan. Aku maklum, sebagai wanita, di masa itu bukan tujuan utama untukku meraih pendidikan yang layak. Dengan kondisi ekonomi orangtua yang pas-pasan dan timbulnya ungkapan bahwa wanita tidak wajib untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena akhirnya wanita akan berakhir di dapur, maka aku menjadi salah satu korban pemikiran orang tua yang kuno.
Saat itu ada rasa sedih yang kurasakan. Melihat teman-temanku memakai baju putih biru dan berhasil melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan aku, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan ijazah sekolah dasarku. Tapi yang pasti aku harus bekerja. Karena aku tidak ingin berpangku tangan dan membebani kedua orangtuaku. Selain itu kakak dan adikku juga masih butuh biaya hidup. Kalau bukan aku yang membantu meringankan beban orangtua lalu siapa lagi?
Aku berpikir pekerjaan seperti apa yang akan aku dapatkan dengan modal ijazah SD. Walaupun pada saat itu lapangan pekerjaan masih sangat luas dan akan dengan mudahnya untuk mendapatkan, namun tanpa ditambahi ketrampilan akan menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalaupun memperoleh pekerjaan paling juga sebagai penjaga toko atau PRT.
Suatu kali aku memutuskan untuk menjadi PRT. Namun karena uang yang kudapat kurang banyak, akhirnya aku mengambil kerja tambahan. Sepulang aku menjadi PRT, aku membantu berjualan di pasar. Hasil uang yang kudapat kuberikan semua pada Ibuku untuk memenuhi kekurangan biaya hidup yang beliau tanggung.
Ikut Kursus
Suatu hari Ibuku bertanya padaku apakah aku ingin melanjutkan sekolah. Jujur aku sangat ingin. Tapi dengan kemampuan ekonomi Bapak dan Ibu akhirnya aku mengurungkan niat itu dan menguburnya. Tapi pada saat itu Ibu bilang padaku bahwa beliau sanggup membiayaiku melanjutkan sekolah meski nanti hanya sebatas SMP saja. Aku mulai berpikir panjang untuk sebuah keputusan. Hingga akhirnya aku memutuskan meminta Ibu untuk membiayaiku kursus menjahit saja.
Bagiku kursus tidak akan menyita banyak waktu dan aku masih punya paruh waktu untuk kerja sampingan dan uang yang kudapat bisa untuk menambahi biaya kursus. Dan jika aku selesai kursus nanti aku bisa mendapatkan ketrampilan yang bisa kugunakan untuk melamar pekerjaan di pabrik garmen. Dan tentunya gaji yang kudapat akan lebih besar sehingga aku bisa lebih meringankan orangtuaku.
Selesai dari pendidikan kursus, aku mencari peruntungan di pabrik. Mungkin benar bahwa aku mendapatkan gaji yang lumayan dibanding aku menjadi PRT atau berjualan di pasar. Namun kenyataannya, untuk mendapatkan gaji sebanyak itu aku juga harus mengorbankan hal yang lebih berat dibandingkan dengan pekerjaanku terdahulu.
Sejak awal kerja aku sudah mendapatkan perilaku kurang mengenakkan dari senior-seniorku. Ditambah lagi dengan usia yang masih sangat belia aku semakin menjadi bahan ejekan dan diperlakukan semena-mena. Dan yang tidak aku suka mereka selalu mengatasnamakan atasan untuk menjajahku. Padahal kalau dinilai secara logika, atasan tidak mungkin memerintah seseorang untuk semena-mena padaku tanpa alasan yang jelas. Hal-hal itulah yang membuatku merasa tertekan dan sakit hati.
Aku juga mulai sering menyembunyikan air mata yang sebenarnya sangat ingin kuteteskan. Semua itu demi orangtuaku. Agar mereka tidak bertambah beban hanya karena memikirkanku. Aku mencoba bertahan selama tiga bulan sebelum aku memutuskan untuk pindah kerja. Aku hanya berpikir jika aku terlalu lama bekerja di pabrik, ketidaknyamanan akan membuatku semakin tersiksa.
Tak lama setelah aku keluar dari pabrik, aku diterima di pabrik konveksi rumahan. Memang gajinya tidak sebesar yang kuterima dari pekerjaan sebelumnya, namun aku mendapatkan kenyamanan di tempat baruku ini. Bos yang biasa kupanggil “Tacik” itu memang galak, namun dia sangat baik hati padaku.
Belajar dari Nol
Saat aku masih sangat baru menjadi pegawainya, dia tidak segan untuk mengajariku dari nol. Dari bagaimana membuat pola sampai menjadi sebuah baju. Dia tidak segan-segan memberikan ilmunya padaku. Sesekali aku dimarahinya jika ada kesalahan, namun marahnya itu sebagai tanda bahwa dia perhatian dan ingin membuat anak buahnya bisa berkembang. Dia lakukan itu pada semua karyawannya. Dan jika karyawannya sudah ada yang mahir lalu ingin membuka usaha sendiri, dia akan memberi izin untuk mandiri.
Aku banyak sekali mengambil ilmu dari tempat kerjaku yang sekarang. Aku menjadi semakin mahir dalam fashion. Akhirnya, menginjak usiaku yang ke-20, seorang pria dari desa menikahiku. Namun aku masih diberi kesempatan suamiku untuk tetap bekerja di konveksi. Namun saat aku hamil dan usia kandunganku menginjak delapan bulan, kuakui aku sepertinya sudah tidak sanggup untuk bolak balik dari rumah ke tempat kerja. Terlebih lagi saat itu aku harus mengayuh sepeda untuk menuju ke sana. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat itu pemilik konveksi sebenarnya masih sangat ingin aku bekerja di sana. Dia sudah sangat cocok denganku dan menyukai pekerjaanku. Namun keputusan tetap keputusan. Selain itu aku juga harus bertanggung jawab untuk merawat anakku.
Setelah kelahiran anakku aku sempat berpikir apa yang akan aku lakukan jika anakku besar nanti. Apakah aku akan menjadi pengangguran dan membebani suamiku kali ini. Tidak. Aku harus bekerja. Namun ternyata ada dilema juga. Siapa yang akan sudi menerimaku yang sudah punya anak ini. Yang mereka butuhkan pasti pekerja yang masih single.
Beberapa tahun kemudian saat anakku sudah masuk SD aku mencoba membuka usaha jahit di rumah. Aku membeli sebuah mesin jahit dari hasil tabungan yang setiap bulan aku sisihkan. Awalnya memang sulit untuk mencari konsumen yang mau membuatkan bajunya di tempatku. Terpaksa saat itu aku hanya menerima permak baju saja. Begitu terus sampai setahun lamanya.
Hingga suatu saat pemilik konveksi yang dulu pernah menjadi bosku memberikanku pekerjaan untuk membuatkan lima setel baju. Alhamdulillah, konsumen pertamaku puas dan kemudian kembali lagi ke tempatku untuk membuatkan baju. Sebenarnya aku tidak enak dengan mantan bosku. Aku takut dianggap mengambil pekerjaannya. Namun ternyata di luar dugaan, mantan bosku itu tidak mempermasalahkan.
Membangun Usaha Sendiri
Satu tahun berjalan dan baju buatanku mulai dikenal dari mulut ke mulut. Ya begitulah model promosi di era 80an. Tidak seperti zaman sekarang yang dengan mudahnya dipromosikan lewat media sosial. Lama kelamaan semakin banyak orang yang ingin menjajal kemampuanku. Namun saat itu kuakui aku masih kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan mesin. Aku masih harus bolak balik ke tempat mantan bosku untuk jahitan khusus dan lubang baju. Kupikir karena lama-lama aku lelah, aku mencoba memberanikan diri untuk meminjam uang pada mantan bosku untuk membeli mesin-mesin khusus itu.
Dengan alat-alat yang sudah mulai lengkap di rumah, semakin banyak juga orang yang datang ke rumahku untuk membuatkan baju. Aku mulai menghasilkan uang yang lebih yang akhirnya bisa kugunakan untuk melunasi hutang, membeli rumah sendiri, membiayai anak semata wayangku dan juga menguliahkan kedua adikku.
Usaha jahit rumahan yang kutekuni sampai kini sudah kujalani 30an tahun. Selama itu jatuh bangun kerasnya menjalani usaha hingga menjadi sekuat sekarang sudah kulalui. Jika ingin lebih berkembang, sebenarnya aku bisa menjadi desainer dan membangun sebuah butik. Namun yang aku pikirkan adalah, menjadi seperti saat ini, dikenal dan dicari banyak orang aku sudah sangat bersyukur. Menjadikan orang mengakui dan memakai hasil karyaku aku sudah puas.
Sepertinya aku sudah mendapatkan karier tertinggiku. Bagiku dengan menjadi penjahit rumahan aku telah banyak membantu orang-orang di kalangan menengah ke bawah untuk tetap bisa tampil fashionable tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Selain itu karier tertinggiku selanjutnya adalah bahwa aku bisa tetap menjadi bagian terpenting bagi keluargaku tanpa harus meninggalkan dan mengabaikan mereka. Nyatanya, pendidikan tinggi tidak selalu menjamin seseorang untuk mencapai karier tertingginya. Karena yang terpenting adalah ketekunan kita untuk menjalani setiap ketetapan dan perjalanan tanpa putus asa.
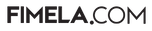
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2785392/original/052251500_1555992341-penjahit_HL.jpg)